Latest Post
02.46
LATAR BELAKANG LAHIRNYA NAHDLATUL ULAMA (NU)
Diterbit Oleh Unknown pada Kamis, 22 Oktober 201502.46
Sebagai warga Indonesia khususnya warga NU haruslah mengetahui sejarah Bangsa
ini. Bagaimana NU dalam peranannya yang begitu besar dalam memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia, mempertahankan keutuhan NKRI dan bagaimana latar
belakang lahirnya ormas terbesar di dunia Nahdlatul Ulama (NU) ini lahir.
Silakan disimak dan dihayati mudah-mudahan menjadi pijakan bagi kita untuk lebih
menghargai jasa-jasa para Pahlawan.
Ada tiga alasan yang melatarbelakangi lahirnya Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926:
1. Motif Agama.
Bahwa Nahdlatul Ulama lahir atas semangat menegakkan dan mempertahankan Agama
Allah di Nusantara, meneruskan perjuangan Wali Songo. Terlebih Belanda-Portugal
tidak hanya menjajah Nusantara, tapi juga menyebarkan agama Kristen-Katolik
dengan sangat gencarnya. Mereka membawa para misionaris-misionaris Kristiani ke
berbagai wilayah.
2. Motif Nasionalisme.
NU lahir karena niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama
dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama
Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni Kebangkitan Para Ulama. NU pimpinan Hadhratus
Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sangat nasionalis. Sebelum RI merdeka, para pemuda di
berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong
Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya.
Tapi, kiai-kiai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis.
Pada 1924, para pemuda pesantren mendirikan Syubbanul Wathon (Pemuda Tanah
Air). Organisasi pemuda itu kemudian menjadi Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO) yang
salah satu tokohnya adalah pemuda gagah, Muhammad Yusuf (KH. M. Yusuf Hasyim
-Pak Ud).
Selain itu dari rahim NU lahir lasykar-lasykar perjuangan fisik, di kalangan
pemuda muncul lasykar-lasykar Hizbullah (Tentara Allah) dengan panglimanya KH.
Zainul Arifin seorang pemuda kelahiran Barus Sumatra Utara 1909, dan di
kalangan orang tua Sabilillah (Jalan menuju Allah) yang di komandoi KH.
Masykur.
Sejarah mencatat, meski bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan
pada 17 Agustus 1945, 53 hari kemudian NICA (Netherlands Indies Civil
Administration) nyaris mencaplok kedaulatan RI. Pada 25 Oktober 1945, 6.000
tentara Inggris tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pasukan itu dipimpin
Brigadir Jenderal Mallaby, Panglima Brigade ke-49 (India). Penjajah Belanda
yang sudah hengkang pun membonceng tentara sekutu itu.
Praktis, Surabaya genting. Untung, sebelum NICA datang, Soekarno sempat
mengirim utusan menghadap Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari di Pesantren
Tebuireng, Jombang. Melalui utusannya, Soekarno bertanya kepada Hadhratus
Syaikh KH. Hasyim Asy’ari: “Apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela
Allah, membela Islam, atau membela al-Qur'an. Sekali lagi, membela tanah air?”
Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari yang sebelumnya sudah punya fatwa jihad
kemerdekaan bertindak cepat. Dia memerintahkan KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri
Syansuri, dan para Kiyai lain untuk mengumpulkan para Kiyai se-Jawa dan Madura.
Para Kiyai dari Jawa dan Madura itu lantas rapat di Kantor PB Ansor Nahdlatoel
Oelama (ANO), Jalan Bubutan VI/2, Surabaya, dipimpin Kiai Wahab Hasbullah pada
22 Oktober 1945.
Pada 23 Oktober 1945, Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari atas nama Pengurus
Besar NU mendeklarasikan seruan jihad fi sabilillah, yang kemudian dikenal
dengan Resolusi Jihad.
Ada tiga poin penting dalam Resolusi Jihad itu: a) Pertama, setiap muslim –
tua, muda, dan miskin sekalipun- wajib memerangi orang kafir yang merintangi
kemerdekaan Indonesia. b) Kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan
layak disebut syuhada. c) Ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah
dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati.
Jadi, umat Islam wajib hukumnya membela tanah air. Bahkan, haram hukumnya
mundur ketika kita berhadapan dengan penjajah dalam radius 94 km (jarak ini
disesuaikan dengan dibolehkannya Qashar Shalat). Di luar radius itu dianggap
fardhu kifayah (kewajiban kolektif, bukan fardhu ‘ain, kewajiban individu).
Fatwa jihad yang ditulis dengan huruf pegon itu kemudian digelorakan Bung Tomo
lewat radio. Keruan saja, warga Surabaya dan masyarakat Jawa Timur yang
keberagamaannya kuat dan mayoritas NU merasa terbakar semangatnya. Ribuan Kiyai
dan santri dari berbagai daerah -seperti ditulis M.C. Ricklefs (1991), mengalir
ke Surabaya.
Meletuslah peristiwa 10 November 1945 yang dikenang sebagai hari pahlawan. Para
Kiyai dan pendekar tua membentuk barisan pasukan non regular Sabilillah yang
dikomandani oleh KH. Maskur. Para santri dan pemuda berjuang dalam barisan
pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh H. Zainul Arifin. Sementara para Kiyai
sepuh berada di barisan Mujahidin yang dipimpin oleh KH. Wahab Hasbullah.
Perang tak terelakkan sampai akhirnya Brigadir Jenderal Mallaby tewas.
3. Motif Mempertahankan Faham Ahlussunnah wal Jama’ah.
NU lahir untuk membentengi umat Islam khususnya di Indonesia agar tetap teguh
pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah (Para Pengikut Sunnah Nabi, Sahabat
dan Ulama Salaf Pengikut Nabi-Sahabat), sehingga tidak tergiur dengan
ajaran-ajaran baru (tidak dikenal zaman Rasul-Sahabat-Salafus Shaleh/ajaran
ahli bid'ah). Pembawa ajaran-ajaran bid'ah yang sesat (bid'ah madzmumah)
menurut ulama Ahlussunnah wal Jama’ah adalah sebagai berikut:
a) Kaum Khawarij dengan imam/pemimpinnya Abdullah bin Abdul Wahab ar-Rasabi
yang muncul di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib Ra. yang berpendapat bahwa
orang yang berdosa besar adalah kafir, sehingga ciri khas mereka mudah menuduh
orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan ajarannya sebagai kafir. Bahkan
sahabat Ali bin Abi Thalib Ra. pun dicap kafir karena dianggap berdosa besar
mau menerima tawaran tahkim/perdamaian yang diajukan oleh pemberontak Muawiyyah
Ra.
b) Kaum Syi'ah, lebih-lebih setelah munculnya sekte syi'ah Rafidhah dan Ghulat.
Tokoh pendiri Syi'ah adalah Abdullah bin Saba’ seorang Yahudi yang pura-pura
masuk Islam dan menyebarkan ajaran Wishoya, bahwa kepemimpinan setelah Nabi
adalah lewat wasiat Nabi Saw. Dan yang mendapatkan wasiat adalah Ali bin Abi
Thalib Ra. Dan Abu Bakar, Umar dan Utsman termasuk perampok jabatan.
c) Aliran Mu'tazilah yang didirikan oleh seorang tabi'in yang bernama Wasil bin
Atho', ciri ajaran ini adalah menafsirkan al-Qur'an dan kebenaran agama
ukurannya adalah akal manusia, bahkan mereka berpendapat demi sebuah keadilan
Allah harus menciptakan al-manzilah baina al-manzilataini, yakni satu tempat di
antara surga dan neraka sebagai tempat bagi orang-orang gila.
d) Faham Qodariyyah yang pendirinya adalah Ma'bad al-Juhaini dan Ghailan
ad-Dimasyqi keduanya murid Wasil bin Atho' dan keduanya dijatuhi hukuman mati
oleh Gubernur Irak dan Damaskus karena menyebarkan ajaran sesat (bid'ah), ciri
ajarannya adalah manusia berkuasa penuh atas dunia ini, karena tugas Allah
telah selesai dengan diciptakannya dunia, dan bertugas lagi nanti ketika kiamat
datang.
e) Aliran Mujassimah atau kaum Hasyawiyyah ciri aliran ini menjasmanikan Allah
(menyerupakan Allah dengan makhluk) yang diawali dengan menafsirkan al-Qur'an
secara lafdziy dan tidak menerima ta'wil, sehingga sehingga mengartikan
yadullah adalah Tangan Allah. (Lihat Ibnu Hajar al-'Asqolani dalam Fath
al-Baari Juz XX hal. 494). Bahkan mereka sanggup mengatakan, bahwa pada suatu
ketika, kedua mata Allah kesedihan, lalu para malaikat datang menemuiNya dan
Dia (Allah) menangisi (kesedihan) berakibat banjir Nabi Nuh As. sehingga
mataNya menjadi merah, dan ‘Arsy meratap hiba seperti suara pelana baru dan
bahwa Dia melampaui ‘Arsy dalam keadaan melebihi empat jari di segenap sudut.
(Lihat asy-Syahrastani dalam al-Milal wa an-Nihal, hal. 141).
f) Ajaran-ajaran Para Pembaharu Agama Islam (Mujaddid) yang dimulai dari Ibnu
Taimiyyah (661-728 H / 1263-1328 M atau abad ke 7 – 8 H / 13 – 14 M yakni 700
tahun setelah Nabi Saw. wafat atau 500 tahun dari masa Imam asy-Syafi'i).
Beliau mengaku penganut madzhab Hanbali, tapi anehnya beliau justru menjadi
orang pertama yang menentang sistem madzhab. Pemikirannya lalu dilanjutkan
muridnya Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah. Aliran ini kemudian dikenal dengan nama
aliran salafi-salafiyah yang mengaku memurnikan ajaran kembali ke al-Qur'an dan
Hadits, tetapi di sisi lain mereka justru mengingkari banyak hadits-hadits
Shahih (inkarus sunnah). Mereka ingin memberantas bid'ah tetapi pemahaman
tentang bid'ahnya melenceng dari makna bid'ah yang dikehendaki Rasulullah Saw.,
yang dipahami oleh para sahabat dan para ulama salaf Ahlussunnah wal Jama'ah.
Mereka juga membangkitkan kembali penafsiran al-Qur'an-Sunnah secara lafdziy.
Golongan Salafi ini percaya bahwa al-Qur’an dan Sunnah hanya bisa diartikan
secara tekstual (apa adanya teks) atau literal dan tidak ada arti majazi atau
kiasan di dalamnya. Pada kenyataannya terdapat ayat al-Qur’an yang mempunyai
arti harfiah dan ada juga yang mempunyai arti majazi, yang mana kata-kata Allah
Swt. harus diartikan sesuai dengannya. Jika kita tidak dapat membedakan di
antara keduanya maka kita akan menjumpai beberapa kontradiksi yang timbul di
dalam Al-Qur’an. Maka dari itu sangatlah penting untuk memahami masalah
tersebut.
Dengan adanya keyakinan bahwa seluruh kandungan Al-Qur’an dan Sunnah hanya
memiliki makna secara tekstual atau literal dan jauh dari makna majazi atau
kiasan ini, maka akibatnya mereka memberi sifat secara fisik kepada Allah Swt.
(umpama Dia Swt. mempunyai tangan, kaki, mata dan lain-lain seperti
makhlukNya). Mereka juga mengatakan terdapat kursi yang sangat besar (‘Arsy)
dimana Allah Swt. duduk (sehingga Dia membutuhkan ruangan atau tempat untuk
duduk) di atasnya. Terdapat banyak masalah lainnya yang diartikan secara
tekstual. Hal ini telah membuat banyak fitnah di antara ummat Islam, dan inilah
yang paling pokok dari mereka yang membuat berbeda dari madzhab yang lain.
Salafisme ini hanya berjalan atas tiga komposisi yaitu; Syirik, Bid’ah dan
Haram. (Penjelasan rincinya akan dibahas kemudian).
Munculnya Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke 12 H / 18 M, seorang pembaharu
agama (mujaddid) yang lahir di Ayibah lembah Najed (1115-1201 H/1703-1787 M)
yang mengaku sebagai penerus ajaran Salafi Ibnu Taimiyyah dan kemudian
mendirikan madzhab Wahabi-Wahabiyyah. Ia pun mengaku sebagai Ahlussunnah wal
Jama’ah karena meneruskan pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal yang diterjemahkan
oleh Ibnu Taimiyyah, tapi sebagaimana pendahulunya, Muhammad bin Abdul Wahab
dan pengikutnya pun layaknya kaum Khawarij yang mudah mengkafirkan para ulama
yang tidak sejalan dengan dia, bahkan sesama madzhab Hanbali pun ia
mengkafirkanya.
Di sini, kita akan mengemukakan beberapa pengkafiran Muhammad bin Abdul Wahhab
terhadap beberapa tokoh ulama Ahlussunnah yang tidak sejalan dengan pemikiran
sektenya:
• Dalam sebuah surat yang dilayangkan kepada Syeikh Sulaiman bin Sahim –seorang
tokoh madzhab Hanbali pada zamannya– Ia (Muhamad Abdul Wahhab) menuliskan: “Aku
mengingatkan kepadamu bahwa engkau bersama ayahmu telah dengan jelas melakukan
perbuatan kekafiran, syirik dan kemunafikan! Engkau bersama ayahmu siang dan
malam sekuat tenagamu telah berbuat permusuhan terhadap agama ini! Engkau
adalah seorang penentang yang sesat di atas keilmuan. Dengan sengaja melakukan
kekafiran terhadap Islam. Kitab kalian itu menjadi bukti kekafiran kalian!”
(Lihat dalam ad-Durar as-Saniyah jilid 10 hal. 31).
• Dalam sebuah surat yang dilayangkan untuk Ibnu Isa –yang telah melakukan
argumentasi terhadap pemikirannya –Muhammad Abdul Wahhab menvonis sesat para
pakar fikih (fuqoha) secara keseluruhan. Ia (Muhamad Abdul Wahhab) menyatakan:
(Firman Allah); “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka
sebagai Tuhan selain Allah”. Rasul dan para imam setelahnya telah
mengartikannya sebagai ‘Fikih’ dan itu yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai
perbuatan syirik. Mempelajari hal tadi masuk kategori menuhankan hal-hal lain
selain Allah. Aku tidak melihat terdapat perbedaan pendapat para ahli tafsir
dalam masalah ini.” (Lihat dalam ad-Durar as-Saniyah jilid 2 hal. 59).
• Berkaitan dengan Imam Fakhrur Razi –pengarang kitab Tafsir al-Kabir, yang
bermadzhab Syafi’i Asy’ary– ia (Muhamad Abdul Wahhab) mengatakan: “Sesungguhnya
Razi tersebut telah mengarang sebuah kitab yang membenarkan para penyembah
bintang.” (Lihat dalam ad-Durar as-Saniyah jilid 10 hal. 355). Betapa
kedangkalan ilmu Muhamad bin Abdul Wahhab terhadap karya Imam Fakhrur Razi.
Padahal dalam karya tersebut, Imam Fakhrur Razi menjelaskan tentang beberapa
hal yang menjelaskan fungsi gugusan bintang dalam kaitannya dengan fenomena
yang berada di bumi, termasuk berkaitan dengan bidang pertanian. Namun Muhammad
bin Abdul Wahhab dengan keterbatasan ilmu terhadap ilmu perbintangan telah
menvonisnya dengan julukan yang tidak layak, tanpa didasari ilmu yang cukup.
Dari berbagai pernyataan di atas maka jangan kita heran jika Muhammad bin Abdul
Wahhab pun mengkafirkan –serta diikuti oleh para pengikutnya (Wahhabi)–para
pakar teologi (mutakallimin) Ahlusunnah secara keseluruhan (Lihat dalam
ad-Durar as-Saniyah jilid 1 hal. 53), bahkan ia (Muhamad Abdul Wahhab)
mengaku-ngaku bahwa kesesatan para pakar teologi tadi merupakan konsensus
(ijma’) para ulama dengan mencatut nama para ulama seperti adz-Dzahabi, Imam
Daruquthni dan al-Baihaqi.
Tokoh Pembaharu Agama (mujaddid) lain penerus faham salafi Ibnu Taimiyyah
adalah muncul pada abad ke 19 di Afghanistan yang bernama Jamaluddin al-Afghani
(1838-1898). Ajarannya diteruskan oleh muridnya dari Mesir di abad ke 19 – 20 M
yang bernama Muhammad Abduh (1949-1905). Pemikiran Muhammad Abduh menyebar ke
berbagai penjuru dunia lewat tulisannya yang dimuat dalam majalah al-Manar.
Setelah beliau wafat pada tahun 1905, majalah al-Manar diteruskan oleh muridnya
yang bernama Muhammad Rasyid Ridla (1865-1935). Kumpulan tulisan Muhammad Abduh
dan M. Rasyid Ridla ini kemudian dibukukan menjadi Tafsir al-Manar.
Dalam perkembangannya aliran Salafi-Wahabi pun terpecah dalam banyak faksi
(kelompok) dengan karakteristiknya masing-masing, tergantung pada imam mana
yang diikutinya. Tokoh ulama Wahabi yang menjadi rujukan dan panutan saat ini
adalah Muhammad Nashiruddin al-Albani seorang dosen Ilmu Hadits di Universitas
Islam Madinah yang lahir pada tahun 1915 dan wafat 1 Oktober 1989. Ia
dipuja-puja kaum Wahabi-Salafi bahkan dianggap lebih alim dari Imam Bukhori,
karena ia men-Takhrij/mengomentari beberapa haditsnya Imam Bukhori (194 – 256
H).
Ajaran Salafi-Wahabi ini masuk ke Indonesia mulanya:
1) Dibawa oleh seorang tokoh pembaharu agama (mujaddid) asal Yogyakarta yang
bernama Darwis yang aktif dan rutin mengikuti pemikiran Muhammad Abduh-M.
Rasyid Ridla lewat majalah al-Manar dan ajaran Wahabi. Ia kemudian dikenal
dengan nama KH. Ahmad Dahlan yang pada 18 Nopember 1912 mendirikan organisasi
keagamaan Muhammadiyyah. Walaupun kenyataannya dalam amaliyah sehari-hari
selama hidupnya KH. Ahmad Dahlan lebih dekat kepada madzhab Syafi’i. Namun
sepeninggal beliau terjadi modernisasi total dari para penerusnya.
2) Syaikh Akhmad Soorkati (1872-1943) seorang tokoh pembaharu (mujaddid) asal
Sudan yang kalah bersaing dalam Jami'at al-Khair di negaranya, kemudian Hijrah
ke Indonesia dan tahun 1914 di Betawi mendirikan organisasi al-Irsyad.
3) Di Bandung pun muncul Mujaddid yang bernama A. Hasan yang juga dikenal
sebagai Hasan Bandung atau Hasan Bangil yang tahun 1927 meneruskan organisasi
PERSIS (Persatuan Islam) yang didirikan pada 1923 oleh KH. Zam Zam Palembang.
4) HOS. Cokroaminoto dengan PSII (Persatuan Syarikat Islam Indonesia).
Apa yang Menyebabkan Aliran "Islam Baru” Dapat Menyebar dengan Cepat?
Muhammad bin Abdul Wahab pernah menguji coba ajaranya kepada penduduk Bashrah,
tetapi karena mereka adalah penganut fanatik ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah,
maka usahanya bagaikan menabrak batu karang. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab
menetap di Dir’iyah dan Pangeran Muhammad ibn Saud (dari Dir’iyah Najed) setuju
untuk saling dukung-mendukung dengan Wahhabi.
Keluarga/Klan Saud dan pasukan/lasykar Wahhabi berkembang menjadi dominan di
semenanjung Arabia, pertama menundukkan Najed, lalu memperluas kekuasaan mereka
ke pantai timur dari Kuwait sampai Oman. Orang Saudi juga membawa tanah tinggi
'Asir di bawah kedaulatan mereka dan pasukan Wahhabi mereka mengadakan serangan
di Irak dan Suriah, dan menguasai kota suci Shi'ah, Karbala tahun 1801.
Pada tahun 1802, pasukan Saudi-lasykar Wahhabi merebut kota Hijaz (Jeddah,
Makkah, Madinah dan sekitarnya) di bawah kekuasaan mereka. Hal ini menyebabkan
kemarahan Daulah Utsmaniyah Turki, yang telah menguasai kota suci sejak tahun
1517, dan membuat Daulah Utsmaniyah bergerak. Tugas untuk menghancurkan Wahhabi
diberikan oleh Daulah Utsmaniyah Turki kepada raja muda kuat Mesir, Muhammad
Ali Pasha.
Muhammad Ali mengirim pasukannya ke Hijaz melalui laut dan merebutnya kembali.
Anaknya, Ibrahim Pasha, lalu memimpin pasukan Utsmaniyah ke jantung Najed,
merebut kota ke kota. Akhirnya, Ibrahim mencapai ibukota Saudi, Dir’iyah dan
menyerangnya untuk beberapa bulan sampai kota itu menyerah pada musim dingin
tahun 1818.
Ibrahim lalu membawa banyak anggota klan Al Saud dan Ibn Abdil Wahhab ke Mesir
dan Ibukota Utsmaniyah, Istanbul Turki, dan memerintahkan penghancuran Diriyah,
yang reruntuhannya kini tidak pernah disentuh kembali. Pemimpin Saudi terakhir,
Abdullah bin Saud dieksekusi di Ibukota Utsmaniyah, dan kepalanya dilempar ke
air Bosphorus. Sejarah kerajaan Saudi Pertama berakhir, namun, Wahhabi dan klan
Al Saud hidup terus dan mendirikan kerajaan Saudi Kedua yang bertahan sampai
tahun 1891.
Perselingkuhan agama - ambisi kekuasaan - kepentingan asing dimulai dari
wilayah Najed. Ketika lasykar Wahhabi - klan Al Saud yang dipimpin Abdul Aziz
Ibnu Sa'ud menyusun kekuatan kembali disertai dukungan persenjataan mesin dari
sekutu lamanya, Inggris (antek Amerika). Maka awal tahun 1900-an mereka
menyerang kembali kota Hijaz yang saat itu dipimpin Raja Syarif Husain. Ketika
itu Hijaz hanya dibantu oleh Daulah Utsmaniyyah Turki yang sudah mulai lemah,
dan akhirnya pada tahun 1924 ketika kekuasaanya sudah mengecil Raja Syarif
Husain mengasingkan diri ke kepulauan Cyprus dan kekuasaanya diserahkan pada
putranya yang bernama raja Syarif Ali.
Raja Syarif Ali membuat kota-kota pertahanan baru, tapi lasykar Wahhabi-klan
Ibnu Sa'ud dengan persenjataan canggih berhasil mengepung semua kota, hingga
yang tersisa hanya pertahanan di pelabuhan Jeddah. Pada ahir 1925 ketika
lasykar Wahhabi-klan Ibnu Sa'ud berhasil menguasai pelabuhan Jeddah, maka Raja
Syarif Ali menyerah pada pemberontak.
Dari tahun 1925 inilah Hijaz dengan dua kota suci Makkah dan Madinah dikuasai
oleh keluarga Sa'ud dan Wahhabi. Dan ahirnya tepat tanggal 23 September tahun
1932, Hijaz berubah nama menjadi al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'udiyyah,
Kerajaan Arab Sau'di, yang dinisbatkan kepada nama leluhurnya yakni Al Sa'ud,
dengan Ibukotanya Riyadh. Dan tahun 1943 muncullah ARAMCO (Arabian-American
Company) yang mengeksplorasi minyak Arab Saudi. Dari sejarah itulah, mengapa
sampai saat ini Arab Saudi selalu tidak bisa bersuara selain seperti suara
Amerika, sekalipun harus berbeda dengan negara-negara Islam lainnya.
Jatuhnya Hijaz ke tangan pemberontak pada 1925 tidak hanya berakibat perubahan
pemeritahan, tapi juga merombak total praktek-praktek keagamaan di Hijaz dari
yang semula Ahlussunnah wal Jama’ah menjadi faham Wahhabi. Seperti larangan
bermadzhab, larangan ziarah ke makam-makam pahlwan Islam, larangan merokok,
larangan berhaji dengan cara madzhab. Bahkan makam Rasulullah Saw., sahabat dan
tempat-tempat bersejarah pun berencana akan digusur karena dianggap sebagai
biang/tempatnya kemusyrikan.
Ketika aliran Salafi-Wahhabi berkembang di Dir’iyyah maupun Najed itu belumlah
membuat risau umat Islam dunia. Tetapi ketika mereka menguasai pusat Islam
yakni dua kota suci di Hijaz, maka hal ini menimbulkan dampak yang luar biasa,
termasuk dalam persebarannya ke seluruh dunia. Melihat perubahan ajaran yang
terjadi di Hijaz, maka hampir semua umat Islam Ahlussunnah wal Jama’ah di
seluruh dunia memprotes rencana pemerintahan baru di Hijaz yang ingin
memberlakukan asas tunggal, yakni madzhab Wahhabi.
Protes luar biasa pun muncul di Indonesia, ketika bulan Januari 1926
ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama’ah di Indonesia berkumpul di Surabaya untuk
membahas perubahan ajaran di dua kota suci. Dari pertemuan tersebut lahirlah
panita Komite Hijaz yang diberi mandat untuk mengahadap raja Ibnu Sa'ud guna
menyampaikan masukan dari ulama-ulama Ahlussunah wal Jama’ah di Indonesia. Akan
tetapi karena belum ada organisasi induk yang menaungi delegasi Komite Hijaz,
maka pada tanggal 31 Januari 1926, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama’ah
Indonesia kembali berkumpul dan membentuk organisasi Induk yang diberi nama
Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Para Ulama) dengan Rois Akbar Hadhratus Syaikh KH.
Hasyim Asy’ari .
Susunan delegasi Komite Hijaz NU untuk menghadap raja Ibnu Sa'ud adalah sebagai
berikut:
Penasehat : KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Masyhuri Lasem, KH. Kholil Lasem
Ketua : KH. Hasan Gipo, Wakil Ketua : H. Shaleh Syamil Sekretaris : Muhammad
Shadiq Pembantu : KH. Abdul Halim
Materi pokok yang hendak disampaikan langsung ke hadapan raja Ibnu Sa'ud
adalah:
1) Meminta kepada raja Ibnu Sa'ud untuk memberlakukan kebebasan bermadzhab
empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. 2) Meminta tetap diramaikannya tempat
bersejarah karena tempat tersebut telah diwakafkan untuk masjid. 3) Mohon agar
disebarluaskan ke seluruh dunia setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji, baik
ongkos haji, perjalanan keliling Makkah maupun tentang Syekh. 4) Mohon
hendaknya semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz, ditulis sebagai
undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum ditulisnya
undang-undang tersebut. 5) Jam'iyyah NU mohon jawaban tertulis yang menjelaskan
bahwa utusan sudah menghadap raja Ibnu Sa'ud dan sudah pula menyampaikan
usul-usul NU tersebut.
Daftar Pustaka:
• Al-Milal wa al-Nihal, Syaikh Abdul Karim asy-Syahrastani • Fath al-Bari fi
Syarh Shohih al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqolani • KH. Zainul Arifin,
panglima Hizbullah, Seorang Pahlawan, NU Online • Pertumbuhan dan Perkembangan
NU, Drs. Choirul Anam. Bisma Satu Surabaya • Resolusi Jihad dalam Peristiwa 10
November, M. Mas’ud Adnan, Jawa Pos • Telaah Kritis Atas Doktrin Faham Salafi /
Wahabi, A. Sihabuddin • Dll.
Label:
SEJARAH
05.44
 Membaca dan menulis buku bisa jadi merupakan suatu aktivitas yang sangat
menyenangkan. Sudut pandang inilah yang dicoba diangkat penulis buku ini.
Secara memikat Hernowo, sang penulis, mampu menunjukkan bahwa buku mempunyai
"rasa" dan "aroma" yang bisa membangkitkan selera. Lebih
dari itu membaca dan menulis buku dapat mengantarkan seseorang untuk memiliki
ketajaman yang luar biasa dalam mengenali dan memperbaiki diri lewat suatu
kemampuan, yang dalam buku ini disebut sebagai "mata baru".
Membaca dan menulis buku bisa jadi merupakan suatu aktivitas yang sangat
menyenangkan. Sudut pandang inilah yang dicoba diangkat penulis buku ini.
Secara memikat Hernowo, sang penulis, mampu menunjukkan bahwa buku mempunyai
"rasa" dan "aroma" yang bisa membangkitkan selera. Lebih
dari itu membaca dan menulis buku dapat mengantarkan seseorang untuk memiliki
ketajaman yang luar biasa dalam mengenali dan memperbaiki diri lewat suatu
kemampuan, yang dalam buku ini disebut sebagai "mata baru".
Menulislah
Diterbit Oleh Unknown pada Jumat, 21 Agustus 201505.44
Melejitkan Diri Dengan Buku
Oleh :Bagus Mustakim
 Membaca dan menulis buku bisa jadi merupakan suatu aktivitas yang sangat
menyenangkan. Sudut pandang inilah yang dicoba diangkat penulis buku ini.
Secara memikat Hernowo, sang penulis, mampu menunjukkan bahwa buku mempunyai
"rasa" dan "aroma" yang bisa membangkitkan selera. Lebih
dari itu membaca dan menulis buku dapat mengantarkan seseorang untuk memiliki
ketajaman yang luar biasa dalam mengenali dan memperbaiki diri lewat suatu
kemampuan, yang dalam buku ini disebut sebagai "mata baru".
Membaca dan menulis buku bisa jadi merupakan suatu aktivitas yang sangat
menyenangkan. Sudut pandang inilah yang dicoba diangkat penulis buku ini.
Secara memikat Hernowo, sang penulis, mampu menunjukkan bahwa buku mempunyai
"rasa" dan "aroma" yang bisa membangkitkan selera. Lebih
dari itu membaca dan menulis buku dapat mengantarkan seseorang untuk memiliki
ketajaman yang luar biasa dalam mengenali dan memperbaiki diri lewat suatu
kemampuan, yang dalam buku ini disebut sebagai "mata baru".
Hanya saja, selama ini membaca dan menulis buku selalu identik dengan rasa
menjemukan dan melelahkan. Buku yang menjadi sarana utama kegiatan tersebut
sama sekali tidak memiliki daya tarik yang memikat. Secara keilmuan, buku boleh
saja berisi segudang ilmu. Namun penampilan buku yang kaku menjadi penghambat
utama bagi seseorang untuk membaca dan menyusunnya.
Hernowo melihat bahwa buku tidak lebih dari kumpulan teks. Buku tidak mampu
memberikan apa-apa. Ribuan atau bahkan miliaran kata yang ada di dalamnya tidak
ada yang bisa memberikan pencerahan secara mempesona. Buku hanya berputar-putar
berpanjang-panjang dan sekadar mempermainkan teks. Buku sama sekali tidak mampu
melampaui teks. Sekalipun terkadang mampu melukiskan problem-problem manusia
yang kompleks, buku tetap saja beku. Tidak ada yang menarik di dalam buku.
Fenomena ini sangatlah ironis. Sebab sebagaimana kata pepatah, buku adalah
gudang ilmu. Di era internet sekarang ini buku masih menduduki peringkat
terbaik sebagai media tranformasi ilmu dan informasi yang lebih mudah dijangkau
oleh masyarakat. Lewat buku ini, Hernowo membongkar kebekuan ini secara panjang
lebar mengenai berbagai permasalahan yang bersifat paradigmatik, kultural dan
sistemik yang menyebabkan buku belum menjadi partner utama dalam sistem
kehidupan masyarakat.
Membangun Paradigma Progresif
Bosan dan ngantuk. Inilah kultur yang terbangun dalam membaca buku.
Karenanya tak heran jika banyak orang yang memilih nonton sinetron daripada
membaca buku. Sebab menonton sinetron terasa lebih santai dan menyenangkan.
Berbeda dengan membaca buku yang membutuhkan banyak energi dan keseriusan yang
tidak jarang justru membuat pusing para pembacanya.
Untuk memasuki dunia buku, paradigma ini harus dibongkar terlebih dahulu.
Hernowo menawarkan sebuah paradigma yang menyamakan buku sebagai
"makanan". Sebagaimana jasmani manusia yang membutuhkan nutrisi agar
tubuh menjadi sehat, manusia pun membutuhkan energi khusus yang dapat mengasah
ketajaman ruhaninya. Dalam konteks inilah buku dapat menjadi santapan ruhani
manusia yang penuh gizi.
Terkait dengan gizi buku untuk kebutuhan ruhani manusia ini, Dr. C. Edward
Coffey, seorang peneliti dari Henry Ford Health System mampu mengungkapkan
sebuah fakta menarik tentang hubungan buku dengan kesehatan mental. Dalam
penelitiannya, ia telah mampu membuktikan bahwa hanya dengan membaca buku,
seseorang akan terhindar dari penyakit demensia yang menyebabkan kepikunan.
Dengan paradigma baru ini, buku dapat diperlakukan sebagai makanan, sama
persis sebagaimana kita memakan makanan jasmani. Beberapa tips yang ditawarkan
Hernowo dalam mengonsumsi buku sebagai makanan ruhani, di antaranya sebagai
berikut. Pertama, agar membaca buku tidak menyebabkan kantuk, buku yang dibaca
haruslah buku yang sesuai kegemaran dengan tema-tema yang sangat disukai
sebagaimana makanan kesukaan. Kedua, sebelum membaca semua halaman buku, ada
baiknya kalau buku-buku tersebut "dicicipi" terlebih dahulu. Bisa
dengan jalan mengenali siapa pengarang buku itu atau dengan mencari informasi
tentang sesuatu yang menarik. Ketiga, untuk menyelesaikannya, membaca buku
dapat dilakukan dengan cara ngemil (sedikit demi sedikit seperti orang yang
makan kacang goreng). Dengan jalan ini buku setebal 300 halaman pun dapat
diselesaikan dengan santai, yaitu dengan jalan mencari halaman-halaman yang
menarik dan bermanfaat dalam buku tersebut. Halaman-halaman ini sajalah yang
dibaca dan didalami tidak perlu membaca semua halaman yang ada di dalam sebuah
buku.
Subyek potensial yang bisa dikembangkan untuk mengenalkan buku adalah
anak-anak. Hernowo membangun konsep ini dari 50 Simple Things You Can Do to
Raise a Child Who Loves to Road karya Kathy A. Zahler. Ada tiga petunjuk paling
awal yang dijadikannya sebagai bahan rujukan untuk menjadikan akan
"keranjingan" membaca. Pertama, memberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada anak agar mereka benar-benar dapat melihat orangtuanya sedang membaca
buku. Kedua, orangtua harus membagikan informasi-informasi yang bermanfaat yang
diperoleh dari kegiatan membaca kepada anak. Ketiga, pada saat membaca buku di
rumah sesekali orangtua harus membacanya dengan suara keras supaya anak dapat
mendengar suara bacaan yang sedang dibaca.
Di samping keteladan di atas, orangtua juga harus membangun suasana yang
menyenangkan dalam memperkenalkan buku kepada anak. Ini dapat dilakukan dengan
mengajak anak jalan-jalan mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan buku.
Misalnya, dua minggu sekali anak diajak untuk "mencicipi" dan melihat
jajaran buku yang ada di toko buku atau perpustakaan. Bisa juga dengan
membiasakan anak untuk memilih buku bacaan secara bebas sesuai dengan
keinginannya. Anak juga harus diberi kebebasan untuk membolak-balik dan
bermain-main dengan bukunya sendiri.
Mengenalkan buku sejak dini kepada anak ini memiliki peranan yang sangat
penting dalam membangun kebutuhan anak terhadap buku. Pada tahapan ini anak
tidak perlu "dikarbit" untuk segera dapat membaca dalam arti memahami
isi buku. Perkenalan ini hanya berfungsi untuk membiasakan anak agar sering
bertemu dengan wujud huruf. Dengan cara ini akan lebih mudah untuk mengenali
kembali dan menyebutkan bunyi huruf. Lebih dari itu, dengan perkenalan antara
suatu rangsangan visual (melihat) huruf dan kesan auditif (mengucapkan) huruf
tertentu.
Institusi sekolah merupakan suatu lembaga yang dipercaya sebagai tempat
belajar membaca. Di sekolah anak mulai dikenalkan dengan huruf. Di sekolah
pulalah mereka diajar mengeja dan membaca hingga memahami buku. Namun sayang
sekolah tidak mengajarkan agar siswanya memiliki kebutuhan terhadap buku.
Sebaliknya membaca justru menjadi kegiatan yang memberani dan memberatkan.
Meskipun perangkat membaca seperti buku bacaan, buku tulis dan juga pena
senantiasa berada di dalam tas siswa, namun tidak ditemukan kultur baca siswa
sekolah yang mengasyikkan.
Fenomena ini merupakan persoalan klasik yang dialami oleh sekolah. Sekolah
yang semestinya dibangun untuk mengawal proses perkembangan kepribadian anak
justru berkembang menjadi lembaga yang memfrustrasikan. Di sekolah anak dipaksa
untuk mengikuti sistem yang dikembangkan sekolah. Padahal belum tentu sistem
tersebut sesuai dengan kecenderungan dan cara belajar anak yang bersangkutan.
Tak heran jika sekolah justru dirasakan sebagai sesuatu yang membelenggu dan
memberatkan.
Buku ini menggambarkan betapa Hernowo sangat terpikat dengan konsep belajar
ala Bobbi DePorter dengan Quantum Learning-nya. Tidak hanya itu Hernowo juga
memunculkan konsep pembelajaran yang sangat fantastis yang digagas oleh
Jeannette Vos dalam The Learning Revolution. Ia juga terpikat dengan konsep
Daniel Goleman dalam Emotional Intelligence dan juga Multiple Intelligence-nya
Howard Gardner.
Menghadirkan Rasa Fan
Melalui model-model pembelajaran tersebut Hernowo ingin menghadirkan rasa
fun bagi siswa sekolah. Dengan rasa ini siswa akan merasakan bahwa sekolah
ternyata merupakan tempat yang sangat mengasyikkan. Perlu dicatat di sini bahwa
menyenangkan dan mengasyikkan bukan berarti menciptakan suasana ribut dan
hura-hura dalam kelas. Ini tidak ada hubungannya dengan kesenangan yang
sembrono dan kemeriahan yang dangkal.
Kegembiraan di sini berarti bangkitnya minat, adanya keterlibatan penuh
serta terciptanya makna, pemahaman (penguasaan atas materi yang dipelajarinya),
dan nilai yang membahagiakan siswa. Itu semua adalah kegembiraan dalam
melahirkan sesuatu yang baru. Penciptaan ini jauh lebih penting daripada segala
teknik, metode atau media belajar yang mungkin dipilih untuk digunakan dalam
proses pembelajaran.
Untuk mendukung gagasan ini Hernowo juga memunculkan fenomena "sekolah
sihirnya Harry Potter". Betapa siswa yang bersekolah di sana memiliki
ketergantungan yang sangat besar untuk selalu belajar dan berkreasi. Mereka
justru merasa sedih ketika musim liburan tiba. Sewaktu liburan datang mereka
selalu berharap agar waktu liburan dapat berjalan dengan cepat.
Dengan jalan ini akan tercipta suatu kebutuhan siswa terhadap sekolah.
Sejalan dengan ini akan terbangun pula suatu kebutuhan terhadap buku sebagai
sarana yang tidak bisa dipisahkan dari sekolah. Dengan demikian akan tercapai
suatu kultur membaca yang mengasyikkan yang dilahirkan dari sistem sekolah yang
menyenangkan.
Merujuk peta kecerdasan Howard Gardner, aktivitas membaca dapat memacu
kategori kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini merupakan suatu kemampuan
menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Pada
halaman-halaman depan buku ini, Hernowo memberikan penekanan yang besar tentang
apa yang dapat diperoleh dari kecerdasan ini. Ia mengungkapkan berbagai profesi
yang dapat dikembangkan dari kecerdasan linguistik.
Di halaman depan tersebut Hernowo memunculkan sederet nama yang telah mampu
melejitkan potensi diri mereka berdasarkan kecerdasan yang mereka miliki.
Nama-nama tersebut di antaranya Hilman "Lupus" Hariwijaya, Emha Ainun
Najib, Nurcholish Madjid, K.H. Abdullah Gymnastiar, Butet Kertarajasa dan juga
Helmi Yahya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang mampu menemukan dan kemudian
mengembangkan potensi sesuai dengan kecenderungan kecerdasan yang dimilikinya.
Sesuai dengan teori "buku sebagai makanan" yang digagasnya,
Hernowo tampaknya ingin memunculkan daya tarik buku di halaman-halaman depan.
Daftar keberhasilan tokoh-tokoh tersebut seolah dijadikan sebagai
"aroma" yang dapat menggugah selera para pembaca. Awalan yang
sedemikian menarik ini masih dilengkapi dengan berbagai tips tentang cara
membaca secara kreatif. Dengan melahap halaman-halaman tersebut para pembaca
akan semakin tergoda untuk mendalami buku ini lebih lanjut.
Penutup
Buku ini dapat dikatakan sebagai refleksi seorang Hernowo. Ia sangat
terinspirasi oleh Akhmad Wahib (1942-1972) dan Soe Hoek Gie (1942-1969), dua
orang tokoh muda yang berhasil membuat catatan harian dan kemudian mampu
mewariskannya kepada generasi berikutnya dalam bentuk buku. Sebagaimana kedua
tokoh muda yang mati muda tersebut, Hernowo bermaksud membagi kesuksesannya
dalam bidang tulis-menulis kepada masyarakat luas. Di samping ingin
mentransformasikan kesuksesannya itu Hernowo juga ingin mencapai suatu
perubahan cara pandang terhadap buku dengan suatu perubahan paradigmatik,
kultural, dan sistemik.
Buku ini terbagai ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama diberi
judul "Makna yang Berproses". Kelompok pertama ini dibuka dengan dua
tulisan yang mencoba memposisikan buku sebagai "makanan". Selanjutnya
diikuti oleh beberapa konsep praktis yang dapat dilakukan untuk membuat
seseorang dapat melakukan kebiasaan membaca buku sejak usianya sangat dini.
Pada bagian akhir kelompok pertama ini, para pembaca diajak untuk menggunakan
aktivitas membaca dan menulis buku sebagai salah satu cara untuk mengenali buku
sebagai salah satu cara untuk mengenali diri. Di sini ditekankan bahwa buku
dapat mengubah pandangan, sikap hidup dan cara berpikr seseorang.
Kelompok kedua dilabeli identitas "Makna yang Menjadi". Makna
yang menjadi merupakan hasil pembacaan yang efektif terhadap buku. Pada
kelompok kedua ini kumpulan tulisan yang disajikan seolah ingin menunjukkan
bahwa Hernowo betul-betul tekah mengikat makna terhadap buku-buku yang telah
dibacanya. Buku-buku tersebut berupa wacana-wacana pendidikan kontemporer
alternatif yang dapat dijadikan pilihan untuk mengelola proses pendidikan
secara lebih efektif sehingga mampu melejitkan diri setiap siswa yang ada di
dalamnya.
Terakhir, judul yang disajikan buku ini sangatlah tepat. Ada dua hal yang
ingin dicapai dalam judul itu. Pertama, membangun kultur baca yang
mengasyikkan. Dan kedua, menggunakan kultur baca tersebut sebagai sarana untuk
melejitkan potensi kecerdasan linguistik. Karenanya buku ini sangat cocok dikonsumsi.
Di samping isinya yang menarik, penyajiannya pun amat memikat. Wajar saja jika
dalam waktu dua bulan, buku in telah naik cetak sebanyak dua kali. Sungguh
menakjubkan. ** Majalah Gerbang, Edisi
4, Th III, Oktober 2003.
Menulis di Rumah
Buku
Oleh : Hernowo
Di kawasan Hegarmanah, Bandung, ada sebuah tempat yang mengasyikkan. Tempat
itu bukan café, juga bukan mall ataupun rental VCD dan DVD. Di tempat itu
terdapat buku-buku yang memperkaya wawasan dan membantu siapa saja untuk
menumbuhkan sel-sel otak (neuron). Buku-buku di Rumah Buku ada yang dijual dan
ada juga yang disewakan.
Saya beruntung dapat mencicipi tempat yang mengasyikkan itu pada sore hari,
Minggu 21 September 2003. Kebetulan sore itu hujan deras datang mengguyur
sebentar dan mengubah hawa yang semula gerah dan berdebu menjadi sejuk dan
nyaman. Sungguh sore itu merupakan sore yang mengondisikan diri saya untuk
menyerap apa saja yang baik dan menarik.
Rumah Buku terletak agak masuk ke dalam, tepatnya di Jalan Hegarmanah 52.
Ruangan yang digunakan untuk memajang buku-buku tidaklah besar, namun terasa
asri. Ada tempat duduk yang empuk untuk membaca buku, disertai ngobrol ringan,
dan ada tempat untuk menulis yang, sepertinya, mampu merangsang imajinasi.
Sore itu saya diundang oleh pengelola Rumah Buku untuk membagikan
pengalaman saya menulis kepada komunitas baca-tulis yang akan dibentuk di situ.
Menurut rencana, komunitas baca-tulis yang masih mencari nama itu kelak akan
membincangkan kegiatan baca-tulis yang dapat memberdayakan anggotanya.
Saya tentu menyambut baik gagasan untuk mendirikan komunitas seperti itu.
Indonesia masih sangat memerlukan sekian juta komunitas yang mempedulikan
kegiatan baca-tulis. Ada kemungkinan, mendirikan komunitas baca-tulis pada saat
ini bukan merupakan suatu kegiatan yang dapat menarik perhatian masyarakat
luas.
Akan tetapi, apabila komunitas baca-tulis direkayasa sedemikian rupa
sehingga menjamur, dan masing-masing komunitas itu lantas sabar untuk terus
hidup dan bertumbuh, saya memperkirakan dalam jangka 3 atau 4 tahun, Indonesia
akan berubah secara dahsyat. Modal penting untuk mendirikan komunitas
baca-tulis hanya satu: kemauan untuk terus bertumbuh.
Usai mengikuti rapat awal yang menggairahkan, tibalah giliran saya untuk
mengisahkan pengalaman saya ketika menulis. Kepada para peserta komunitas yang
hadir, saya menunjukkan tiga macam strategi menulis yang saya gunakan untuk
mengatasi hambatan kurangnya percaya diri pada saat menulis. Tiga macam
strategi itu adalah "meniru", membebaskan diri, dan mengkonstruksi
pemahaman.
Strategi pertama, "meniru", saya ibaratkan sebagai langkah wajar
yang dapat dijalani oleh seorang penulis pemula. Untuk mampu melakukan sesuatu,
kita harus meniru. Untuk dapat berbicara, kita harus meniru orangtua kita
ketika mereka berbicara. Untuk dapat menendang bola dengan baik, kita harus
meniru seseorang yang sudah berpengalaman dalam menendang bola dengan baik.
Begitu juga menulis. Kadang meniru seseorang yang sudah piawai menulis
dianggap sebagai plagiat. Itu betul apabila proses meniru itu lantas kita
tunjukkan kepada publik. Yang saya maksud meniru di sini tentu bukan untuk
keperluan publikasi. Kita meniru menulis dalam konteks belajar menulis.
Pada saat-saat awal menulis, saya meniru Cak Nun--sapaan akrab Emha Ainun
Nadjib. Cak Nun, dulu, begitu lihainya memadukan dua kata yang memiliki latar
belakang budaya sangat berbeda. (Sebagai contoh, misalnya penciptaan frase
"ahlul-terminal" untuk menggambarkan preman di stasiun bus.) Saya
kadang terdorong untuk menciptakan frase sebagaimana cara Cak Nun menciptakan
frase yang menggelitik.
Contoh lain meniru yang saya lakukan, misalnya, tiba-tiba di pikiran saya
terbangun sebuah konsep tentang masyarakat Indonesia yang memprihatinkan. Saya
ingin merumuskannya secara tertulis. Tetapi saya tidak mampu. Lalu bertemulah
saya dengan tulisan Cak Nun yang cocok dengan pikiran saya yang ingin saya
rumuskan itu. Saya langsung meniru saja rumusan Cak Nun.
Saya juga meniru Kang Jalal--sapaan akrab Jalaluddin Rakhmat--ketika ingin
menata tulisan saya. Kang Jalal adalah model saya dalam menulis secara jernih
dan tertata. Saya ingin menyerap (meniru) keahlian Kang Jalal dalam menulis
secara jernih dan tertata. Lantas saya membaca secara asyik buku-bukunya.
Apabila saya menemukan tulisan panjang Kang Jalal yang bagus, saya menirunya
yaitu dengan memindahkan tulisan tersebut ke catatan harian saya.
Juga, selain Cak Nun dan Kang Jalal, saya meniru cara menulis Ustad Quraish
Shihab. Ustad yang satu ini sangat ahli dalam membongkar dan merumuskan makna
sebuah kata. Saya kadang diajak untuk menjelajahi sebuah makna kata yang luar
biasa kaya dan konkret. Cara memilih sebuah kata yang cocok dalam mewakili
perasaan dan pikiran saya, saya tiru dari cara Ustad Quraish menulis.
Saya kok yakin bahwa dengan meniru, kita tetap dapat mengembangkan
gaya-tulis khas kita. Artinya, karakter kita tidak mungkin habis digilas oleh
proses peniruan kita. Model yang kita tiru--dalam hal ini berkaitan dengan
menulis--malah akan membantu kita mencuatkan karakter tulisan kita. Bisa jadi,
pada saat awal, kita masih dipengaruhi oleh model yang kita tiru. Tetapi, dalam
jangka panjang, kita tentu dapat memunculkan keinginan, kehendak, dan kemauan
kita sendiri dalam tulisan kita.
Setelah meniru, saya lalu menggunakan konsep "pembebasan diri"
pada saat awal menulis. Saya membebaskan diri dari aturan apa pun, termasuk
aturan kebahasaan. Pada saat awal menulis, saya memposisikan diri sedang
mencari dan mengumpulkan bahan yang ingin saya tulis. Jadi, agar bahan-bahan
yang tersimpan di dalam diri saya itu dapat mengalir dengan lancar, maka saya
harus membebaskan diri dari kerangkeng apa pun.
Teori membebaskan diri dalam menulis ini, sekarang dikembangkan oleh para
pakar menulis dengan cara-cara yang sangat menarik. Dr. Rico, misalnya,
menamakan proses membebaskan diri ini sebagai cara menulis dengan teknik
"clustering". Tony Buzan menamakannya sebagai teknik "mind
mapping". Dan seorang psikolog kondang yang namanya sulit dieja, Mihaly
Csikszentmihalyi, mengartikannya sebagai "flow".
Terakhir, setelah meniru dan membebaskan diri, saya mempersepsi menulis
sebagai cara saya menyusun atau mengonstruksi proses pemahaman. Hingga saat
ini, saya berpendapat bahwa lewat menulislah (mengikat hal-hal yang bermakna)
seseorang dapat dibantu untuk "menguasai" suatu masalah. Ingat,
"ikatlah ilmu dengan menuliskannya" kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib
r.a. Demikianlah, sore itu di Rumah Buku saya menyampaikan hal-hal itu.***
Bagaimana Membuat Buku yang Bergizi
Oleh: Hernowo
Senang sekali dapat terus bertemu dengan Anda di Mizan OnLine. Meskipun
pertemuan kita hanya lewat jembatan bernama kata-kata, namun saya harus
bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk terus berlatih menulis. Semoga,
saya sungguh ingin berharap, pembaca juga mendapat manfaat dari tulisan-tulisan
saya.
Mulai minggu depan, insya Allah, saya akan membuat tulisan berseri di
rubrik "Plong" dengan topik sebagaimana judul tulisan saya ini. Saya
ingin mengajak para pembaca untuk melakukan eksplorasi bersama saya ke dunia
buku, tepatnya dunia yang di dalamnya kita dapat menikmati bagaimana seseorang
membuat buku.
Saya akan mencoba menjadi pemandu pembaca dalam menjelajahi hampir semua
corak buku yang pernah dibuat oleh para penulis andal. Tentu, kata "hampir
semua" itu tidak lantas merujuk ke seluruh buku yang ada di dunia. Saya
akan memilihkan buku-buku yang, menurut penilaian saya, memberikan hal-hal
baru.
Titik tekan saya dalam memilih buku-buku yang memberikan hal-hal baru itu
terletak pada bagaimana seorang penulis menyajikan gagasannya, dan bagaimana
penyajian itu dapat memberikan suasana lain saat seorang pembaca masuk ke dalam
dunia buku yang diciptakan penulis tersebut.
Apa yang saya rumuskan itu tentulah masih abstrak. Namun, saya akan mencoba
menunjukkannya pada serial tulisan saya yang berkaitan dengan "bagaimana
membuat buku yang bergizi tinggi". Pada tahap awal, kita akan belajar
kepada penulis-penulis sukses, seperti Tony Buzan, Spencer Johnson, Jalaluddin
Rakhmat, J.K. Rowling, Helen Fielding, dan masih banyak penulis lain, yang menuangkan
gagasannya secara apik dan tertata.
Selanjutnya, setelah kita memiliki sejumlah pengetahuan tentang corak buku
yang disajikan dengan sangat kaya dan berbeda, kita akan masuk ke pengenalan
komponen buku secara sangat tajam. Dalam buku Mengikat Makna, saya telah
menunjukkan secara selintas anatomi buku. Nah, di dalam serial tulisan saya
kali ini, saya akan mempreteli (membongkar secara detail dan satu per satu)
setiap komponen dan kemudian mengenali apa fungsi tiap komponen itu dalam
"membunyikan" buku.
Setelah semuanya itu, saya akan menunjukkan kepada pembaca bagaimana kita
dapat mengelola energi kreatif yang ada di dalam diri kita untuk menciptakan
judul-judul yang "menggigit". Atau, dalam konteks lain, misalnya,
adalah bagaimana kita memanfaatkan benar potensi kita untuk memadukan bahasa
rupa (visual) dan bahasa kata (tekstual) secara melejit dan menarik.
Pembaca yang budiman, membuat buku memang dapat mengasyikkan. Bagi saya,
membuat buku bagaikan melakukan pemotretan atas kehidupan diri saya, dan
kemudian hasil pemotretan itu saya petakan secara apik di sebuah album. Menata
foto yang diletakkan secara miring, atau memberikan komentar foto yang
mengesankan, hampir persis keadaannya saat saya merakit gagasan orang lain ke
dalam buku-buku saya.
Tentu, saya akan berusaha sekuat daya saya untuk tidak terjebak pada
pemaparan yang pelik, rumit, dan cepat membuat para pembaca bosan. Saya akan
mencoba memberikan paradigma baru dalam membuat buku. Saya akan mencoba
menyajikan tulisan-tulisan saya sependek mungkin dan bersifat "how
to" (bagaimana melakukan sesuatu secara praktis). Doakan saja ya supaya
saya dapat memenuhi syarat-syarat yang telah saya rumuskan tersebut.
Yang lain, saya ingin proses saya menyajikan serial tulisan ini berlangsung
interaktif. Artinya, saya mengajak para pembaca untuk memberikan respons dan
bertanya tentang apa saja. Anda dapat langsung mengirim e-mail ke
info@mizan.com, atau bisa langsung juga mengirimkannya kepada saya. Saya akan
senang sekali apabila proses interaksi ini terjadi. Sebab hanya dengan bertukar
pengalaman secara aktiflah, sebuah gagasan atau perumusan itu dapat terus
direvisi dan disajikan dengan lebih baik.
Kemudian, selain itu pula, saya juga akan membangkitkan minat para pembaca
untuk punya kemauan, terutama, dan kemampuan menulis buku. Tentu, saya tidak
bisa mengarahkan agar pembaca membuat buku ini dan buku itu. Pilihan membuat
buku dalam konteks ini atau konteks itu, saya serahkan sepenuhnya kepada
pembaca. Saya akan menunjukkan saja, di dalam serial tulisan saya ini, bahwa
potensi membuat buku itu sebenarnya sudah tertanam di dalam diri pembaca.
Nah, akhirnya sampailah saya pada penjelasan soal kenapa harus menggunakan
kata "bergizi" dan ditambah dengan kata "tinggi" lagi. Kan
sudah cukup kalau buku itu "bergizi" dan tidak usah gizi yang
dikandungnya tinggi? Benar sekali. Buku yang bergizi saja sudah cukup. Buku
yang bergizi sudah pasti akan membuat seorang pembaca buku mampu menyerap
gizi-ruhani yang luar biasa. Kenapa harus ditambahi kata "tinggi"?
Pembaca, saya menambahi kata "tinggi" agar di dalam menuliskan
serial tulisan ini ada semacam tantangan. Saya memang belum punya konsep
tentang "bergizi tinggi" itu seperti apa. Atau bagaimana merumuskan
secara objektif dan bisa disetujui oleh hampir semua kalangan tentang buku yang
miliki "gizi tinggi" itu. Sungguh, pada saat ini, itu belum
terpikirkan oleh saya.
Saya, sekali lagi, hanya ingin ada tantangan. Soal buku yang bergizi, saya
kira sudah saya jelaskan di dalam dua buku saya, Mengikat Makna dan Andaikan
Buku Itu Sepotong Pizza. Saya merumuskan buku-buku yang memiliki gizi adalah
buku-buku yang mampu menggerakkan pikiran pembacanya. Dan proses penggerakan
pikiran yang dapat dilakukan oleh sebuah buku, ada kemungkinan, hanya lewat
susunan kata yang memang memenuhi kaidah penalaran, diksi yang baik, serta juga
koherensi dan komposisi yang yahud pula, yang disajikan oleh sebuah buku.
Lantas, kira-kira bagaimana rumusan soal buku yang bergizi tinggi? Semoga
saja, serial tulisan saya nanti dapat memecahkan soal ini. Selamat menikmati,
dan senang dapat membantu Anda. **Bandung, 21 Agustus 2003
Jangan Berhenti Pada “Sekedar Tahu”:
Paradigma Baru Pembelajaran ?
Penulis: Hernowo
Pendidikan
bukanlah ibarat mengisi sebuah ember. Pendidikan adalah menyalakan sekelebat
api. –William Butler Yeats
Ketika saya terus berusaha mengotak-atik wujud konkret dari kurikulum
berbasis emosi, saya menemukan pentingnya mengubah paradigma pemelajaran selama
ini. Gagasan memunculkan paradigma-baru dalam pemelajaran ini saya peroleh
sebenarnya sudah cukup lama. Dalam buku Vitamin T, saya menunjukkan pentingnya
seorang pembaca buku memiliki paradigma-baru membaca pada zaman yang serbacepat
berubah ini.
Dan paradigma-baru membaca ini saya peroleh dari pemikiran Sindhunata--yang
dipijakkan pada gagasan Bloom dan Conrard--yang tertuang dalam sebuah pengantar
yang ditulisnya untuk buku saya yang lain, Main-Main dengan Teks Sembari
Mengasah Kecerdasan Emosi. Sindhunata menunjukkan bahwa saat ini tak cukup jika
seorang pembaca buku memiliki paradigma, "Apa yang dapat diberikan oleh
teks?" Paradigma-lama membaca itu harus diganti dengan paradigma-baru yang
berbunyi, "Teks yang mana yang dapat mengubah diriku?
Nah, berpijak pada pemikiran
Sindhunata tersebut, saya kemudian membawanya ke proses pemelajaran. Tampaknya,
kini, seoang pemelajar tak cukup jika memiliki paradigma belajarnya dalam
konteks, “Apa yang dapat kupahami dari mata pelajaran ini?†Merujuk ke
pemikiran Sindhunata, selayaknyalah para pemelajar dewasa ini, sudah mulai mengganti
paradigma-lama belajarnya dengan paradigma-baru yang berbunyi, “Apakah mata
pelajaran yang kupeljari ini dapat mengubahku?"
Untuk sampai ke paradigma-baru belajar, seorang pemelajar perlu menggunakan
kecerdasan emosinya. Tentu, kecerdasan rasionalnya sudah lebih dahulu digunakan
untuk menganalisis hal-hal penting berkaitan dengan mata pelajaran yang ingin
dipelajarinya. Namun, setelah kecerdasan rasionalnya membantu memahami mata
pelajaran yang ingin dikuasainya, dia perlu melanjutkan proses belajarnya
dengan menggunakan kecerdasan emosi miliknya secara sadar.
Menggunakan kecerdasan emosi berarti mencoba melibatkan atau mengaitkan
dirinya dengan mata pelajaran yang sedang dipelajarinya. Sekali lagi, menurut
para pakar otak, emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memberi
arti. Lewat emosilah seseorang kemudian mencoba mengaitkan apa yang ada di
dalam dirinya dengan apa yang sedang terjadi di luar dirinya. Emosi dapat
membawa masuk pengalaman eksternal (atau hal-hal yang sedang terjadi di luar
diri) untuk digabungkan dengan pengalaman internal (atau hal-hal yang sudah
dimiliki seseorang.
Apabila sebuah mata pelajaran yang sudah dikuasai oleh seseorang ternyata
tidak nyantol atau terkait dengan pengalaman internal yang telah terbangun di
kedalaman dirinya, ada kemungkinan mata pelajaran itu tidak memberikannya
makna. Artinya, proses belajar dengan berpijak pada paradigma-baru,
"Apakah mata pelajaran yang sedang kupelajari ini dapat mengubah
diriku?", ada kemungkinan tidak terbangun di dalam dirinya. Hal itu
dikarenakan mata pelajaran tersebut tidak bisa dikaitkan, lewat emosinya,
dengan pengalaman yang sudah tertanam di dalam dirinya.
Mengapa ketidakterkaitan itu bisa terjadi? Ada banyak penyebab. Saya ingin
menyebut beberapa hal saja. Pertama, proses pemelajaran tersebut tidak dalam
kondisi yang menyenangkan. Artinya, ketika si pemelajar mendapatkan mata
pelajaran tersebut, dia berada dalam keadaan yang diliputi oleh emosi negatif
(risau, tertekan, bingung, kekalutan, ancaman, dan semacamnya). Emosi negatif
kadang bersifat menolak atau membawa seseorang untuk tidak dapat berkonsentrasi
atau fokus. Kedua, lingkungan eksternal yang melingkupinya (termasuk jika ada
seorang pengajar yang membantu si pemelajar memahami materi pelajaran yang dipelajarinya)
benar-benar tidak menyamankan (udara panas, perut lapar, presentasi hanya satu
arah, monoton, kering, kelelahan fisik dan psikis melanda, dan semacamnya).
Ketiga, di dalam diri si pemelajar memang tidak ada pengalaman yang
benar-benar pernah eksis yang terkait dengan mata pelajaran yang sedang
dipelajarinya. Yang mungkin perlu diperhatikan di hal ketiga ini adalah ada
kemungkinan dia punya pengalaman tentang mata pelajaran yang sedang
dipelajarinya, namun pengalaman itu membuatnya mengalami hal-hal yang tidak
menyenangkan. Hal ketiga ini jelas perlu dievaluasi secara cermat oleh semua
pihak yang terlibat dalam proses pemelajaran. Yang lebih parah jika para
pengajarnya pun tidak berusaha mengaitkan lebih dahulu kehidupan yang dijalani
sehari-hari dengan mata pelajaran yang ingin diajarkannya. Atau dalam bahasa
lain, sang pengajar tanpa sengaja memisahkan mata pelajaran yang ingin
diajarkan itu terpisah dengan dunia-nyata dirinya.
Paradigma-baru belajar ini memberikan kepada siapa saja untuk tidak lagi
menganggap bahwa memahami hal-hal baru itu atau ilmu sudah cukup. Belajar pada
zaman sekarang sudah tidak lagi bermanfaat apabila hanya "sekadar
tahu". Tingkat “sekadar tahu†harus dilewati sehingga seperangkat
pengetahuan yang sudah dipahaminya mampu mengubah dirinya menjadi diri yang
baru dan berbeda dengan diri sebelumnya. Ada kemungkinan apabila diri dapat
berubah setelah mempelajari sesuatu yang baru, sang diri kemudian dapat
mengumpulkan semangat dan gairah untuk mempelajari sebanyak mungkin hal-hal
baru lagi.
Inilah kunci dari pentingnya melibatkan dan menggunakan kecerdasan emosi
dalam sebuah pemelajaran. Emosi akan membawa diri untuk menjumpai warna-warni
atau pelangi pemelajaran. Emosi akan mengajak seseorang untuk melihat kekayaan
dan keanekaragaman sebuah peristiwa. Dan emosi akan mengajak inner-self
(diri-lebih-dalam) seseorang untuk ikut terlibat dan mencari kaitan dengan apa
pun yang sedang terjadi di luar dirinya. Apabila sebuah pemelajaran dapat
melibatkan emosi, proses dan hasil pemelajaran, sudah dapat dipastikan, akan
membaik ketimbang hanya menggunakan kecerdasan rasional.
Bukan hanya semangat dan gairah akan muncul jika emosi dilibatkan. Ada
kemungkinan besar, si pemelajar akan mencoba menciptakan sesuatu yang baru yang
berasal dari kedalaman dirinya. Karena emosi dapat menjangkau hal-hal yang
paling dalam yang disimpan oleh seseorang di dalam dirinya, proses penciptaan
tersebut bisa jadi akan sangat unik. Jadi, lewat emosi, yang dibantu (atau
bekerja sama secara komplementer dengan) kecerdasan rasional, seorang pemelajar
dapat menunjukkan (mengekspresikan) dirinya lewat karya-karya ciptaannya.
Apabila seseorang dapat menciptakan sebuah karya nyata--dalam bentuk apa
pun sesuai dengan jenis mata pelajaran yang sedang dipelajarinya--maka karya
nyata itu bisa dijadikan bukti bahwa dirinya telah berubah. Apakah dengan
mendapat nilai sembilan atau sepuluh dalam sebuah ujian lantas pemerolehan
nilai itu dapat membuktikan bahwa seorang pemelajar telah berhasil mengubah
dirinya menjadi diri yang baru? Ada kemungkinan ya. Namun, ada kemungkinan juga
bukti pemerolehan nilai itu tidak valid. Tentu bukti itu akan menjadi sangat
valid apabila dia dapat menciptakan sebuah karya yang menunjukkan keunikan
dirinya setelah dia mendapatkan nilai tinggi tersebut.
Apa yang saya ungkapkan terakhir ini juga sejalan dengan definisi
kecerdasan menurut penemu teori multiple intelligences, Howard Gardner. Menurut
Gardner, kecerdasan, di masa sekarang, perlu dirumuskan menjadi dua. Pertama,
untuk memecahkan masalah; dan kedua, untuk menciptakan sebuah karya. Defenisi
kecerdasan yang pertama jelas merupakan paradigma-lama belajar. Ini berkaitan
dengan tes atau ujian, sementara definisi kedua sangat terkait dengan
paradigma-baru belajar. Seseorang dapat dikatakan dapat memanfaatkan
pengetahuan yang telah dikuasainya (yaitu dengan mengubah dirinya) apabila
mampu menciptakan sebuah karya yang sesuai dengan mata pelajaran tersebut.
Semoga bermanfaat. (Subuh, 26 Januari 2005)
Membaca & Menulis Bukan
Sekedar Teknik ?
Oleh Hernowo
Hidup itu terbatas. Kita mendiami satu tubuh, satu
pikiran, dan melihat dunia dengan sepasang mata. Melalui menulis dan membacalah
dunia kita menjadi lebih terbuka. Kita menjadi lebih terbuka--dan dengan
demikian menjadi tidak terbatas--dikarenakan dapat menggunakan "mata"
(pikiran) orang lain yang tersebar di mana-mana.-JOAN LINGARD
Hari Sabtu, 3 Desember 2004, kemarin merupakan hari yang penuh kenangan.
Sekitar pukul 09.30 WIB saya memasuki sebuah ruangan kelas di kampus ITB.
Rasa-rasanya, dulu, saya sering memasuki ruangan kelas yang kini saya masuki
dengan peran berbeda. Dulu saya memasuki ruangan itu untuk mendengarkan
penjelasan para dosen. Kini saya memasuki ruangan tersebut untuk menyampaikan
penjelasan kepada para mahasiswa.
Saya diundang oleh Jurusan Informatika ITB untuk menyampaikan pembahasaan
mengenai salah satu kemampuan akademis, yang diperlukan untuk studi, kepada
para mahasiswa baru angkatan 2004. Saya tak mengira kalau jumlah mahasiswa baru
itu lebih dari seratus orang. Saya ingin kemampuan akademis yang dirumuskan
oleh panitia tersebut saya rumuskan sendiri sebagai keterampilan-dasar (basic
skill) penting dalam ikut menyukseskan studi. Dan basic skill yang saya
sampaikan jelas tak jauh dari reading and writing skill.
Sayang, ruangan yang menghidupkan semangat saya itu lagi mengalami gangguan
listrik. Sehingga OHP yang saya minta, dan sudah disediakan di ruangan kelas,
tidak dapat saya gunakan. Saya pun harus berteriak agak keras ketika
menjelaskan konsep saya tentang membaca dan menulis karena ruangannya cukup
besar dan dipadati oleh banyak mahasiswa. Saya sebenarnya agak kurang puas
kalau tak menggunakan OHP dalam mempresentasikan pikiran-pikiran saya.
Namun, alhamdulillah, presentasi saya dapat berjalan lancar dan, menurut
saya, mampu mengusik perhatian para mahasiswa. Saya dapat mengajak para
mahasiswa untuk berpartisipasi-aktif meramaikan ceramah saya. Ceramah saya
dapat berlangsung interaktif. Saya memang meminta para mahasiswa untuk menyela
(melakukan interupsi) selama saya menyampaikan penjelasan secara bebas. Saya,
akhirnya, dapat menyelesaikan kegiatan saya tersebut dalam waktu hampir dua
jam.
Meskipun, mungkin, saya melihat masih ada beberapa mahasiswa yang
mengacungkan tangan untuk bertanya, saya harus menghentikan acara saya. Pukul
13.00 WIB, pada hari Sabtu itu, saya juga diminta oleh Jurusan Ilmu
Perpustakaan UNPAD untuk menyampaikan materi membaca efektif kepada mahasiswa
baru. Kebetulan penyelenggaraan acara membaca efektif tersebut berlangsung di
Jatinangor. Jadi, saya harus menyiapkan diri saya supaya tidak terlambat datang
ke acara kedua pada hari Sabtu itu.
Ada seorang mahasiswi ITB yang bertanya kepada saya. Sebenarnya, dia tidak
bertanya. Dia menyampaikan semacam hampir keluhan. Katanya, di SMA dulu dia
pernah memperoleh materi yang hampir sama dengan materi yang saya berikan.
Katanya, ketika dia mengikuti program tersebut, dia memiliki semangat untuk
menerapkan materi yang diperolehnya ketika dia duduk di bangku SMA. Namun,
keluhnya, ternyata dia hanya tahan menerapkan materi itu dalam beberapa hari
saja. Selebihnya dia tak termotivasi bahkan terjerumus dalam lembah kemalasan
membaca dan menulis.
Saya langsung, secara tegas, menjawab bahwa teknik-teknik membaca dan
menulis itu kadang memang diperlukan. Hanya, teknik itu perlu dibiasakan
penerapannya agar manfaatnya tampak kentara. Teknik yang hanya dicoba beberapa
kali dan tidak dibiasakan, tidak akan memberikan sesuatu yang bersifat
memberdayakan bagi si pengguna teknik. Nah, di balik pemberian teknik ada hal
lain yang perlu diperhatikan. Hal lain itu bernama paradigma. Paradigma inilah
yang akan memotivasi seseorang untuk membiasakan diri dalam menerapkan suatu
teknik.
Paradigma adalah isi benak atau cara berpikir kita tentang bagaimana
memahami dan menindaki sesuatu. Apabila pikiran kita tidak diubah dalam
menjalankan suatu teknik, maka teknik itu tidak akan memberikan apa-apa kepada
kita. Jadi, apabila seorang instruktur hanya melatihkan suatu teknik membaca
kepada para peserta pelatihan--dan tidak memberikan landasan berpikir yang
jelas dan kukuh berkaitan dengan mengapa teknik ini atau itu yang perlu dicoba
diterapkan--ya ada kemungkinan teknik-teknik itu tidak ada gunanya dalam
membangkitkan semangat peserta untuk memberdayakan dirinya dengan teknik-teknik
itu.
Saya jelaskan kepada si mahasiswi bahwa materi yang saya berikan untuk para
mahasiswa baru Jurusan Informatika sifatnya lebih mengarah pada persoalan
paradigma--lebih tepat jika dikatakan sebagai "pergeseran paradigma".
Ada kemungkinan besar, ketika saya menjelaskan landasan berpikir saya, saya pun
menyampaikan teknik. Misalnya, ketika saya menjelaskan konsep "mengikat
makna" (mengapa kegiatan membaca perlu dibarengkan dengan kegiatan
menulis), saya sebenarnya sedang memberikan teknik membaca yang efektif.
Selain konsep "mengikat makna", saya pun menunjukkan pentingnya
mempersepsi buku sebagai "makanan", yaitu makanan untuk ruhani.
Kebetulan ketika saya menjelaskan soal ini, buku terbaru saya, Vitamin T, sudah
jadi dalam bentuk buku yang ciamik. Akhirnya dengan menunjukkan buku Andaikan
Buku Itu Sepotong Pizza dan Vitamin T, saya mencoba menggeser paradigma
berpikir para mahasiswa tentang buku serta menunjukkan secara jelas bahwa ada
buku yang bergizi dan ada pula buku yang beracun.
Kepada si mahasiswi juga saya tunjukkan bedanya teknik yang dilandasi oleh
sebuah paradigma yang kuat, dan teknik yang sekadar teknik tanpa ada landasan
berpikir yang hebat. Untuk memperjelas soal ini, saya bertanya kepada si
mahasiswi, "Apakah Anda percaya apabila saya katakan bahwa menulis itu
dapat menyembuhkan?" Si mahasiswi menjawab, "Percaya!" Saya pun
melanjutkan lagi pertanyaan tersebut, "Mengapa Anda percaya? Apa landasan
berpikir atau argumentasi Anda?" Si mahasiwi diam tak menjawab.
Nah, apabila Anda menerima sebuah teknik untuk melakukan sesuatu atau Anda
mempercayai bahwa sesuatu itu akan memberikan manfaat kepada Anda, namun Anda
tidak bisa menjelaskan mengapa itu bermanfaat bagi Anda, ya Anda tidak memiliki
paradigma-baru berkaitan soal itu. Si mahasiswi bertanya mendesak,
"Bagaimana saya bisa memperoleh landasan berpikir atau sebuah
paradigma-baru?" "Anda perlu membaca buku yang berkaitan dengan
teknik yang ingin Anda terapkan atau yang berkaitan dengan landasan berpikir
yang perlu Anda pahami."
Di UNPAD, seorang mahasiswi bertanya pula tentang perbedaan antara menyerap
informasi (atau pengetahuan) lewat buku dan televisi (VCD). Dia mencontohkan
misalnya di Metro TV kadang ada penayangan tentang biografi seorang tokoh.
Sementara itu ada juga buku yang mengisahkan tentang kehidupan sang tokoh yang
ditayangkan di televisi. Apakah materi yang diserap dari dua media yang berbeda
ini memang memberikan pengetahuan yang berbeda atau sama saja? Sebab kalau
sama, kan lebih enak menonton televisi ketimbang membaca buku ?
Secara tersirat tampak dari pertanyaan si mahasiswi bahwa dia ingin
menunjukkan kepada saya bahwa membaca buku itu berat dan menonton televisi itu
ringan. Saya kira saya mengamini saja hal yang ingin disampaikan secara
tersirat ini. Namun, Anda perlu tahu bahwa meskipun membaca buku itu berat, ada
hal-hal penting yang tidak dapat ditandingi oleh menonton televisi dari
kegiatan membaca buku. Membaca buku itu aktif dan, bisa jadi, menonton televisi
itu pasif.
Saya kemudian menjelaskan paradigma-baru membaca kepada para mahasiswi yang
hadir di forum yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Perpustakaan bahwa
apabila Anda membaca buku, Anda sebenarnya sedang menyerap perbendaharaan kata
yang ada di buku tersebut. Jadi, apabila Anda membaca buku biografi seorang
tokoh, Anda sebenarnya sedang memasukkan bahasa yang mengisahkan sang tokoh ke
dalam diri Anda. Dan ini tidak terjadi dengan kegiatan menonton televisi
tentang biografi sang tokoh.
Nah, apabila Anda ingin mengisahkan kembali kehidupan sang tokoh yang Anda
pahami, Anda akan kelabakan apabila hanya menonton televisi. Anda baru akan
lancar mengisahkan kehidupan sang tokoh apabila Anda membaca buku yang
mengisahkan biografi sang tokoh. Apalagi jika Anda mau menulis sesuatu tentang
sang tokoh, atau Anda ingin membuat makalah tentang sang tokoh, atau Anda ingin
menganalisis sang tokoh, semua ini tentu memerlukan perbendaharaan kata yang
sangat kaya agar Anda lancar menuliskannya. Dan jika hal ini yang ingin Anda
capai, Anda perlu membaca buku.
Membaca buku yang bercerita (yang tidak berisi data dan angka), akan
membuat seseorang dapat menceritakan kembali tentang apa yang dibacanya. Ketika
saya menyampaikan soal ini kepada para mahasiswa Jurusan Informatika ITB,
mereka segera saja mengeluh bahwa buku-buku yang mereka baca di kampus hampir
semuanya berisi bahasa pemograman yang banyak data dan simbol-simbol serta
angka. "Jadi, buku semacam ini tak bisa membuat saya menceritakan apa yang
saya baca secara mengalir?" tanya seorang mahasiswa. "Ya,
jelas," jawab saya. "Buku itu membuat Anda tak bisa ngomong apa-apa.
Apalagi untuk menuliskan sesuatu. Buku-buku itu mungkin saja memberikan
pengetahauan kepada Anda, namun hanya membaca buku-buku semacam itu akan
membuat Anda kesulitan menyampaikan gagasan Anda secara bercerita."
"Lantas bagaimana mengatasinya Pak?" "Ya, bacalah buku-buku yang
bercerita, seperti buku biografi atau catatan harian," tambah saya.
Membaca dan menulis ada kemungkinan besar memang tidak hanya berhubungan
dengan teknik. Apalagi jika mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang kurang
menghargai budaya baca-tulis. Untuk mengubah kekurangperhatian bangsa ini
terhadap kegiatan baca-tulis diperlukan upaya mengubah cara berpikir mereka
tentang kegiatan baca-tulis. Mengubah cara berpikir mereka tentu tak semudah
melatihkan teknik membaca dan menulis. Mengubah cara berpikir hampir sama
dengan mengubah wajah peradaban yang dimiliki sebuah bangsa. (Minggu, 4
Desember 2004, pukul 09.26)
Aki Achdiat, Sang “Raksasa” itu
Oleh : Hernowo
Tubuhnya tampak ringkih. Ketika berdiri pun dia perlu disangga oleh
sebatang tongkat. Ada dua orang yang kemudian memegang dua lengan yang dekat
dengan bahunya ketika dia harus berjalan. Tampak jalannya pun tertatih-tatih.
Hanya, yang mengagumkan, bicaranya masih jernih dan lancar. Dialah sang
"raksasa" di dunia sastra Indonesia (kata Yudi Latif) dan
dunia-sastra dunia (tambah Saini K.M.) yang pernah mencetak prestasi besar
dengan menelurkan roman ATHEIS.
Saya beruntung dapat melihat, dan merasakan, secara langsung "semangat"-nya
yang luar biasa ketika bicara soal sekularisme di dunia sekarang dan juga
soal-soal besar berkaitan dengan ideologi. Padahal usianya sudah mendekati
seabad! Padahal sepasang matanya sudah tidak mampu lagi bekerja secara normal!
Sosok sang "raksasa" ini, menurut saya, sudah sepantasnya untuk saya
kagumi dan teladani, meskipun saya sendiri baru bersentuhan dengan
kepribadiannya sore itu.
Ketika Aki Achdiat sempat bercerita tentang proses kreatif menulisnya, saya
benar-benar dibuat ternganga. Saya yang belakangan ini menekuni dunia
baca-tulis dan sudah seperti merasakan memiliki seabrek paradigma baru tentang
baca-tulis, menjadi keder dan bersegera menyembunyikan apa pun yang saya
miliki. "Mengarang itu bagaikan menuangkan seluruh pengalaman hidup,"
katanya. Ketika saya menangkap kata-katanya ini, saya membayangkan bahwa
"pengalaman hidup" yang dimaksudkan oleh Aki ini adalah pergulatan
hidup yang dalam dan intens.
Tepat saya kira rumusan Yudi ketika mengatakan bahwa Manifesto
Khalifatullah--"kispan" (kisah panjang)-nya yang merupakan karya
terbaru Aki--merupakan kisah yang berbeda dengan novel Atheisnya.
"Kispan" ini adalah semacam wadah yang di dalamnya kemudian
dimanfaatkan oleh si penulis untuk menunjukkan pergulatan ide. Ia tak sekadar
cerita. Ia tak membawa-bawa kehidupan yang biasa-biasa saja. Ia merupakan
pengalaman hidup yang panjang yang ditulis tidak sebagaimana penulis sekarang.
Sebagaimana kata Yudi, "kispan" ini adalah semacam kisah panjang
(terlalu panjang untuk disebut novel dan terlalu pendek untuk dimasukkan ke
kategori cerita pendek) berbasiskan ide.
Manifesto Khalifatullah--atau sebuah tulisan yang dapat mengubah keadaan,
terutama mengubah diri para pembaca--adalah sebuah proses. Ia tidak diketik
kemudian langsung jadi. Aki mengaku tak bisa menulis cepat-cepat dan sekali
jadi. Menulis bagaikan, sekali lagi, menuangkan kehidupannya yang panjang dan
penuh oleh pertempuran. Menulis seperti ini jelas perlu melibatkan seluruh
totalitas kehidupan seseorang. Menulis seperti ini membutuhkan semacam
kejujuran tingkat tinggi. Bagaimana mungkin sebuah kisah ditulis dengan hebat
apabila si penulis tak punya pengalaman hebat?
Yang mengagetkan saya (kalau saya tak salah dengar lho), Aki mengatakan
bahwa proses menulis itu gampang. Atau, dalam bahasa yang lain, dapat dikatakan
bahwa tidak ada kesulitan menulis. Menulis tidak sulit? Menuliskan kehidupan
adalah hal gampang? Soedjatmoko pernah menyampaikan pengalaman menulisnya bahwa
menulis itu bagaikan kehidupan seorang ibu yang sedang melahirkan anaknya. Ada
penderitaan hebat dan, tentu saja, ada kesulitan hebat (kadang-kadang).
Sementara itu, Sindhunata pernah juga mengatakan bahwa menulis itu merupakan
kegiatan yang tidak ringan karena melibatkan pikiran secara total.
Apa kira-kira yang dimaksud oleh kata-kata Aki bahwa menulis itu gampang?
"Menulis itu gampang kalau si penulis sudah mematangkan benar
pengalamannya. Bahan-bahan yang ditulisnya akan mengalir begitu saja tanpa
dapat dicegah." Kematangan dan kepemilikan pengalaman itulah yang rupanya
menjadi syarat utama agar seorang penulis dapat melahirkan gagasan-gagasannya.
Dan kematangan plus kepemilikan pengalaman inilah yang membuat sebuah tulisan
yang hebat mencuat. Tentu, yang dibicarakan Aki bukanlah tulisan yang
sekadarnya. Tulisan yang diharapkan lahir dari seorang penulis beneran adalah
model tulisan yang dilahirkan oleh seroang penulis semacam Bernard Shaw.
Saya kemudian mendapatkan banyak sekali bahan dari penuturan Aki sore itu.
Saya seperti berubah menjadi seseseorang yang lagi belajar membaca dan menulis
untuk benar-benar menjadi penulis besar dan hebat kelak. Saya merasakan ada
"semangat" yang ditularkan oleh Aki dan kemudian menyusupi diri saya.
Mungkin saya tak harus menjadi "sebesar" Aki Achdiat ataupun Bernard
Shaw. Cukuplah jika saya punya impian atau cita-cita yang mendorong saya untuk
terus mendekati kebesaran dan kehebatan Aki Achdiat. Cukuplah jika kemudian
saya dapat mengembangkan diri saya terus-menerus, sebagai seorang penulis,
sehingga impian saya itu dapat saya capai sedikit demi sedikit dan benar-benar
saya nikmati.
Nah, ketika saya ketemu dengan Haris Priyatna di acara sore itu, saya
ditanya olehnya, "Mas Hernowo mau seperti Aki Achdiat?" dan langsung
saya jawab dengan tegas, "Ya." Sembari sedikit menjelaskan
argumentasi saya kepada Haris kenapa saya ingin meneladaninya, saya menekankan
sekali bahwa yang saya teladani itu bukan sosok "raksasa"-nya di
dunia sastra. Saya ingin meneledani sosok beliau yang hingga usia 94 tahun
masih memiliki pikiran segar dan jernih. Pastilah itu akibat kerutinan beliau
dalam menjalankan kegiatan membaca buku dan menuliskan pengalaman beliau.
Saya yakin apa yang dilakukan oleh Aki Achdiat pasti dapat saya tiru.
Bahkan saya sangat menganjurkan kepada rekan-rekan di Mizan untuk mengubah
kegiatan rutinnya di Mizan, dalam konteks membaca dan menulis, untuk
benar-benar menjadikan kegiatan itu digunakan sebagai salah satu cara terampuh
menumbuhkan dendrit atau mengayakan dan merapatkan jaringan saraf otak. Tentu
saja dengan mengubah cara berpikir kita seperti itu, ada kemungkinan besar
rutinitas kerja yang kadang membosankan akan mendatangkan berkah tak terkira.
Lantas, setelah saya menuliskan semua yang saya alami ketika berjumpa
dengan Aki Achdiat, saya diingatkan oleh tulisan Mas Haidar Bagir yang diposisikan untuk
mengantarkan karya pertama saya, Mengikat Makna. Saya benar-benar tak pernah
menghilangkan dari benak saya kata-kata Isaac Asimov yang dikutip Mas HB dalam
mengantarkan karya saya itu. Apa yang dikatakan Asimov? "Kalau dokter saya
mengatakan bahwa hidup saya hanya tinggal 6 menit lagi, saya tak akan menciut.
Saya hanya akan mengetik lebih cepat lagi." **
Mengobrolkan
“Ilmu Ngglethek” Dengan Sindhunata
Oleh : Hernowo
Bakiak itu laki-laki dan wanita
tak pernah keduanya berpisah
Bila yang satu melangkah
yang lain mengikutinya
seperti suami istri yang setia
Tak mungkin yang satu menyeberangkan ke kanan
lainnya menyeberangkan ke kiri
keduanya selalu maju, kiri-kanan, kanan-kiri, berganti-ganti
Tak mungkin yang satu meninggalkan yang lain
keduanya saling menunggu untuk maju
Sindhunata, "Bakiak alias Teklek" dalam Ilmu Ngglethek Prabu
Minohek (Boekoe Tjap Petroek, Sleman, 2004, h. 298)
Begitu saya membaca kidungan ini, saya teringat diri saya yang lampau
ketika saya menganalogikan kegiatan baca-tulis yang diselenggarakan secara
bareng bagaikan kehidupan suami-istri yang saling komplementer
(dukung-mendukung atau lengkap-melengkapi). Saya menuliskan soal pentingnya
kebarengan penyelenggaraan kegiatan baca-tulis itu dalam sebuah tulisan di buku
saya, Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza. Kini, saya menemukan bait-bait indah
yang mampu menggambarkan dua kegiatan yang telah mengubah diri saya tersebut
dalam kidungan ciptaan Romo Sindhunata.
Kidungan indah itu saya temukan di buku terbaru Romo Sindhu, Ilmu Ngglethek
Prabu Minohek. Buku ini mengisahkan secara lugas dan tuntas kehidupan seniman
ludruk kondang Cak Kartolo. Lewat gaya tulis Romo Sindhu yang mengalir dan
bersahaja, saya diberi semacam makna yang luar biasa berkaitan dengan sepenggal
kehidupan orang bawah. Jelas bahwa sepenggal kehidupan itu, sebelum saya
membaca buku karya Romo Sindhu, sama
sekali tak terbayangkan oleh diri saya. Mungkin saja saya sudah pernah
membayangakan. Namun, saya yakin, pembayangan itu bukan pembayangan yang
akhirnya meyakinkan bahwa sepenggal kehidupan manusia itu memang ada secara
real.
Ada empat bagian materi yang dipisahkan secara tegas ketika saya mencoba
memahami "the big picture" buku tersebut. Sebenarnya, buku ini sudah
selesai di tiga bagian pertama. Bagian terakhir, atau bagian keempat, adalah
cara penulisnya menunjukkan manfaat yang dapat diraihnya ketika menulis buku
yang memiliki bobot tinggi ini. Bagian keempat adalah bagian, yang menurut
saya, sangat penting karena si penulis dapat memeragakan kepada para pembacanya
bahwa dia ternyata dapat menyerap secara hampir sempurna "ilmu" yang
disampaikan oleh Cak Kartolo dan rekan-rekannya. Di bagian keempat itulah sang
penulis menciptakan kidungan yang "meniru" kidungan Cak Kartolo. Ini
sebuah pencapaian yang spektakuler. Jarang ada penulis buku yang kemudian
memanifestasikan secara konkret perolehannya begitu selesai menulis buku.
Materi pokok buku ini memang diurai secara asyik dalam bagian pertama,
kedua, dan ketiga. Bagian pertama berisi esai-esai ringan, namun menunjukkan
kedalaman ketika saya membacanya berulang-ulang, yang berkisah tentang
kehidupan Cak Kartolo dan rekan-rekan seprofesinya. Kehidupan mereka bak
panggung ludruk yang mula-mula sulit sekali saya rasakan kebenarannya, meskipun
Romo Sindhu berkali-kali menekankan bahwa itulah kehidupan sejati. Mungkin
lantaran saya belum pernah merasakan secara nyata (atau mungkin juga karena
saya nggak mau merasakan) kehidupan sebagaimana yang dialami oleh Cak Kartolo
dan rekan-rekannya, menyebabkan saya belum dapat memasukkan kehidupan nyata Cak
Kartolo dan rekan-rekannya sebagai pengalaman (kehidupan baru yang menyatu
dengan kehidupan) diri saya.
Kehidupan para seniman ludruk itu, sungguh, merupakan ironi. Saya,
misalnya, dibuat tertawa (namun tawa saya adalah tawa yang dilandasi rasa
getir) menyaksikan Cak Tamin yang hanya punya satu stel baju dan celana. Jika
baju dan celananya kotor, dia harus mencucinya dengan cara yang saya kira sulit
diungkapkan kebenarannya dalam kata-kata. Bayangkan, setelah mencuci baju dan
celana itu, dia harus kungkum (berendam) di sungai tempat dia mencuci baju dan
celananya hingga baju dan celananya kering kembali. Apa mungkin ada kehidupan
seperti ini? Dalam ludruk, dalam kehidupan para seniman ludruk, kehidupan
seperti itu ternyata ada.
"Manusia adalah makhluk yang sangat pelit dengan tertawa,"
demikian tercantum sederetan tulisan di sampul belakang buku Ilmu Ngglethek
Prabu Minohek. "Padahal hanya dengan tertawa, ia akan menjadi makin
bijaksana. Hanya dengan tertawa, ia akan kuat dan bisa menerima hidupnya
sehari-hari yang rutin dan biasa, dengan segala beban dan kesulitannya. Tertawa
adalah intisari ilmu ngglethek. Hanya dengan tertawa, kita bisa menyelami,
sesungguhnya hidup ini hanyalah ngglethek belaka. Ngglethek, maksudnya, adalah apa
yang kita bayangkan ternyata lain dengan kenyataan yang terjadi, dan apa yang
kita usahakan mati-matian, ternyata tak berarti apa-apa buat hidup kita."
Dalam bagian kedua dan ketiga buku ini, saya menemukan banyak hikmah
kehidupan. Ingin saya katakan di sini bahwa Cak Kartolo adalah seniman ludruk
yang brilian. Ketika saya menyampaikan soal ini kepada Romo Sindhu, dia hanya
bilang bahwa Cak Kartolo memang punya "kepekaan" yang sulit
dirumuskan dengan kata-kata. Ringkasnya, Cak Kartolo memang punya "kelebihan"
yang tak dimiliki seniman lain. Menciptakan kidungan dan jula-juli bukan
pekerjaan gampang. Kidungan-kidungan itu ada aturannya yang ketat. Seseorang
yang mencipta puisi di zaman kini mungkin lebih mudah karena kata-kata yang
diciptakannya tidak diberi "bingkai". Sementara itu, kidungan model
ludrukan Cak Kartolo perlu "bingkai" yang membuat kidungan itu dapat
didendangkan (dengan, kadang, rasa getir yang mengoyak sukma).
Kidungan ciptaan Cak Kartolo dapat saya nikmati di bagian kedua, meski saya
harus meraba-raba apa sesungguhnya makna kata-kata yang dibawa oleh kidungan
miliknya itu. Lalu, ciptaan lain yang tak kalah hebatnya ada di bagian ketiga
yang bercerita tentang lakon-lakon jula juli guyonan Cak Kartolo. Ada tiga
lakon yang ditunjukkan oleh Romo Sindhu. Ketiga lakon itu berjudul Basman
Juragan Genthong, lalu Cacing Anil, dan Loro Pangkon. Entah kenapa lakon
Tumpeng Maut tidak dipertunjukkan di buku ini. Mungkin karena di bagian
pertama, seluk beluk terciptanya atau hal-hal yang berkaitan dengan soal
tumpeng itu sudah dibahas secara cukup komprehensif.
Apa yang saya peroleh usai membaca buku Romo Sindhu tentang Cak Kartolo
ini? Pertama, saya memperoleh kehidupan yang kaya. Kegiatan membaca yang
senantiasa saya persepsi sebagai sebuah cara menyerap kekayaan hidup saya
peroleh dari buku ini. Saya diajak untuk menikmati kehidupan masyarakat bawah
yang penuh ironi. Di balik kesedihan, di balik, penderitaan, dan di balik
kesulitan hidup mereka ternyata ada tawa. Ketika saya sempat ngobrol langsung dengan
Romo Sindhu, dia mengatakan bahwa tawa mereka itu mungkin dapat dikatakan
semacam cara untuk mentransendensikan kepahitgetiran hidup. Orang-orang bawah
itu dapat bertahan dan lebih kuat dalam menahan gempuran hidup yang menekan
lantaran mereka mampu tertawa--meskipun tawa itu muncul lantaran ironi
kehidupan mereka.
Kedua, buku ini membuktikan pentingnya para intelektual kita untuk
bersegera mengabadikan (mendokumentasikan) warisan yang sangat bermanfaat untuk
melangsungkan kehidupan kita di zaman yang gampang berubah seperti saat ini
dalam bentuk tulisan yang berkisah (yang memudahkan seseorang menikmati dalam
konteks membaca). Saya katakan kepada Romo Sindhu bahwa penyamarataan
(globalisasi) manusia yang gencar berlangsung pada saat ini hanya bisa dikalahkan
apabila kita memiliki keunikan etnis. Artinya, kita berbeda karena kita punya
akar yang khas, yang menyejarah, dan dapat dilacak keberadaannya di masa lalu.
Memang, mustahil untuk mempertahankan pentas ludruk dalam zaman seperti ini.
Yang dipentingkan pada saat ini adalah merefleksikan kekayaan warisan ludruk
dalam bentuk yang kontekstual dengan zaman. Kata Romo Sindhu, ini jugalah yang
kemudian dilakukan oleh para filosof Barat dalam merefleksikan legenda atau
drama-drama Yunani.
Ketiga, ketika saya membaca buku karya Romo Sindhu, saya mempersepsi diri
saya mampu menyerap kemampuan Romo dalam berkisah tentang kehidupan manusia.
Buku ini jelas bukan buku yang berisi kisah fiksi. Ini kisah yang real, yang
nyata, dan ada di bumi kita. Kemampuan Romo berkisah tentang kehidupan seniman
ludruk adalah kemampuan yang sulit dicari tandingannya. Kata-kata yang tercipta
dari kepiawaian abstraksi Romo atas kehidupan para seniman ludruk--dalam
menggambarkan kehidupan (misalnya, rasa getir--bukanlah kehidupan (rasa getir)
sebagaimana digambarkan oleh kamus-kamus bahasa. Rasa getir yang diciptakan
Romo dari kehidupan para seniman ludruk adalah kata yang memiliki daya gugah
sekaligus daya ubah yang dahsyat. Saya merasakan benar soal ini dan saya
kemudian malah tertulari oleh gaya berkisah Romo berkaitan dengan bagaimana
saya nanti menuliskan sesuatu secara mengalir (misalnya kehidupan saya
sendiri).
Obrolan saya dengan Romo Sindhu memang tidak hanya lewat buku ciptaannya.
Pada siang hari yang terik, sekitar pukul satu lebih empat puluh lima menit,
hari Rabu 17 November 2004, saya bertemu beliau di kantornya, yang terletak di
Deresan, Jogjakarta. Kantor majalah Basis begitu nyaman dan asri. Pepohonan
tinggi dan besar masih memenuhi halaman-halaman yang sangat luas. Panas terik
yang menyengat kota Jogja dapat diredam dan diubah oleh dedaunan yang menghijau
menjadi angin semilir yang menyehatkan sekaligus memberikan gairah untuk hidup
lebih baik di masa depan. Saya ngobrol dengan Romo Sindhu di tempat yang nyaman
dan asri ini. Sekitar dua jam kami mengobrol ditemani teh panas dan potongan
mangga yang ranum.
Kehidupan memang indah. Kehidupan yang kadang kita lihat tampak garang dan
mengerikan, sebenarnya dapat kita ubah menjadi kehidupan yang damai dan
menenteramkan. Siapkah kita mengubah kehidupan yang kadang tampak garang dan
angker itu menjadi kehidupan yang indah memesonakan? Siapkah kita melihat diri
kita sendiri dan bersabar lebih dahulu dalam melihat diri sendiri sehingga diri
kita benar-benar mau dan mampu memperhatikan atau mempedulikan diri sendiri
kita sebelum kita ingin memedulikan orang lain? Siapkah kita mengubah diri kita
lebih dahulu sebelum terburu-buru memperingatkan orang lain dan mengajak mereka
untuk berubah?
Kadang kita sendiri belum memahami diri kita sendiri. Kadang, yang lebih
parah, kita terburu-buru melompat untuk memperhatikan diri orang lain sebelum
diri kita sendiri tuntas kita perhatikan. Melalui karya-karya Romo Sindhu dan
menikmati proses berinteraksi dengan pikiran beliau, saya merasakan bahwa saya
masih harus banyak belajar. Saya masih harus meningkatkan kegiatan berlatih
saya membaca dan menulis untuk menyerap sesuatu yang pokok dan penting bagi
perubahan diri saya agar diri saya terus mampu menjadi lebih baik. Obrolan
dengan Romo Sindhu mengingatkan saya bahwa manusia itu lemah. Hanya dengan
membagikan apa yang kita milikilah kelemahan kita itu dapat kita ubah menjadi
semacam kekuatan yang luar biasa.
Terima kasih untuk Romo Sindhu atas waktu yang disediakan untuk saya pada
hari Rabu itu. Saya merasakan hari-hari saya ke depan semakin bertambah cerah
dan menggairahkan diri saya untuk terus mau belajar membaca diri saya dan
menuliskan secara cermat tentang pertumbuhan dan perkembangan diri
saya.Teruslah berkarya Romo. Dan sampaikan semua yang ingin Romo sampaikan
dalam bahasa yang mengalir, bahasa yang menggugah dan memiliki daya ubah.
(Ditulis di Jogja, Kamis pagi,18 November, dan disempurnakan di Bandung, Sabtu
pagi, 20 November 2004 dalam keadaan yang menyenangkan dan menyamankan). **
Revisioning : Menyunting Berbasiskan Emosi Posistif
Oleh : Hernowo
Segala sesuatu yang ingin Anda kerjakan harus menjanjikan
manfaat bagi Anda atau Anda tidak akan termotivasi untuk melakukannya.-Bobbi DePorter dan Mike Hernacki, Quantum Learning
Saya mempersepsi tugas seorang editor sebagai tugas memberikan opini-kedua
(second opinion). Tugas editor tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bahasa.
Editor juga perlu memperhatikan gagasan yang dibawa oleh sebuah tulisan dan,
ini yang penting, bagaimana gagasan tersebut dapat dikemas menjadi sesuatu yang
mudah dibaca dan memotivasi sang pembaca.
Berdasarkan persepsi saya tersebut, saya berharap seorang yang ditugasi
untuk menyunting (baca: memperbaiki) sebuah tulisan menjadi mampu untuk
memperkaya dan memperindah tulisan yang disuntingnya. Salah satu tugas penting
editor dalam konteks memberikan opini-kedua adalah membuatkan judul-judul baru.
Judul-judul baru ini dapat terletak di jantung tulisan dan juga di sekujur
tulisan.
Keberhasilan seorang editor, biasanya saya soroti dari kepiawaiannya
menemukan judul yang lain daripada yang lain. Bagi saya, judul adalah identitas
sebuah tulisan. Judul adalah perasan dari inti gagasan sebuah tulisan. Pabila
judul tidak "menggigit", ada kemungkinan seorang pembaca tidak
tertarik untuk memperhatikan secara saksama sebuah tulisan yang sedang
dibacanya.
Memang, kadang pembaca tidak memerlukan judul yang "menggigit".
Asal judul itu sudah memberikan suatu makna tertentu yang membuatnya tertarik
untuk membaca, itu sudah cukup. Biasanya, straight news tidak memerlukan judul
yang, katakanlah, bombastis. Judul untuk sebuah berita cukup apabila dapat
langsung memberikan pemahaman atas apa yang sedang terjadi.
Ini berbeda dengan feature. Feature jelas membutuhkan judul yang
"menggigit" dan impresif. Penulisan feature lebih bebas daripada
penulisan berita. Waktu untuk menulis feature juga lebih banyak ketimbang
menulis berita yang kadang sangat dibatasi oleh keadaan. Dengan keadaan seperti
ini, seorang editor kemudian dapat lebih leluasa untuk memilih dan menentukan
judul yang menarik perhatian pembaca.
Mengapa saya menekankan sekali persoalan judul? Saya menekankan soal judul
ini karena di sinilah letak dari seni menulis. Dalam bahasa Quantum Learning,
seni menulis ini disebut sebagai teknik "show not tell" (memeragakan
dan bukan hanya memberi tahu kepada pembaca). Ketika sebuah tulisan tidak dapat
berperan sebagai seorang peragawati yang melenggok-lenggok di catwalk, bisa
jadi sebuah tulisan itu mati.
Tulisan yang menggugah adalah tulisan yang mampu menunjukkan dirinya.
Tulisan yang menarik minat seorang pembaca untuk mau terus memperhatikan
tulisan yang dibaca adalah tulisan yang dinamis. Untuk memahami seni menulis
ini, saya akan mengutipkan beberapa contoh yang saya ambil dari buku Quantum Learning,
tepatnya di Bab "Menulis dengan Penuh Percaya Diri".
Ini contoh kalimat yang memberitahukan: Ini adalah hari yang indah. Hujan
menimpa atap. Di seberang jalan, padang rumput menghijau.
Ini contoh kalimat yang memeragakan atau menunjukkan: Ketika membuka
jendelanya pada hari Sabtu pagi yang cerah, dia merasakan kesegaran menebar di
udara. Dedaunan di setiap pohon kemilau terkena pantulan sinar mentari.
Hamparan bunga yang beraneka warna menghiasi jalan masuk dan berseru,
"Musim semi!"
"Penjelasan yang hidup adalah
alat yang ampuh bagi para penulis. Ketika Anda belajar menulis deskripsi, Anda
akan mampu mengembangkan gambaran visual dalam benak para pembaca. Anda akan
mengubah pernyataan-pernyataan yang kering mengenai fakta menjadi ilustrasi
yang memesonakan. Orang tidak hanya akan membaca dan memahami, tetapi mereka
akan menghubungkan dan bereaksi," tulis Bobbi DePorter dan Mike Hernacki
dalam karyanya, Quantum Learning.
***
Dalam buku Write Where You Are: How to Use Writing to Make Sense of Your
Life karya Dr. Caryn Mirriam-Goldberg, ada beberapa hal menarik yang perlu juga
diperhatiakan oleh seorang editor. Salah satu hal menarik yang ingin saya
perkenalkan di sini adalah konsep revisioning (meninjau kembali). Saya
berpendapat bahwa konsep revisioning ini perlu dijadikan rujukan oleh para
editor yang ingin menjadikan sebuah tulisan yang diperbaikinya menjadi tulisan
yang menggugah.
Hebatnya, Dr. Caryn tidak hanya menunjukkan bagaimana melakukan revisoning.
Dia juga menjabarkan secara detail bagaimana seorang editor dapat mempraktikkan
secara baik konsep tersebut. Salah satu di antara persyaratan penerapan konsep
revisioning adalah seseorang perlu berada di dalam kondisi yang memungkinkan
emosi positif muncul.
Dalam buku Meraih Kebahagiaan, Jalaluddin Rakhmat menunjukkan adanya empat
ciri berkaitan dengan emosi positif. Pertama disebut joy (keriangan), kedua
interest (ketertarikan), ketiga contentment (kepuasaan), dan keempat love
(kasih sayang yang menyebar). Apabila empat ciri ini tampak pada seseorang,
niscaya orang tersebut berada dalam balutan emosi positif.
"Jangan pernah menganggap revisi sebagai memperbaiki sebagai sesuatu
yang salah," tulis Dr. Caryn mengutip pendapat Marion Dane Bauer.
"Anggapan itu akan membuatmu memulai dalam keadaan mental yang negatif.
Lebih baik menganggap revisi sebagai kesempatan untuk meningkatkan sesuatu yang
kamu sukai."
Di tempat lain di dalam bukunya, Dr. Caryn juga menulis soal revisi ini
dengan kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat, "Anggap revisi sebagai
kesempatan untuk melihat hasil karya seseorang dengan mata segar. Dalam
prosesnya, Anda (wahai para editor) lebih banyak belajar mengenai diri sendiri,
mengenai sebuah tulisan, dan bagaimana Anda dapat memperbaiki sebuah tulisan.
Proses menulis (dan tentu saja menyunting--H)--menulis sesuatu, membentuknya,
memperbaikinya, dan membiarkannya bertualang di sebuah dunia yang baru--dapat
membantu Anda lebih banyak dari sekadar menuangkan tulisan sekali jadi."
Ketika saya membaca dan memahami tulisan Dr. Caryn tentang merevisi
(memperbaiki) tulisan ini, saya mendapatkan gairah, motivasi, dan sesuatu yang
ingin saya raih lewat kegiatan menulis dan memperbaiki tulisan. Merevisi
tulisan jadinya adalah sebentuk kegiatan yang sangat menyenangkan.
"Meninjau kembali (revisioning) adalah kata yang diciptakan penyair
Adrienne Rich. Kata ini berarti melihat tulisan dan hidup Anda dengan cara baru
untuk melihat kemungkinan yang ada di luar batas-batas waktu dan adat
kebiasaan," tulis dr. Caryn menutup uraiannya. **Bandung, 24 Oktober 2004
Menulis Feature di Dunia Venus
Oleh: Hernowo
Hampir setiap
penulis profesional tahu tentang Fog Index--agar tulisannya mudah dibaca:
menulis dengan kata-kata yang sederhana dan aktif, serta kalimat-kalimat yang
pendek, jelas, dan padat-berisi. -GORDON
DRYDEN DAN JEANNETTE VOS
Tulisan yang
bagus biasanya bernada seperti mengobrol. Tentu saja, untuk beberapa topik,
gaya yang lebih formal pasti lebih sesuai--tetapi jangan salah menganggap bahwa
bersikap serius itu sama dengan bersikap membosankan. -COLIN ROSE
"Bumi kini telah menjadi Venus," kata pakar marketing, Hermawan
Kartajaya, dalam karyanya yang menerobos, Marketing in Venus. "Dunia Venus
adalah dunia yang lebih emosional dan interaktif. Di dunia itu, EQ lebih unggul
ketimbang IQ atau--dalam bahasa yang lain--feel lebih penting dari think."
Oleh sebab itu, lanjut Hermawan, "Untuk memenangkan persaingan di Venus,
Anda harus lebih banyak bermain di context (how to offer). Content--what to
offer--yang bagus adalah suatu keharusan. Namun, content yang bagus tidaklah
cukup. Content hanyalah 'tiket' untuk masuk ke arena persaingan, bukan untuk
memenangkan persaingan. Context-lah 'tiket' Anda untuk memenangkan persaingan
di Venus."
Saya berpendapat dari sejak dahulu, apa yang dirumuskan sebagai jenis
tulisan yang dapat dikategorikan sebagai feature (karangan khas) tidaklah
berubah. Merujuk ke pandangan Hermawan, content yang dikandung feature adalah
tetap. Menurut Drs. Andi Baso Mappatoto, M.A.--pernah menjabat Ketua Dewan
Direktur Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara (LPJA)--dalam bukunya, Teknik
Penulisan Feature (Karangan Khas), arti kata feature adalah "karangan
lengkap nonfiksi bukan berita-lempang (straight news) dalam media massa yang
tak tentu panjangnya, dipaparkan secara hidup sebagai pengungkapan daya
kreativitas yang kadang-kadang menggunakan sentuhan subjektivitas pengarang
terhadap peristiwa, situasi, aspek kehidupan dengan tekanan pada daya pikat
manusiawi untuk mencapai tujuan memberitahu, menghibur, mendidik, dan
meyakinkan pembaca".
Dalam kesempatan ini, saya tidak akan membahas content (what atau apanya)
tulisan yang dapat digolongkan sebagai feature. Saya akan lebih menekankan
pembahasan pada context (how atau cara), yaitu bagaimana seorang penulis dapat
menciptakan feature yang menarik dan sesuai perkembangan zaman. Dalam bahasa
Hermawan, saya ingin mengajak siapa saja untuk menulis feature yang dapat
dinikmati masyarakat Venus dan tulisan tersebut benar-benar dapat
"memenangkan" persaingan dalam merebut hati sebagian besar pembaca.
"Memenangkan" di sini saya artikan sebagai sebuah kesuksesan yang
dicapai sebuah tulisan feature dalam menginspirasi atau--dalam bahasa
saya--menyentuh dan kemudian mampu "menggerakkan" pikiran pembacanya.
Untuk keperluan tersebut, saya menggunakan empat tulisan sebagai sumber
rujukan dalam membahas context tulisan feature yang cocok untuk masyarakat
Venus--sebuah masyarakat yang lebih menekankan sisi emosional ketimbang
rasional. Keempat tulisan itu adalah, pertama, karya Ignas Kleden, "Esai:
Godaan Subjektivitas"; kedua, karya Agus R. Sarjono, “Sebuah Bukan Esai
tentang Esai†(kedua tulisan ini dimuat di majalah sastra Horison, edisi
Januari 2004); ketiga, karya Mula Harahap, "Tentang Esai-Esai
Pribadi" (saya peroleh dari sebuah milis di internet); dan keempat, karya
Farid Gaban, "Kolom: Esai dengan Gaya" (pernah disampaikan di depan
para editor Penerbit Mizan).
Feature yang Berbasiskan Esai ?
Tentu saja feature bukan esai, atau esai bukanlah feature. Kata Ignas
Kleden, esai lahir karena keinginan berkata-kata, semacam obrolan dalam bentuk
tulisan. Kalau obrolan adalah bentuk penuturan lisan, maka esai adalah
perwujudannya dalam bentuk tulisan. "Sebuah esai, karena itu," tulis
Ignas, "menjadi prosa yang dibaca karena memikat dan mencekam perhatian,
dan daya tarik itu muncul karena ada bayangan pribadi penulis berkelebat atau
mengendap di sana.
"Apabila kita membaca esai Putu Wijaya, 'Meditasi di Madison', maka
yang menarik di sana bukanlah lukisan pengarang tentang suasana di sebuah
universitas Amerika tempat dia tinggal dan bekerja selama beberapa bulan. Yang
membuat kita tercekam adalah cerita pengarang tentang dirinya sendiri. Kita
turut merasakan betapa dia gugup melatih para mahasiswa Amerika agar dapat
memainkan sebuah teaternya berjudul 'Gerr'. Betapa pula dia kesulitan dan
cemas--dengan bahasa Inggris yang masih terbatas--menjelaskan konsep teaternya
dan berusaha melepaskan para mahasiswanya dari konsep teater barat, sebagaimana
yang mereka pelajari dari kuliah dan latihan yang mereka peroleh
sebelumnya."
Subjektivitas dalam mengutarakan gagasan adalah hal yang memberikan watak
khas pada esai. "Apabila subjektivitas itu dikontrol dan ditekan sampai
minimal, maka yang kita dapati adalah tulisan ilmiah. Seperti kita tahu, ilmu
pengetahuan menuntut lukisan dan uraian dapat diusahakan sedekat mungkin dengan
keadaan suatu objek yang diteliti atau yang sedang diamati, Subjektivitas yang
terlalu banyak dianggap mengganggu dan merendahkan mutu sebuah tulisan. Esai,
sebaliknya dari itu, justru menghidupkan subjektivitas," tulisan Ignas
menegaskan.
Ada banyak jenis tulisan yang bagus di media massa, namun tulisan itu
jarang dibaca oleh para pembacanya. Mengapa? "Hal ini karena banyak
tulisan dalam rubrik opini, misalnya, yang memiliki kecenderungan bernada
kering, tidak 'berjiwa'. Para penulis, lagi-lagi, kadang-kadang punya pandangan
keliru bahwa tulisan analisis haruslah bersifat dingin: objektif, berjarak,
anti-humor, dan tanpa bumbu," tulis Farid Gaban. "Berbeda dengan
menulis untuk jurnal ilmiah, menulis untuk koran atau majalah adalah menulis
untuk hampir 'semua orang'. Tulisan harus lebih renyah, mudah dikunyah,
ringkas, dan menghibur (jika perlu), tanpa kehilangan kedalaman, dan tanpa
terjatuh menjadi tulisan murahan."
Bagaimana agar sebuah tulisan dapat menarik perhatian, renyah, mudah
dikunyah, ringkas, dan menghibur (jika perlu)? "Kreativitas," jawab
Farid Gaban pendek. Kreativitas? Ya. "Dalam era kebebasan seperti sekarang
ini, seorang penulis dituntut memiliki kreativitas yang lebih tinggi untuk
memikat para pembaca. Para pembaca, dewasa ini, memiliki demikian banyak
pilihan bacaan. Lebih dari itu, sebuah tulisan di koran dan majalah tak hanya
bersaing dengan tulisan lain di koran atau majalah lain, tetapi juga bersaing
dengan berbagai kesibukan yang menyita waktu para pembaca: pekerjaan di kantor,
menonton televisi, mendengar musik di radio, berselancar di internet, mengasuh
anak, dan sebagainya."
Farid kemudian mengenalkan satu "genre" baru penulisan esai yang
disebutnya sebagai "creative nonfiction", atau nonfiksi yang ditulis
secara kreatif. "Dalam 'creative nonfiction', penulis esai mengadopsi
teknik penulisan fiksi (dialog, narasi, anekdot, klimaks dan anti-klimaks,
serta ironi) ke dalam nonfiksi. Berbeda dengan penulisan esai yang kering dan
berlagak objektif, 'creative nonfiction' juga memungkinkan penulis lebih
menonjolkan subjektivitas serta keterlibatan terhadap tema yang ditulisnya.
Karena memberi kemungkinan subjektivitas lebih banyak, esai seperti ini juga
umumnya menawarkan kekhasan gaya ('style') serta personalitas si penulis,"
demikian tulis Farid Gaban.
Langkah Menuju Penulisan Feature yang "Menggugah"
Seperti tergambarkan dalam penjelasan Ignas dan Farid tentang bentuk
tulisan esai di atas, feature dapat ditulis secara lebih "menggugah"
apabila si penulis dapat melakukan pergerakan secara tepat dari tulisan yang
bersifat subjektif menuju tulisan yang bersifat objektif. Dalam bahasa
akademis, feature yang "menggugah" adalah feature yang berada di
antara tulisan yang benar-benar bebas dan tulisan yang memenuhi kaidah-kaidah
ilmiah. Atau, mengikuti rumusan Edward de Bono, tulisan tersebut dapat dipenuhi
dengan cara bergerak dari pemikiran vertikal menuju pemikiran lateral. Berikut
ini usulan tiga langkah saya untuk menjadikan diri Anda sebagai penulis feature
yang andal.
Pertama, ketika Anda ingin mengawali kegiatan menulis esai, cobalah
menggunakan metode "mind mapping" (pemetaan pikiran). Metode ini,
setidaknya, akan mendukung Anda dalam membuat jaringan fakta (bahan yang hendak
diungkapkan dalam bentuk feature) secara detail dan terkuasai secara total.
Apabila "peta pikiran" dapat dibuat, si penulis feature dapat
memiliki keyakinan tinggi bahwa bahan-bahan yang dikumpulkan memang hampir
mendekati lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Dan untuk mengecek apakah
bahan-bahan yang sudah dikumpulkan itu memang sangat lengkap (dan kemudian
dapat benar-benar dikuasai), penggunaan metode "mind mapping" (Tony
Buzan) atau "clustering" (Gabriele Rico) dapat sangat membantu.
Kedua, diri si penulis (terutama pengalaman yang sudah dimiliki si penulis)
benar-benar connect dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Apabila ini
dapat dilakukan, maka tulisan feature akan unik. Kata Viki King, "Anda
sedang menulis feature yang tidak mungkin ditulis oleh orang lain. Sebuah kisah
yang berkobar di dalam diri Anda adalah feature yang 'komersial'. Anda tidak
menjadi penulis kelas dua di bawah siapa pun. Anda menjadi yang terbaik bagi
diri Anda sendiri. Anda memiliki satu hal yang layak jual sebagai seorang penulis--sudut
pandang Anda. Sudut pandang Anda adalah sebuah cara unik untuk melihat dunia
berdasarkan seluruh pengalaman Anda dan bagaimana Anda merasakan dunia di
seputar Anda."
Ketiga, awalilah menulis feature dengan memanfaatkan otak kanan. Menurut
Roger Sperry, pemenang hadiah Nobel bidang kedokteran yang menemukan dua
belahan otak, setiap orang punya otak kiri dan otak kanan yang berfungsi secara
berbeda. Proses berpikir otak kiri bersifat logis, urut, dan rasional. Belahan
ini sangat teratur. Sementara itu, proses berpikir otak kanan bersifat acak,
tidak teratur, intuitif, dan holistik. Cara berpikirnya sesuai dengan cara-cara
untuk mengetahui yang bersifat nonverbal, seperti perasaan dan emosi. Dengan
menggunakan otak kanan lebih dahulu, berarti bahan yang akan dialirkan menjadi
lebih terbuka, bebas, dan tidak kaku. Baru setelah semua bahan dikeluarkan oleh
otak kanan, gunakan otak kiri untuk menatanya. Demikianlah, semoga tulisan ini
bermanfaat dan mampu "menggerakkan" pikiran Anda.[]
Mengeksplorasi
Potensi Kecerdasan
Oleh : Hernowo
"Pada akhir tahun 2002, Andrew
Oswald dari Warwick University mempublikasikan sebuah survei atas 2.500 orang
Inggris yang dipilih secara acak. Survei Oswald menunjukkan bahwa penjelajah
Internet lebih banyak yang menjadi anggota grup komunitas atau organisasi
sukarela dibandingkan yang nonpenjelajah Internet.
"Lebih jauh diungkapkan oleh Oswald bahwa para penjelajah Internet itu
kemungkinan besar adalah mereka yang mengunjungi gereja secara teratur, lebih
berpendidikan, dan lebih memiliki penghasilan yang baik ketimbang orang yang
bukan penjelajah.
"Kebalikan dari opini umum yang terdapat di Inggris, tampaknya para
penjelajah Internet sudah mulai dapat menyeimbangkan kehidupan elektronis
mereka dengan kehidupan sosialnya. Mereka tidak terus-menerus membungkuk di
depan komputer sepanjang hari sebagaimana semula diasumsikan. Mereka, ternyata,
lebih jarang menonton televisi daripada rata-rata orang lainnya.
"Ini menyiratkan bahwa ketimbang menggunakan waktu bebasnya untuk kegiatan
yang bersifat pasif, mereka secara aktif menggunakan Internet untuk berhubungan
sosial dengan orang lain."
Laporan tentang survei Oswald ini saya peroleh dari buku Tony Buzan yang
membahas kecerdasan sosial. Secara menarik, Buzan menunjukkan bahwa Internet
dapat memperkaya kehidupan sosial seseorang. Ini berarti, Internet dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kecerdasan sosial seseorang.
Data lain yang menarik juga ditunjukkan oleh sebuah studi yang dilakukan di
Jepang. Seorang spesialis otak, Takashi Tsukiyama, melakukan penelitian ke
sebuah kelompok yang mengalami penurunan daya ingat. Dia tertarik meneliti
kasus tersebut karena surat kabar Straits Times pernah membuat berita yang
kurang lebih menyatakan bahwa "kurangnya interaksi sosial di antara generasi
muda di Jepang menyebabkan menurunnya daya ingat seseorang".
Para peneliti membenarkan hal ini, dan menuding bahwa penyebab utamanya
adalah kecenderungan meningkatnya isolasi sosial di antara orang-orang karena
mereka terlalu bergantung pada mesin-mesin yang secara bertahap mengikis daya
ingat. Banyak orang yang diam dan terkungkung di dalam rumah dan tidak memiliki
kesempatan untuk saling bersosialisasi secara tatap muka. Hal ini dikarenakan
sejak kecil mereka sudah akrab dengan video games.
Menurut para peneliti lebih jauh, sosialisasi membutuhkan kesiagaan
terus-menerus dan daya ingat yang teruji di mana semua indra--yang merupakan
pilar utama daya ingat--digunakan secara aktif. Para peneliti juga menyimpulkan
bahwa mainan dan layar komputer yang bersifat mengisolasi diri menghambat
pertumbuhan daya ingat.
Dalam bukunya itu, Buzan tidak hanya menunjukkan secara menarik tentang
fakta-fakta baru yang mengubah proses pemelajaran berkaitan dengan peningkatan
kecerdasan. Dia, secara terampil dan lugas, juga mengajak para pembacanya untuk
mengeksplorasi setiap jenis kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Bahkan,
buzan juga menunjukkan secara gamblang bahwa jenis kecerdasan yang satu dapat
menunjang pelejitan jenis kecerdasan yang lain.
Ketika Buzan menyinggung kecerdasan spasial atau "picture smart",
dia mengatakan begini: "Termasuk dalam kecerdasan spasial adalah kemampuan
menempatkan atau meletakkan barang dalam suatu lingkungan tertentu sehingga
dapat menimbulkan rasa nyaman dan menyenangkan bagi orang lain. Seni yang
berasal dari negeri Cina kuno yang disebut Feng Shui adalah pemanfaatan
kecerdasan spasial yang diterapkan pada kecerdasan sosial."
Ketika Buzan sampai pada kecerdasan fisik (physical intelligence) atau
dalam bahasa Howard Gardner diistilahkan sebagai bodily-kinestetic
intelligence, dia menunjukkan manfaat kecerdasan ini. Menurutnya, kecerdasan
fisik menyangkut kemampuan menjadikan diri fit secara fisik, leluasa bergerak,
seimbang serta tenang dan semuanya terkendali. Menyantap makanan yang bergizi,
memiliki tubuh yang kuat, lentur, dan bugar juga termasuk dalam kemampuan
kecerdasan ini.
Nah, bila Anda mampu mengembangkan kecerdasan fisik, kata Buzan, lingkungan
teman-teman Anda secara otomatis akan menjadi semakin luas. Hal ini dikarenakan
naluri orang-orang akan membawa mereka kepada seseorang yang sehat, seimbang,
serta penuh semangat dan gairah hidup.
Meskipun Buzan tidak sebagaimana Gardner yang melakukan penelitian, namun
proses penjelajahan Buzan atas pelbagai potensi kecerdasan dapat membantu kita
untuk melihat secara luas dan kaya tentang peran masing-masing kecerdasan dalam
menumbuhkembangkan diri. Saya juga kaget ketika Buzan menemukan tolok ukur yang
dapat digunakan untuk menilai seberapa tinggi kecerdasan verbal atau "word
smart" yang dimiliki seseorang.
"Kecerdasan ini diukur berdasarkan besarnya perbendaharaan kata yang
Anda miliki," katanya. "Lalu juga kemampuan Anda untuk dalam waktu
yang singkat mengerti hubungan antara suatu kata dengan hal-hal lain; sejelas
apa Anda dapat mengekspresikannya, ketajaman Anda dalam melihat hubungan logis
yang terdapat pada kata-kata, dan keanekaragaman imajinasi yang Anda
gunakan."
Meskipun saya ragu ketika Buzan mengaitkan imajinasi dengan kecerdasan
verbal, saya merasakan betapa J.K. Rowling dapat menggegerkan dunia perbukuan,
lewat serial novel fantasi yang fantastis, Harry Potter. Ada kemungkinan besar,
Rowling menjadi salah seorang terkaya di Inggris ya gara-gara kekuatan
imajinasi Rowling yang yang sangat dahsyat itu.
Ketika mengaitkan kecerdasan verbal dengan kecerdasan sosial, Buzan pun
mengajak saya untuk memasuki wilayah yang sungguh mencengangkan saya.
"Dalam percakapan normal, kecerdasan verbal yang berkombinasi dengan
bahasa tubuh merupakan paket yang utuh!" Lantas, Buzan juga menunjukkan
kepada saya, "Renungkanlah bagaimana percakapan, kuliah, pidato, surat,
koran, majalah, buku, Internet, dan puisi telah mempengaruhi hidup Anda dan
hubungan Anda dengan orang lain."
Baik, mari kita berhenti sejenak di sini. Lihatlah diri hebat Anda. Di
dalam diri hebat Anda tersimpan pelbagai potensi kecerdasan yang siap Anda
manfaatkan dan eksplorasi secara luar biasa. Diri Anda dapat menjadi apa saja.
Anda punya kombinasi unik yang setiap saat dapat berubah sesuai keinginan Anda.
Dan itu baru berkaitan dengan kecerdasan lho. Saya kira masih banyak potensi
diri kita yang belum kita ketahui dan kita eksplorasi secara baik dan benar.
Selamat mengeksplorasi diri Anda yang menakjubkan.**
Kegiatan Membaca Berbasiskan “Multiple
Intelligences”.
Oleh : Hernowo
"Seperti yang diungkapkan Elbow dalam risetnya pada
tahun 1973, sulit untuk mengendalikan lebih dari satu gagasan dalam pikiran
secara sekaligus. Tatkala kita menuliskan gagasan kita, hal-hal samar dan
abstrak menjadi jelas dan konkret. Ketika semua pikiran tumpah di atas kertas,
kita dapat melihat hubungan di antara mereka, dan proses itu kemudian dapat
menciptakan pemikiran yang lebih baik. Menulis, dengan kata lain, dapat membuat
seseorang lebih cerdas." -STEPHEN
D. KRASHEN dalam The Power of Reading
Dalam sebuah pelatihan membaca yang dihadiri oleh para guru SD, saya diberi
pertanyaan oleh seorang peserta tentang bagaimana caranya menghilangkan
kejenuhan membaca buku. Pertanyaan itu membawa saya ke Universitas Harvard
tempat Profesor Howard Gardner berasal. Lewat "Project Zero"-nya,
Profesor Gardner kemudian menemukan sebuah teori yang dinamainya Multiple
Intelligences (Kecerdasan Majemuk--selanjutnya saya singkat KM).
KM adalah teori baru pemelajaran yang menunjukkan bahwa kecerdasan yang
dimiliki setiap anak itu tidak hanya satu. Menurut Profesor Gardner, sedikitnya
ada sembilan tipe kecerdasan yang sudah tertanam sejak lahir yang dimiliki
seorang anak. Asal dia tidak mengalami cacat fisik di bagian otaknya, tentulah
kesembilan kecerdasan itu dapat dikembangkan. Bahkan satu atau dua kecerdasan
dapat dikembangkan menuju puncak. Teori KM ini jelas merupakan teori yang mampu
mengubah cara berpikir seseorang berkaitan dengan cara-cara mengukur
kecerdasan.
Apabila KM dikaitkan dengan kegiatan membaca, jelas kecerdasan yang dominan
di dalam membantu seseorang untuk mau dan mampu membaca adalah kecerdasan
linguistik atau word smart. Kegiatan membaca buku adalah kegiatan yang
berkaitan dengan teks. Agar dapat menyerap informasi yang bermanfaat dari buku,
seseorang perlu memiliki keterampilan atau kemampuan mencerna teks. Memang,
kadang, di sebuah buku ada gambar yang menyertai teks. Namun, tetap saja,
gambar kadang tidak mampu menghadirkan makna yang solid. Tekslah yang dapat
diandalkan untuk membangun makna secara utuh.
Saya jelaskan kepada para guru bahwa ketika seseorang menggunakan word
smart-nya, dia juga dapat bersuara. Apa artinya ini? Word smart juga berkaitan
dengan telinga. Merujuk ke sini, jelas bahwa membaca buku tidak harus diam
membisu. Membaca teks dapat juga bersuara sehingga telinga lahir mendengarkan
apa yang disuarakan oleh mulut. Bahkan, menurut kabar, pada zaman dahulu, para
filosof Yunani semacam Socrates atau Plato, jika mengajarkan sesuatu kepada
murid-muridnya lewat buku, mereka membaca buku bagaikan membaca puisi--dengan
suara atau intonasi yang sangat indah dan kadang menggetarkan kalbu.
Membaca buku juga dapat menggunakan kecerdasan matematika atau logic smart.
Bagaimana caranya? Sebelum membaca, seseorang dapat mengkalkulasi pelbagai hal
yang ada di sebuah buku. Misalnya soal ketebalan buku dan berapa jumlah bagian
atau bab yang ada di buku. Lalu juga dia dapat menghitung berapa rata-rata
alinea yang terdapat di setiap lembar halaman buku. Atau, ini yang penting, dia
dapat menghitung kemudahan teks, yang ada di sekujur halaman buku, untuk dibaca
lewat perhitungan "Fog Index". Bahkan "Fog Index" ini juga
dapat mendeteksi secara matematis seberapa tinggi kandungan teks dalam
memberikan motivasi (soal ini tentu memerlukan pembahasan tersendiri), dan
seterusnya.
Apabila dua macam variasi membaca buku sudah dicoba diterapkan, tambahlah
dengan satu kecerdasan lagi bernama kecerdasan gambar (picture smart). Apabila
buku yang dibaca tidak ada gambarnya (bukan buku komik), cobalah berusaha keras
menggunakan daya imajinasi yang kita miliki. Setiap kali membaca deretan teks,
berhentilah sebentar dan bayangkan di benak kita tentang gambaran yang ingin
dimaksudkan oleh si penulis buku. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Atau,
cobalah kaitkan kisah yang dilukiskan si penulis dengan keadaan diri kita? Daya
imajinasi ini, menurut saya, dapat membantu kita juga dalam menafsirkan suatu
makna teks yang terkait dengan karakter diri kita.
Lantas, membaca buku juga dapat menggunakan kecerdasan musik (music smart).
Siapa tahu, dengan menyetel musik lembut yang menyamankan otak kanan akan
membuat kita bersemangat untuk mencerna teks secara luar biasa. Apabila
menyetel musik sudah dilakukan, cobalah juga membaca dengan berdiri atau
berjalan-jalan secara perlahan. Apabila Anda membaca buku dengan cara ini, Anda
sedang menggunakan kecerdasan kinestetik (body smart) Anda. Mungkin Anda jenuh
membaca lantaran Anda terus-menerus duduk dan tidak menggerakkan fisik Anda.
Nah, cara ini dapat dicoba. Sesekali berhentilah membaca dan berdirilah
seolah-olah Anda sedang meraih buah jambu yang ketinggiannya melebihi jangkauan
tangan Anda ketika tangan Anda direntangkan secara vertikal ke atas.
Kecerdasan lain yang dapat digunakan adalah kecerdasan merenung sendirian
atau kecerdasan personal (self smart). Kecerdasan ini tentu sering Anda lakukan
ketika membaca buku. Anda "mojok" sendirian di sebuah ruang yang
hening dan Anda ingin sendirian berkonsentrasi memamah teks-teks yang
berlarian. Ini sah-sah saja. Namun jika Anda jenuh dengan kegiatan semacam ini,
ajaklah istri, anak, atau sahabat Anda untuk ikut "nimbrung" dalam
kegiatan membaca Anda. Apabila hal seperti ini yang Anda lakukan, itu berarti
Anda menggunakan kecerdasan bergaul atau kecerdasan sosial (people smart). Anda
dapat mendiskusikan buku yang Anda baca dengan orang lain dan ambillah
kesimpulan secara bersama.
Atau, apabila Anda punya taman, cobalah membaca buku di taman yang asri
milik Anda. Di taman tersebut, Anda mungkin akan bertemu dengan kupu-kupu yang
sedang terbang. Atau Anda hanya dapat menghirup wewangian yang dilepaskan oleh
pelbagai bunga yang ada di taman tersebut. Atau, siapa tahu di taman itu Anda
memiliki beberapa hewan piaraan seperti burung yang terus berkicau atau
hewan-hewan lain. Jika kegiatan membaca buku yang Anda lakukan ini berlangsung
dalam keadaan seperti di taman itu, Anda berarti sedang menggunakan kecerdasan
alam (nature smart).
Berapa kecerdasan yang sudah Anda gunakan dalam membaca buku sebelum Anda
menggunakan kecerdasan alam? Ada word, logic, picture, music, body, self, dan
people smart. Ada tujuh kecerdasan! Ini artinya, Anda dapat menghilangkan
kejenuhan membaca buku lewat delapan cara (jika ditambah dengan nature smart).
Bayangkan, cara-cara yang saya jelaskan di atas belum menyentuh kombinasi
antara kedelapan cara itu. Misalnya, Anda masih dapat mengombinasikan word
smart dengan nature smart. Atau Anda bahkan dapat menggunakan keseluruhan
kecerdasan tersebut secara serentak. Luar biasa bukan membaca berbasiskan KM?
Nah, kecerdasan terakhir, kecerdasan kesembilan, yang ditemukan Profesor
Gardner perlu dicoba pula oleh Anda. Kecerdasan ini bernama kecerdasan meraih
makna (existence smart). Orang kadang menyamakan kecerdasan ini dengan
kecerdasan spiritual, sebagaimana kecerdasan personal/diri dan kecerdasan
sosial/masyarakat dikaitkan dengan kecerdasan emosi yang ditemukan oleh Dr.
Daniel Goleman. Memang sih sepertinya ada kemiripan antara kecerdasan
eksistensial dengan kecerdasan spiritual. Namun, Profesor Gardner ingin agar
kecerdasan eksistensial ini netral alias tidak dihubungan dengan kebenaran
agama tertentu.
Profesor Gardner memang mencoba berusaha keras agar kesembilan tipe
kecerdasan yang ditemukannya itu dapat diajarkan di sekolah. Artinya, pelbagai
kecerdasan ini selayaknya dapat digunakan oleh guru ketika mengajar dan,
terutama, setiap siswa ketika belajar. Karena dengan memberikan peluang kepada
para siswa agar memahami materi pelajaran dengan pelbagai cara, ada kemungkinan
seorang siswa dapat belajar secara alamiah, yaitu belajar sesuai dengan
karakter dirinya. Apabila seorang siswa dapat menemukan gaya belajar yang khas
dirinya, bisa jadi dia dapat belajar secara nyaman dan menyenangkan, meskipun
yang dia pelajari itu hal-hal yang memiliki kesulitan yang tinggi dan gampang
mendatangkan kebosanan.
Nah, bagaimana mengaitkan kecerdasan kesembilan ini dengan kegiatan membaca
buku? Mudah sekali. Anda tinggal menyusun pertanyaan sebanyak-banyaknya ketika
membaca. Dan tujukan pertanyaan itu kepada si penulis buku. Cuma itu? Ya. Hal
ini dikarenakan kecerdasan eksistensial berkaitan dengan sebuah pencarian yang
sangat intens dan dalam sekali. Apabila Anda menggunakan kecerdasan ini, Anda
akan diajak untuk menggugat, mempertanyakan, dan bahkan bersikap kritis. Saya
suka sekali menggunakan kecerdasan ini untuk mempertanyakan apa manfaat buku
yang sedang saya baca. Kecerdasan ini, di tangan saya, bagaikan alat penggali
yang mampu membantu saya memperoleh makna-makna hebat ketika membaca buku.
Dalam buku Quantum Learning, kedua penulisnya menganjurkan agar apabila
seseorang melakukan sebuah kegiatan, cobalah mempertanyakan lebih dahulu
manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan itu. Kedua penulis mengistilahkan
kegiatan mempertanyakan ini dengan nama AMBAK (Apa Manfaatnya Bagiku?). Nah,
ketika saya menggunakan kecerdasan eksistensial ketika membaca buku, saya pun
sebenarnya sedang mencari manfaat sebanyak-banyaknya dari buku yang saya cerna.
Akibat dari aktivitas mempertanyakan ini, saya kemudian didorong masuk lebih
dalam ke materi yang saya baca di buku tersebut.
Akhirnya, kecerdasan ini juga membantu saya untuk melanjutkan kegiatan
membaca dengan kegiatan penting lain, yaitu menuliskan apa yang saya dapat dari
membaca buku tertentu. Dalam istilah saya, kegiatan lanjutan membaca buku ini
saya sebut sebagai proses "mengikat makna". Setiap kali saya membaca
buku, saya berjanji kepada diri saya sendiri bahwa saya harus mendapatkan
"makna" (manfaat) yang sifatnya saya bangun atau saya konstruksi. Dan
untuk mendapatkan bangunan makna tersebut, saya mau tidak mau harus menuliskan
apa yang saya dapat tersebut.
Bayangkan, kegiatan membaca buku dapat mendorong seseorang untuk juga
berlatih menulis? Betapa tidak menjenuhkannya apabila kita dapat melakukan
kegiatan membaca dengan menggunakan sembilan kecerdasan yang diusulkan oleh
Profesor Gardner. Semoga lewat tulisan ini, saya sudah dapat memberikan jawaban
kepada seorang peserta pelatihan membaca yang bertanya kepada saya. Semoga
tulisan ini bermanfaat dan mendorong Anda untuk membaca buku dengan pelbagai cara
yang terkait dengan potensi diri Anda yang bernama kecerdasan. Selamat membaca
buku.[]
Membangun Citra Diri Lewat Menulis
Oleh : Hernowo
Oleh : Hernowo
.... hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk
keperluan hari esok .... (Al-Hasyr: 18)
Ketika saya membaca buku Marketing Yourself: Kiat Sukses Meniti Karier dan
Bisnis karya Hermawan Kartajaya, saya merasakan sekali gejolak-hebat terjadi di
dalam diri saya yang terdalam (inner-self). Saya merasakan sekali bahwa selama
ini saya seperti kurang memperhatikan diri saya sendiri. Boro-boro
mempedulikan, memperhatikan diri saja rasa-rasanya susah sekali.
Selama hampir setengah abad hidup saya, sudah banyak ilmu yang saya
pelajari. Sejak masuk TK, saya sudah diajari macam-macam--ilmu menyanyi, berbaris,
hormat kepada ibu guru, dan banyak lagi. Masuk ke SD, para guru saya, selama
enam tahun, juga telah memberikan banyak sekali ilmu. Begitu juga ketika di SMP
dan SMA. Apalagi setelah saya menjadi mahasiswa. Rasa-rasanya, setiap hari saya
belajar sesuatu yang baru.
Lantas, apa yang saya lakukan dengan ilmu-ilmu yang saya miliki? Saya
memang tak ingin sekadar mengatakan bahwa ilmu-ilmu yang saya dapat itu sudah
memberikan manfaat banyak kepada keberlangsungan hidup saya. Saya menjadi
seperti ini pada usia hampir setengah abad ini, ya tentu dikarenakan ilmu yang
saya peroleh selama saya bersekolah. Setelah membaca Marketing
Yourself--meskipun, sekali lagi, ilmu-ilmu yang saya dapat itu telah memberikan
manfaat kepada saya--saya ingin tunjukkan kepada para pembaca tulisan saya ini
bahwa ilmu-ilmu yang saya dapat saya rasakan juga berperan mengasingkan diri
saya terhadap diri saya yang lebih dalam.
Agak susah ya kalimat terakhir itu Anda pahami? Begini. Meskipun ilmu-ilmu
yang saya miliki sekarang telah memberikan manfaat, namun ilmu-ilmu itu
sekaligus membuat diri saya menjauh dari diri saya sendiri. Lewat ilmu-ilmu
yang saya dapat, saya seperti didorong untuk bisa lebih memahami keadaan yang
berada di luar diri saya. Ringkasnya, ilmu-ilmu itu membuat saya lebih tahu
banyak tentang hal-hal di luar diri saya ketimbang memahami apa yang ada di
dalam diri saya sendiri. Bagaimana pembaca, kira-kira sudah dapat Anda
pahamikah hal-hal yang ingin saya sampaikan ini?
Semakin banyak ilmu yang saya dapat dari sekolah, semakin terasing diri
saya dengan diri saya sendiri. Saya memang lantas dapat menulis tentang kota
Frankfurt dan London ketika saya berkunjung ke sana. Saya juga dapat menuliskan
keadaan kota Makkah dan Madinah ketika saya berhaji ke Tanah Suci. Saya juga
dapat mengamati rekan-rekan saya ketika bekerja bersama saya. Saya bahkan
kadang dapat melemparkan kritik kepada hal-hal yang terjadi di luar diri saya.
Tentu, semua itu dapat saya lakukan karena saya punya ilmu.
Namun, dapatkah saya merumuskan diri saya secara baik dan benar? Apakah
saya mengetahui apa yang bergejolak di dalam diri saya? Sudah sampai di mana
perjalanan diri saya selama ini? Apakah yang saya cari sudah saya dapatkan?
Sebenarnya tujuan hidup saya itu apa ya? Apakah saya sudah pernah merasakan
cinta yang sesungguhnya? Apakah saya perlu benar-benar merasakan cinta?
Sudahkah saya bahagia? Dalam konteks apa saya berada dalam keadaan bahagia? Apa
yang sudah saya lakukan sehingga yang saya lakukan itu dapat bermanfaat bagi
orang lain? Apakah saya sudah memperbaiki kelemahan-kelemahan saya? Apakah saya
berani mengkritik diri saya secara tajam dan blak-blakan?
Mungkin apabila saya terus menderetkan pertanyaan-pertanyaan tentang diri
saya, sebagaimana yang saya lakukan di atas, kertas yang saya gunakan untuk
menulis ini akan sangat panjang jadinya. Nah, pertanyaan saya yang paling
penting untuk saya tujukan kepada diri saya adalah "Apakah ilmu yang saya
peroleh selama ini sudah membantu saya untuk memahami diri saya?" Saya
ingin secara tegas di sini menyatakan bahwa saya belum memperoleh ilmu untuk
memahami diri saya. Jadi, dengan pernyataan ini, saya kemudian dapat secara
tegas menyatakan hal penting berikutnya bahwa ilmu yang selama ini saya miliki
cenderung untuk tidak membuat saya memahami diri saya sendiri.
Buku Marketing Yourself sungguh mendorong dan mendukung saya untuk mencari
ilmu yang dapat saya gunakan untuk memahami diri saya. Mengapa saya ingin
mendapatkan ilmu yang dapat membantu saya untuk memahami diri saya? Sebab jika
saya tidak bersegera mendapatkan ilmu tersebut, ada kemungkinan ilmu saya yang
lain (di luar ilmu untuk memahami diri) dapat saja bertambah, namun saya
semakin dijauhkan dari diri saya oleh ilmu yang terus bertambah itu. Ini akan
berakibat fatal. Saya bisa berubah menjadi orang yang tidak rendah hati. Saya
bisa menjadi orang yang tidak jujur. Saya juga, ada kemungkinan besar, lantas
bisa menjadi orang yang kadang bersikap arogan karena ilmu saya yang banyak itu
(minus ilmu untuk memahami diri).
Setidaknya, buku Marketing Yourself ini mengingatkan saya bahwa saya perlu
merumuskan diri saya secara segera. Buku ini mengenalkan konsep membangun citra
diri dengan nama "segitiga PDB". PDB adalah singkatan dari
"positioning", "differentiation", dan "brand".
Sebagaimana yang saya pahami atas konsep "segitiga PDB", konsep
tersebut menganjurkan agar seseorang itu dapat memposisikan dirinya di tengah
masyarakatnya. Memposisikan diri berarti mengenali diri dan kemudian meletakkan
diri dalam konteks yang diinginkannya.
Setelah berhasil memposisikan diri, seseorang perlu terus mempertajam
detail tentang dirinya. Proses memposisikan (atau dalam bahasa saya adalah
merumuskan dan mengenali) diri sendiri itu, perlu berlangsung secara kontinu
dan konsisten--kalau perlu setiap hari. Apabila proses itu dapat dilangsungkan
secara kontinu dan konsisten, nanti orang itu akan masuk ke wilayah berikutnya
yang bernama diferensiasi. Artinya, tiba-tiba saja detail diri atau keunikan
diri itu akan mencuat hebat.
Detail atau keunikan diri yang sudah diperoleh seseorang pun perlu dijaga.
Sebab, detail diri itu bisa hilang ditelan perkembangan zaman. Jadi, detail
atau keunikan diri itu perlu diasah terus-menerus sehingga semakin mengkilap
dan terang benderang. Inilah proses yang tidak mudah karena seseorang yang
sudah mencuat keunikan dirinya cenderung untuk merasa "berbeda"
dengan orang lain (dalam bahasa kasarnya, ini bisa disebut dengan
"sombong"). Kesombongan akan merusak baik "positioning"
maupun, yang akan dirusak lebih parah, "differentiation".
Apabila seseorang dapat secara hebat dan konsisten menjaga
"positioning" dan "differentiation"-nya, maka--menurut
konsep "segitiga PDB"--secara otomatis orang tersebut akan memiliki
semacam merek atau citra atau "brand". Sebagaimana produk benda mati
seperti mobil, "brand" tentu akan mampu membuat perbedaan. Bisa jadi
sebuah produk yang fungsinya sama (mobil adalah alat transportasi), namun jika
yang satu lebih kuat "brand"-nya, maka nilai jualnya tentu akan lebih
tinggi. Begitulah seorang manusia yang sudah sampai ke taraf memiliki
"brand".
Apakah konsep "segitiga PDB" itu dapat dikatakan sebagai ilmu
yang dapat membuat seseorang dapat memahami diri? Apakah ini merupakan ilmu
yang dapat membuat seseorang menjadi tidak terasing dengan dirinya apabila
dapat menguasai dan--ini yang penting--menerapkan konsep "segitiga
PDB"? Saya tidak tahu. Ada kemungkinan ya, dan ada kemungkinan tidak. Lho
kok akhirnya, Pak Hernowo tidak dapat memutuskan soal ini secara tegas?
Saya berpendapat, konsep "segitiga PDB" ini akan dapat membantu
seseorang untuk mengenali dirinya. Hanya saya akan menambahkan di sini bahwa
konsep "segitiga PDB" ini baru akan efektif apabila orang yang ingin
memiliki "brand" itu dapat merumuskan dirinya secara tertulis.
Artinya, hanya lewat kegiatan "merumuskan" atau menulis (dalam bahasa
saya, ini disebut "mengikat") ada kemungkinan besar seseorang dapat
dengan cepat dan kukuh memposisikan dirinya, lantas mencari keunikan dirinya,
dan akhirnya membangun citra diri yang baik.
Saya khawatir jika penerapan konsep "segitiga PDB" itu dituliskan
oleh orang lain, ada kemungkinan orang yang akhirnya memiliki "brand"
itu tidak mampu untuk mengendalikan dampak negatifnya (ingat soal
"sombong" yang saya singgung di atas). Apabila seseorang dapat merumuskan
dirinya dan memiliki catatan yang akurat tentang dirinya dalam bentuk tertulis,
bukan saja dia dapat mengatasi dampak negatif tersebut, melainkan juga dapat
terus mengembangkan dirinya secara terprogram dan terarah.
Marilah kita membangun citra diri kita--dalam konteks yang terus membaik
hari demi hari--lewat menuliskan diri kita dalam bentuk catatan harian.[]
Basic Skill
Oleh : Hernowo
Keyakinanku semakin kuat bahwa kegiatan membaca dan menulis dapat membantu
seseorang untuk mengatasi sebagian besar persoalan hidup yang berat-menekannya.
Apabila kegiatan membaca dan menulis dikaitkan dengan pendidikan, keutamaannya
sudah sangat jelas. Buku telah membuktikan kepada dunia bahwa dirinya mampu
membuat peradaban dapat bertahan dalam kebaikan atau, bahkan, terus meningkat
menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi.
Apalagi yang dapat aku kata-katakan tentang buku dan dua macam kegiatan
yang mengiringinya itu? Apakah aku harus terus mencari manfaat dari kegiatan
membaca dan menulis hingga jumlahnya bertambah banyak, sebagaimana aku
senantiasa mengawali kegiatan membaca dan menulisku dengan mencari dan
mendapatkan manfaat?
Aku, misalnya, sudah bertemu dengan psikolog James W. Pennebaker. Aku juga
sudah bertemu dengan neurolog Edward Coffey. Bahkan aku juga sudah bertemu
dengan ahli linguistik Stephen D. Krashen lewat hasil-hasil penelitiannya yang
terkait dengan buku dan kegiatan membaca-menulis. Semua yang kubaca hampir
pasti menyatakan bahwa kegiatan baca-tulis itu sangat bermanfaat bagi
pengembangan diri seseorang yang melakukannya.
Selain itu, aku juga sudah membaca banyak buku yang ditulis oleh para tokoh
hebat yang mampu mengubah dunia. Buku-buku itu mengubah dunia lewat perubahan
yang terjadi pada diri-diri para pembaca buku mereka. Misalnya, Karen
Armstrong, penulis buku menyejarah, Sejarah Tuhan, telah mengubah diriku dalam
menjalankan agamaku. Bahkan secara unik, Karen telah memasukkan kosakata ke
dalam diriku yang teramat kaya berkaitan dengan bagaimana ku harus merumuskan
Tuhan yang kuyakini ada. Karen jugalah yang mengajakku untuk menikmati kekayaan
para penulis zaman dahulu lewat perjalanan panjang membaca teks yang
dilakukannya yang, sungguh, sangat mengasyikkanku.
Aku juga telah mengenali sosok J.K. Rowling, Stephen King, Tony Buzan,
Pramoedya Ananta Toer, Kuntowijoyo, Fatima Mernissi, Ali Syari`ati, Joyce
Wycoff, Thomas Armstrong, Daniel Goleman, Stephen Covey, Ignas Kleden, Ratna
Megawangi, Sindhunata, dan masih banyak lagi penulis "berkarakter"
lewat tulisan-tulisan mereka. Tak terhitung serbuan pengalaman mereka yang
dirumuskan dalam teks-teks yang "menggigit" yang memasuki tubuh dan
jiwaku dan menyatu dengan diriku. Aku benar-benar merasakan perubahan yang
terjadi di dalam diriku akibat "gizi teks" mereka yang menyerbu
diriku.
Sungguh, aku menemukan banyak sekali makna. Makna-makna itu tampil dalam
warnanya yang paling cemerlang dan kadang menyilaukanku. Makna itu tak hanya
berhenti pada kata. Makna itu terus menyerbuku hingga membumbui kehidupan
nyataku. Aku lalu dapat mengutarakan pengalaman mengesanku dalam bentuk yang
komunikatif dan, mungkin, indah. Aku lantas tidak kehabisan kata ketika muncul
sesuatu yang bergejolak dan menyentak di dalam diriku yang harus kutampakkan
secara jelas. Lewat membaca dan menulislah diriku dapat kudeteksi perkembangan
dan pertumbuhannya.
Apalagi yang aku cari dan ke mana lagi aku harus menuju berkaitan dengan
buku? Apakah setelah aku menuliskan pengalamanku ini aku dapat menemukan
sesuatu yang baru? Bukankah aku berkali-kali dibantu oleh kegiatan membaca dan
menulisku untuk senantiasa siap dalam menerima hal-hal baru? Bukankah
buku-bukuku yang kubaca mampu membawaku untuk terbang bebas dalam memandang
dunia secara berbeda? Apalagi yang harus aku kata-katakan soal buku dan
kegiatan membaca-menulis? Apalagi yang harus kutunjukkan kepada pembaca bukuku
tentang kegiatan yang telah membawaku menuju dunia yang baru dan terus-menerus
berubah?
Aku ingin bertanya kepada diriku sendiri. Apakah setiap hari aku memang
hanya membaca buku dan menuliskan sesuatu? Apakah tidak ada kegiatan penting
lain selain membaca buku dan menuliskan sesuatu? Mengapa harus buku dan
kegiatan baca-tulis yang memenuhi kehidupanku? Tidakkah lebih baik mencari
variasi kegiatan lain yang lebih kaya dan beragam ketimbang hanya menekuni dan
fokus pada buku dan kegiatan baca-tulis? Apakah buku dan kegiatan baca-tulis
benar-benar telah menjadikan aku sebagai manusia yang utuh dan memiliki sesuatu
yang layak ditunjukkan kepada dunia?
Tidak mudah untuk menjawab pertanyan-pertanyan itu. Apa untungnya aku
menjawab pertanyan-pertanyan seperti itu? Apakah dengan menjawab
pertanyaan-pertanyaan itu, aku lantas dapat menemukan sesuatu yang lain dan
lebih hebat ketimbang kegiatan membaca dan menulis? Apakah ada pengganti yang
lebih baik untuk memperkaya diri dengan ilmu ketimbang buku? Bagaimana aku
meletakkan semua pertanyaan itu dalam masa-masa sekarang ini? Oh ya, apakah aku
juga harus terus menggenjot kemampuanku untuk terus menulis buku dan buku lagi?
Aku tidak tahu. Aku sudah menulis buku sebanyak hampir belasan buku. Di dalam
diriku, dan sebagian diriku yang telah kukeluarkan dari diriku dalam bentuk
buku, kini masih ada lebih dari lima buku yang siap aku munculkan. Rasa-rasanya
aku tidak kehabisan gagasan. Bahkan, aku heran, gagasan yang aku ambil dari
kedalaman diriku ini tak pernah kering. Aku juga dimudahkan dalam mengalirkan
gagasanku dalam bentuk yang benar-benar tidak terpotong-potong.Kadang, memang,
aku menjumpai tulisanku yang tidak selesai alias baru separuh atau tiga
perempat jadi.
Meskipun begitu, aku merasakan bahwa aku kini tak gampang kesal atau
frustrasi dalam menerima keadaan yang menunjukkan bahwa tulisanku, ternyata,
belum selesai. Aku malah kadang merasa dinyamankan jika sebuah gagasan yang
ingin kukeluarkan belum dapat kutumpahkan semua. Aku merasakan bahwa diriku
tidak dapat harus terus-menerus memenuhi hasratku. Aku harus mengerem
keinginanku dan mengendapkan agar dapat kucicil lagi pada kesempatan lain.
Mencicil adalah temuanku yang luar biasa dalam menerjuni dunia membaca dan
menulis.
Mencicil sangat terkait dengan keberadaan otakku. Mencicil membuat hidup
ini lebih dapat dinikmati dan kemudian menampakkan detailnya secara
perlahan-lahan dan apa adanya. Sungguh, aku diteguhkan oleh Karen Armstrong
ketika dia menunjukkan kepadaku bahwa aku harus berada dalam keadan yang senang
dan toleran terhadap pikiran orang lain jika sebuah teks yang kubaca ingin
menyampaikan makna kepadaku. Metode Karen yang hebat--berkaitan dengan prinsip
membaca dan menuliskan teks--ini sungguh mengeluarkanku dari kegelapan.
Aku memang terasyikkan oleh buku autobiografi Karen, Menerobos Kegelapan.
Aku menemukan kata-kata yang ditulis Karen di buku itu yang sangat menggugahku.
Aku jumpai berkali-kali menuliskan bahwa hidupnya berubah, dirinya berubah, ada
sesuatu yang berubah di dalam eksistensinya sebagai seorang penulis ketika dia
bersentuhan dengan baik teks maupun pengalaman orang lain. Aku yakin sekali
buku dapat mengubah seseorang ke arah yang lebih baik. Aku yakin bahwa kegiatan
membaca dan menulis dapat memberikan kepada orang, yang mau menjalaninya secara
konsisten dan kontinu, sesuatu yang tiada ternilai hargaya.
Aku yakin... bahwa buku dan kegiatan baca-tulis layak dijadikan
semacam--atau memang sudah dari sononya emang sudah disebut sebagai--basic
skill. Apakah aku hanya mengulang-ulang saja hal-hal yang sudah lama diketahui
orang berkaitan dengan tulisanku kali ini?[]
Menuliskan Kehidupan
Oleh : Hernowo
Saya baru paham benar pentingnya "menuliskan kehidupan" setelah
menyampaikan materi "quantum writing" di Universitas Pendidikan
Indonesia, Bandung, pada Rabu, 25 Februari 2004. Pemahaman saya tersebut
tiba-tiba muncrat tak terkira begitu pikiran saya berinteraksi dengan pikiran
para peserta yang ikut mendengarkan "kuliah" saya.
Di tempat acara berlangsung, secara tegas saya membedakan antara menuliskan
kalimat-kalimat sebagaimana biasa kita lakukan sewaktu menjalankan kegiatan
menulis dengan "menuliskan kehidupan". "Menuliskan
kehidupan" ini berarti kita mengeluarkan secara bebas hal-hal yang pernah
kita alami lewat "kendaraan" bernama kata-kata.
Jika kita hanya menuliskan kalimat, kita dapat terjebak pada aturan
berbahasa tulis. Kita harus, seolah-olah, mampu lebih dahulu menyusun sebuah
kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Atau kita dibingungkan
lebih dahulu tentang bagaimana kalimat pembuka, dan sebagainya.
Sementara itu, "menuliskan kehidupan" tidak mempersoalkan aturan
berbahasa tulis dan bisa dimulai dari mana saja. "Menuliskan
kehidupan" lebih bebas ketimbang menuliskan kalimat. Di sini, tampak jelas
bahwa menuliskan kalimat lebih mementingkan "kendaraan"-nya,
sementara "menuliskan kehidupan" lebih mementingkan
"isi"-nya.
Apakah kemudian kegiatan "menuliskan kehidupan" lantas boleh
bebas melanggar kaidah-kaidah kebahasaan? Ada kemungkinan, pada tahap awal ya!
Kan pada tahap awal menulis itu hasil tulisan kita tidak langsung sempurna
bukan? Bagaimana kita dapat menulis jika kita sudah dipenjara oleh
kaidah-kaidah kebahasaan?
Jadi, memang, jika Anda ingin berpindah dari sekadar menuliskan kalimat ke
tahap "menuliskan kehidupan", Anda perlu menyadari bahwa
"menuliskan kehidupan" tidak bisa langsung sempurna. Ada kemungkinan,
pada saat awal menulis, tulisan Anda berantakan. Anda harus menerima lebih
dahulu keadaan ini.
Yang lebih ditekankan pada saat Anda pertama kali "menuliskan
kehidupan" adalah kebebasan, yang hampir-hampir mutlak, dalam mengalirkan
semua hal yang memang ingin Anda alirkan. Jika sebelum Anda berniat menulis ada
keinginan menulis tentang kehidupan Anda yang kaya, misalnya, tetapi setelah
masuk ke praktik penulisan ternyata yang Anda tulis malah kehidupan Anda yang
miskin, ya terus saja menulis.
Apa pun yang Anda pikirkan, ada kemungkinan setelah mewujud menjadi sederet
tulisan, pada tahap penulisan awal, ada kemungkinan tidak sama. Inilah
"menuliskan kehidupan" itu. Anda harus menerima keadaan tersebut.
Bisa jadi isi kepala dan hati Anda jika dituangkan memang lain dengan yang
dipikirkan dan dirasakan sebelumnya. Inilah, sekali lagi, arti "menuliskan
kehidupan".
Nah, tahap lanjut "menuliskan kehidupan", setelah hal-hal awal
tadi, adalah mengendapkan lebih dahulu bahan-bahan tulisan yang sudah Anda
keluarkan dari kedalaman diri Anda. Jangan langsung memperbaiki tulisan
kehidupan Anda. Anda bisa frustrasi jika membarengkan kegiatan mengeluarkan
bahan dengan memperbaiki tulisan. Anda perlu mendiamkannya beberapa jam atau
bahkan sehari.
Biarkan bahan-bahan itu hidup sendiri. Biarkan pula pikiran Anda tumbuh
meninggalkan bahan-bahan tulisan Anda pertama kali yang, mungkin, masih
berantakan. Biarkan. Dan Anda harus menerima kondisi seperti ini.
"Menuliskan kehidupan" perlu kesabaran tinggi dan perlu ada jeda!
Saya yakin, jika Anda sudah terbiasa mengalami tahap-tahap sebagaimana yang
saya jelaskan di atas, Anda akan mengalami peningkatan pesat dalam upaya
"menuliskan kehidupan" Anda. Anda lantas tak terjebak dengan aturan
kebahasaan. Anda sudah mulai berani untuk mengeluarkan apa saja. Anda
kemudian--ini yang luar biasa--menemukan sesuatu yang bermakna dalam menjalani
proses "menuliskan kehidupan" Anda.
Jika Anda sudah terbiasa "menuliskan kehidupan"--misalnya
menuliskan kehidupan Anda setiap hari dengan bahasa khas milik Anda--Anda akan
menjumpai bahwa ternyata tulisan Anda bisa mengalir dan enak dibaca. Siapa yang
menentukan bahwa tulisan Anda mengalir dan enak dibaca? Ya, Anda sendiri, bukan
ahli bahasa!
Andalah yang harus merasakan apakah tulisan kehidupan Anda itu dapat Anda
pahami atau tidak. Bagaimana orang lain akan paham tulisan Anda jika Anda
sendiri kesulitan memahami tulisan Anda sendiri? Jadi, "menuliskan
kehidupan" berarti juga Anda sedang berkomunikasi--tepatnya
berinteraksi--dengan diri Anda sendiri.
Lewat interaksi yang intens--ada kemungkinan Anda perlu memperbaiki tulisan
Anda berkali-kali sehingga Anda menemukan sendiri bahasa khas miliki Anda--saya
yakin bahasa-ungkap-tulis Anda akan sedikit demi sedikit terperbaiki. Saya
yakin sekali jika bahan yang Anda tuliskan itu memang merupakan pengalaman
Anda, dan Anda jujur dalam menuliskannya, bahasa Anda akan mengalir.
Perlu waktu berapa lamakah latihan "menuliskan kehidupan" itu
sehingga yang berlatih dapat merasakan keberhasilannya? Saya tidak tahu.
Andalah yang dapat mengukur keberhasilan diri Anda sendiri. Waktunya bisa
sangat panjang, dan bisa sangat pendek, bergantung kemauan-kuat Anda. Apakah
cepat-lambatnya keberhasilan itu juga bergantung pada "isi" kehidupan
yang dituliskan?
Saya kira tidak. Saya yakin setiap orang punya pengalaman yang berbeda
dengan orang lain. Kualitas kehidupan Anda akan semakin membaik jika dituliskan.
Sebab, lewat proses penulisan kehidupan Anda, Anda akan mampu melihat secara
gamblang proses kehidupan yang Anda jalani. Apakah tulisan Anda merekam
kehidupan Anda yang membosankan, atau yang itu-itu saja, atau ada kehidupan
yang membanggakan Anda?
Apa pun hasil tulisan Anda, jika Anda berhasil "menuliskan
kehidupan" Anda, Anda memiliki peluang mengubahnya secara cepat dan
drastis. Anda dapat mengendalikan dan mengarahkan kehidupan Anda dengan bantuan
tulisan kehidupan Anda. Andalah tuan dari "takdir" Anda yang akan
Anda jalani.
Inilah manfaat-hebat dari "menuliskan kehidupan". Ada kemungkinan
Anda jadi bersemangat untuk mengubah hidup Anda yang tampak biasa menjadi
"berharga". Ada kemungkinan pula Anda mau mencetak kehidupan yang
membanggakan diri Anda dan mewariskannya kepada anak cucu Anda. Inilah manfaat
lebih jauh dari "menuliskan kehidupan".
Jadi, tunggu apa lagi? Ubahlah paradigma Anda tentang menulis. Segeralah
perbaiki cara Anda memandang kehidupan Anda lewat menulis. Dikarenakan
"menuliskan kehidupan" ini tak berpijak pada aturan-aturan menulis
secara kebahasaan, ada kemungkinan Anda--siapa pun Anda--dapat "menuliskan
kehidupan" Anda yang bermakna dan berharga untuk dibaca oleh orang lain.
Selamat "menuliskan kehidupan" Anda yang hebat dan bermanfaat
bagi orang lain. Senang dapat membantu Anda. (Bandung, 25 Februari 2004)
Bahasa Pengalaman
Oleh : Hernowo
Saya barusan digugah oleh kata-kata ciptaan Anthony Robbins. Robins dikenal
sebagai pembangkit motivasi nomor wahid. Karyanya, Unlimited Power dan Awaken
the Giant Within adalah, bisa dikatakan, semacam bacaan "wajib" bagi
hampir semua orang yang ingin merasakan bahwa di dalam setiap diri manusia
tersimpan kekuatan mahahebat.
Kata-kata Robbins yang menggugah diri saya itu saya peroleh dari karyanya
yang lain, Giant Steps. Menurut Deepak Chopra, karya Robbins ini memberikan
peluang bagi setiap pembacanya untuk menjangkau sesama manusia yang sedang
mencari kedalaman hidup yang lebih hakiki dengan cara mengajak kita untuk
merangkul visi pribadi kita selama setahun penuh.
Memang, tak seperti Unlimited Power ataupun Awaken the Giant Within, karya
Robbins, Giant Steps, dipola sedemikian rupa sehingga menjadi bacaan yang
berisi sebanyak 365 halaman pas. Setiap hari, kita diajak untuk merenungkan sesuatu
yang sangat bermakna bagi kehidupan kita. Ini, tentu, luar biasa!
Oleh sebab itulah, Giant Steps diposisikan sebagai buku yang dapat
memberikan inspirasi kepada siapa saja agar mampu menguasai diri setiap hari
selama setahun penuh. Bahkan, secara sangat nyata, buku ini ingin menciptakan
langkah-langkah raksasa bagi setiap orang agar, dalam kehidupan sehari-hari,
dapat terjadi perubahan-perubahan kecil namun menghasilkan perbedaan besar.
Apakah sebuah buku dapat mengajak para pembacanya untuk melakukan
langkah-langkah raksasa dalam mengubah kehidupannya? Bukankah buku hanya
terdiri atas deretan kata-kata? Bukankah buku sifatnya diam dan kadang tidak
secara aktif mempengaruhi dan mengubah diri seorang pembaca buku? Bukankah buku
itu benda mati? Apakah ada buku-buku yang berisi sesuatu yang menghidupkan,
membangkitkan, dan mendorong sesuatu untuk bergerak, berubah?
Saya kira pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan sebelum ini dapat saya
jawab secara negatif--artinya, buku memang tidak mampu mengubah seseorang ke
arah yang lebih baik. Namun, tunggu dahulu pembaca. Saya bisa jadi memang dapat
saja terdorong untuk memberikan jawaban yang negatif seperti itu. Akan tetapi,
yang menjawab seperti itu adalah diri saya yang dahulu, yang belum membaca
Giant Steps-nya Robbins.
Saya kini memiliki jawaban positif setelah membaca buku Robbins. Saya
dipengaruhi. Saya digerakkan. Saya didobrak. Diri saya yang lama, yang karatan
dan seperti tak berdaya menghadapi hidup yang senantiasa berubah,
dihancurleburkan. Mengutip Jung, lewat Giant Steps, seolah-olah diri saya yang
lama sedang mengalami peruntuhan, dan tiba-tiba, secara dahsyat, diri saya yang
baru mengalami pengutuhan.
Ada dua belas kelompok gagasan Robbins di Giant Steps. Dan setiap kelompok
gagasan tersebut dipecah-pecah menjadi unit-unit kecil yang berisi gagasan
Robbins yang lebih detail dan menonjok. Unit-unit kecil gagasan tersebut
akhirnya membentuk benang merah dari inti buku yang dipola menjadi 365 gagasan
terkecil.
Setiap gagasan terkecil dapat dibaca habis dalam satu halaman. Ada halaman
yang penuh berisi kata-kata Robbins, dan ada yang hanya separo. Kayaknya,
setiap halaman memiliki bobot yang sama meskipun jumlah kata-katanya berbeda.
Saya kira, Robbins tidak sedang bermain kata-kata. Robbins, secara cerdik dan
cerdas, sedang memainkan pikirannya lewat kosakata yang sangat kaya dan
terpilih.
Saya ingin mengutip saja satu bagian di buku tersebut yang memperkaya jiwa
saya. Bab ini terletak di kelompok gagasan urutan keenam dan dijuduli dengan
bagus, "Perbendaharaan Kata Sukses". Hari-hari ini, saya memang lagi
tergila-gila dengan kata-kata hebat--katakanlah bahasa yang mampu membangkitkan
jiwa. Saya yakin, kata-kata yang bagus dapat menggerakkan diri seseorang.
Nah, begitu saya sampai ke bab keenam Giant Steps, saya disambut oleh
Aldous Huxley. Huxley adalah orang besar dan memiliki pengalaman luar biasa. Di
halaman awal bab keenam itu, Robbbins mengajak Huxley untuk menyambut para
pembacanya. Lewat kata-kata (lebih tepat "pengalaman") Huxley, Robbins
berkata, "Kata-kata itu membentuk semacam tali yang di dalam tali itu
seseorang mengaitkan dan mengikatkan pelbagai pengalamannya." Saya
tercengang!
Sungguh, saya seperti disodok oleh tongkat yang kekuatan sodokannya tak
terbayangkan oleh pikiran saya. Saya terjengkang dan dipaksa untuk merenungkan
pengalaman saya. Punyakah saya bahasa yang hebat untuk melukiskan pengalaman
saya? Saya merasa bahwa saya punya pengalaman. Dan, yang lebih membuat saya
harus tunduk adalah, kenyataan, bahwa saya memiliki pengalaman selama hampir
setengah abad!
Apakah pengalaman saya, sepanjang itu, cukup berharga bagi saya? Apakah
pengalaman saya bermakna bagi saya dan keluarga saya? Apakah pengalaman saya
sangat kaya? Apakah pengalaman saya berbeda dengan pengalaman orang yang sebaya
dengan saya? Apakah pengalaman saya dapat saya gambarkan? Apakah pengalaman
saya dapat saya bagikan? Bagaimana saya memahami pengalaman saya?
"Kebanyakan orang hanya memiliki perbendaharaan kata sebanyak kurang
lebih ribuan kata. Jika Anda merenungkan bahasa Inggris saja, bahasa terbesar
di dunia, Anda akan menemukan bahwa bahasa tersebut mengandung antara setengah
hingga tiga perempat juta kata. Itu berarti kita, mungkin, hanya memiliki
kira-kira dua persen dari perbendaharaan kata bahasa Inggris.
"Yang lebih parah lagi adalah bahwa kebanyakan orang hanya memiliki
kira-kira selusin kata, mungkin paling banter dua puluh kata, untuk
menggambarkan emosi-emosi mereka yang konsisten mereka alami. Dan dari semuanya
itu, biasanya separo darinya--atau mungkin lebih--merupakan kata-kata yang
menunjukkan emosi negatif.
"Nah," tulis Robbins sedikit menantang para pembaca bukunya,
"seberapa banyakkah kata yang biasanya Anda gunakan untuk menggambarkan
perasaan Anda, entah perasaan itu Anda ekspresikan kepada orang lain atau
kepada diri Anda sendiri? Seberapa banyakkah kata yang bisa Anda tuliskan
sekarang berkaitan dengan emosi Anda? Seberapa banyak?"
Sebelum saya tersadarkan oleh apa yang ditulis Robbins, saya sudah diserang
oleh kata-kata Robbins yang lain, yang didasarkan atas pengalaman Dr. Norman
Cousins. Masih dalam bab keenam, saya dibenturkan oleh Robbins dengan kata-kata
Cousins, "Kata-kata itu bisa mendatangkan penyakit. Kata-kata itu bisa
mematikan! Oleh karena itulah para dokter yang bijaksana sangat berhati-hati
dalam berkomunikasi."
Apakah hanya dokter yang berhak berhati-hati dalam berkomunikasi? Apakah
hanya dokter yang cara berkomunikasinya buruk yang dapat mematikan seseorang?
Bukankah kita, kita sebagai manusia biasa, juga dapat "membunuh"
seseorang lewat bahasa komunikasi yang kita gunakan? Bukankah kita kadang
memarahi orang di tempat yang tak semestinya kita marah? Bukankah kita, kadang,
menyindir seseorang dengan bahasa yang sudah dihaluskan namun tajamnya masih
setajam pisau bedah? Bukankah, lewat kata-kata pula, kita masih sering
"membunuh" semangat orang lain yang ingin bangkit? Dan bukankah kita
sendiri kadang menggunakan kata-kata yang buruk untuk menunjukkan diri kita?
Sungguh betapa dahsyatnya kata. Taufiq Pasiak, dalam karyanya, Revolusi
IQ/EQ/SQ, menunjukkan kepada saya bahwa kata-kata itu--dalam kosakata bahasa
Inggris--memang dapat berubah wujud menjadi "pedang". Coba pindahkan
huruf "s" di kata "words" ke depan. Anda akan menemukan
sebilah pedang yang keluar secara cepat dari himpunan kata tersebut.
Untuk menutup tulisan saya ini, saya ingin mengunci semua pemahaman saya
atas gagasan Anthony Robbins--yang tersimpan di dalam bukunya Giant
Steps--dengan sebuah tanda tanya. Entah kapan saya dapat menjawab tanda tanya
tersebut. Saya berharap para pembaca tulisan saya ini dapat membantu saya untuk
memecahkan misteri kata-kata yang dilontarkan oleh Robbins.
Robbins menulis, "Ketika Anda menggunakan bahasa perlambang, Anda
tidaklah sedang menggambarkan pengalaman Anda yang sesungguhnya, melainkan Anda
sedang menunjukkan kepada orang lain tentang bagaimana Anda merasakannya."
(Bandung, 8 Februari 2004)
Menuliskan
Pengalaman : Bagaimana Saya Membangkitkan Motivasi Menulis
Oleh : Hernowo
Saya hanya dapat menulis apabila yang ingin saya tulis itu benar-benar
sudah menjadi bagian dari pengalaman saya. Kadang saya memang ingin menulis
sesuatu, misalnya untuk dapat dimuat di sebuah koran atau media lain. Kadang
juga saya diminta oleh seseorang untuk dapat mengirimkan tulisan tertentu agar
dapat dimuat di majalah miliknya. Atau, kadang, tiba-tiba saja saya memang
ingin mengeluarkan sesuatu dalam diri saya dalam bentuk tertulis.
Menulis menjadi mudah bagi saya apabila, pada saat awal menulis, saya
memiliki kebebasan mutlak. Memang, orang lain boleh saja menentukan topik untuk
saya tulis. Namun, kendali pertama untuk menuliskannya haruslah ada di tangan
saya. Dan biasanya saya memang mengetikkan topik-permintaan itu di layar
komputer atau di kertas yang sudah saya sediakan. Namun, setelah terketik, saya
langsung saja tidak menghiraukannya. Saya ketik apa saja yang memang ingin saya
ketik. Saya keluarkan apa saja yang memang dapat saya keluarkan.
Apa yang saya lakukan ini kemudian saya ketahui sebagai salah satu teknik
menulis yang disebut sebagai teknik freewriting atau fastwriting. Menulis akan
menjadi sebuah kegiatan yang sangat sulit dan mengesalkan apabila saya tidak
dapat membebaskan diri dari pelbagai penilaian dan ancaman. Keadaan itu akan
tambah parah dan menekan saya apabila terjadi pada saat saya mau mulai menulis.
Saya lalu mencoba mengatasi problem menulis ini dengan cara "membebaskan
diri".
Lalu apa yang sebaiknya ditulis pada saat awal agar seorang penulis
memiliki kendali mutlak saat mulai menulis? Ya menuliskan apa saja. Apa saja?
Ya. Saya biasa menuliskan pengalaman saya yang paling dekat dan paling mudah
diingat. Bisa jadi, topik yang diminta kepada saya itu berkaitan dengan cara
mengatasi kebosanan dalam belajar. Namun, saya memulai menulis dengan mengutip
sebait lagu yang baru saja saya dengarkan dan bait-bait lagu itu mengesankan
saya.
Sungguh, saya sering bertemu dengan hal-hal "ajaib" begitu saya
mulai memijit tombol-tombol huruf di keyboard komputer saya secara
sangat-sangat bebas. Seiring dengan munculnya deretan huruf yang berbaris rapi
di layar komputer yang kemudian barisan huruf itu memberikan makna, saya
kemudian merasakan betapa di kepala saya muncul sesuatu yang berbentuk seperti
"jaringan". Saya merasakan ada semacam kabel yang dengan cepat saling
terjulur dan berhubungan antara kabel yang satu dengan kabel yang lain. Di
kepala saya lantas terjadi hubungan hebat antara pengalaman yang satu dengan
pengalaman yang lain. Bait-bait lagu yang saya ketikkan, yang mula-mula tak ada
hubungannya dengan cara mengatasi kebosanan dalam belajar, tiba-tiba membawa
saya menuju wilayah yang di dalamnya saya pernah mengalami suatu pembelajaran
yang sangat menyenangkan.
Setelah itu, secara sangat cepat, saya seperti didesak, didorong,
diempaskan oleh semacam gelombang dahsyat yang datang bagaikan air bah. Saya
lalu dengan mudah mengalirkan apa yang mendesak itu lewat barisan kata-kata.
Kalau sudah begini, wah, saya jadi sangat asyik menulis dan dapat terus
bertahan hingga seluruh gelombang dahsyat itu habis saya keluarkan. Apakah
tulisan kemudian selesai? Apakah kadang saya mengalami juga semacam kemacetan
menulis meskipun sudah tujuh puluh lima persen bahan-bahan teralirkan keluar?
Ada kemungkinan tulisan memang tidak selesai pada waktunya atau pada saat
saya termotivasi menulis. Atau, begitu saya asyik menuliskan apa yang ingin
saya tulis, tiba-tiba mesin berpikir saya ngadat alias berhenti total. Ini
bagaikan lampu yang sudah menyala sangat terang tiba-tiba aliran listrik putus
dan lampu itu padam--byar kemudian pet! Jelas saya sering mengalami hal-hal
seperti ini. Apa yang kemudian saya lakukan? Ya saya berhenti saja. Kadang saya
ngomel dan kadang saya menyabari keadaan seperti ini. Sebab apa lagi yang dapat
dilakukan oleh seorang penulis apabila tiba-tiba dia mengalami kemacetan dalam
menulis?
Kalau, ternyata, kemudian kemacetan itu terus melanda bagaimana? Saya
biasanya mengatasi problem ini dengan kembali membaca buku. Buku apa saja.
Mengapa buku apa saja dan bukan buku yang relevan dengan topik yang hendak
dituliskan? Maksud saya dengan pernyataan "buku apa saja" adalah buku
yang kemungkinan besar berkaitan dengan topik yang hendak ditulis. Namun, saya
juga menganjurkan agar membaca buku yang lain. Siapa tahu kemacetan itu justru
dapat diatasi lewat jalur yang tidak lazim. Dan saya sering mengalami menemukan
cara mengatasi kemacetan menulis lewat cara yang tidak lazim.
**
Motivasi menulis saya semakin berkobar-kobar setelah berkali-kali
mendapatkan sesuatu yang kadang mencengangkan setelah saya selesai menulis,
meskipun tulisan yang saya tulis belum selesai. Apa yang saya peroleh setiap
kali selesai menulis? Kepuasan? Mungkin ya. Namun, yang sangat saya nikmati
adalah kelegaan atau rasa plong yang luar biasa. Begitu saya selesai menulis,
beban-beban yang menusuk-nusuk pikiran dan jiwa saya seakan-akan hilang, musnah
terseret oleh kata-kata yang saya coba tuliskan di layar komputer atau di
selembar kertas.
Mengapa bisa begitu? Ini lantaran, dalam menulis, saya senantiasa
berprinsip bahwa yang ingin saya tulis adalah apa yang berkaitan dengan diri
saya. Mau menulis tentang teori baru pembelajaran kek, atau mau menulis tentang
demonstrasi mahasiswa kek, atau yang lain, saya harus yakin bahwa diri saya
terlibat penuh di dalam tulisan-tulisan saya. Itu prinsip saya. Jadi, tulisan
saya adalah juga karakter saya--apa yang memang betul-betul milik saya.
Oleh karena itulah saya senantiasa menganjurkan kepada siapa saja yang
ingin menjadi penulis agar memiliki lembar-lembar catatan harian. Saya sendiri,
setelah mengetahui bahwa menulis dapat "menyembuhkan", lalu berusaha
keras untuk menuliskan apa saja tentang diri saya setiap hari. Saya menuliskan
catatan harian saya tidak hanya di kertas-kertas lembaran atau buku tulis. Saya
kadang bahkan memanfaatkan handphone untuk mencatat secara ringkas apa yang
berkelebatan di pikiran dan hati saya. Selain kertas dan hp, saya biasa juga
lari ke komputer dan menulis secara sangat cepat di situ.
Catatan-catatan harian saya terus saya perhatikan. Sekecil dan seremeh apa
pun kandungan catatan harian saya itu, saya senantiasa mempedulikannya dan,
terutama, saya rawat. Saya merawatnya dengan membacanya kembali dan
menumbuhkannya. Kadang catatan yang ada di hp, saya pindahkan ke layar komputer
dan saya kembangkan menjadi sebuah tulisan yang hidup dan bergizi. Kadang
coretan-coretan yang tak keruan di buku-buku tulis saya, saya coba tata dan
strukturkan kembali sehingga menjadi semacam himpunan gagasan yang sistematis
dan tersusun rapi. Saya tak lelah-lelahnya untuk memberi pupuk kepada
tulisan-tulisan mentah saya. Pupuk itu biasanya saya peroleh saat membaca buku
atau berdiskusi dengan teman-teman saya.
Membaca dan menulis bagi saya merupakan dua kegiatan yang saling
komplementer. Yang satu mendukung yang lain. Apabila dua kegiatan ini dapat
kita lakukan secara serempak, insya Allah, dua kegiatan ini akan menjelma
menjadi kegiatan yang efektif (ada efeknya terhadap perkembangan diri kita) dan
menyenangkan. Menyenangkan? Ya, ini lantaran apabila kegiatan yang satu macet,
kegiatan yang lain dapat mengatasi kemacetan itu. Saya telah membuktikannya
berkali-kali pada saat saya mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat buku
Mengikat Makna dan Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza.
**
Bagaimana agar kita dapat termotivasi untuk sangat bergairah menulis
artikel popular di koran, artikel ilmiah di jurnal, dan juga skripsi? Sebelum
saya melangkah ke tulisan-tulisan yang dapat dikonsumsi publik secara luas dan
beragam, saya berprinsip bahwa saya harus memecahkan lebih dahulu
kendala-kendala internal dalam menulis. Menurut saya, menulis artikel untuk
dapat dikonsumsi publik akan terasa sulit dan berat bagi saya apabila saya
belum dapat memecahkan kendala-kendala menulis yang bersifat internal. Apa itu,
sebenarnya, kendala menulis secara internal? Dan adakah juga kendala menulis
secara eksternal?
Kendala menulis yang bersifat internal sudah saya coba jelaskan di
bagian-bagian terdahulu. Saya memecahkannya dengan membuat catatan harian dan
mempersepsi menulis sebagai sesuatu yang dapat menyembuhkan diri saya. Kata
"menyembuhkan" di sini memiliki arti yang sangat luas dan bermakna
bagi saya. Pertama, menulis dapat membantu saya "mengikat" episode
kehidupan saya yang mengesankan saya. Apabila saya dapat terus mengingat
hal-hal berharga yang saya lakukan setiap hari, saya tentu saja akan
bersemangat untuk terus hidup bukan?
Kedua, menulis dapat membantu saya menghilangkan tekanan-tekanan yang
datang membanjir dari luar diri saya. Misalnya, ada pekerjaan kantor yang sulit
dan tidak dapat saya rampungkan pada waktunya. Biasanya ini sangat menekan diri
saya. Saya tidak dapat tidur dan terus dibebani dengan ketakselesaian itu. Nah,
dengan menulis, saya kemudian dapat mengekspresikan seluruh apa yang menyesaki
jiwa saya. Saya berusaha mengosongkan pikiran dan hati saya dengan membuang
semua hal yang mengganggu. Saya lalu plong. Bukankah hidup jadi nyaman dan bisa
dinikmati apabila jiwa kita lapang dan lega, tidak sesak oleh masalah melulu?
Ketiga, menulis dapat memunculkan hal-hal baru. Saya terbantu sekali
mengumpulkan pengalaman saya dan kemudian mengombinasikan pengalaman saya dalam
versi yang berbeda-beda untuk memunculkan pengalaman baru yang lain lewat
menulis. Menulis bagaikan memetakan pengalaman konkret diri saya. Ada
pengalaman yang masih mentah, dan ada juga yang sudah kebablasan dan harus
distop. Ini semua tampak jelas apabila kita tuliskan dan kita baca tulisan kita
itu. Saya kira inilah salah satu manfaat besar "menyembuhkan" itu.
Bukankah dengan adanya sebuah peta pengalaman hidup yang tertata dan tergambar
dengan jelas, kita lalu dapat melalui hidup kita dengan enak dan ringan?
Tentu saja, masih banyak sisi "menyembuhkan" yang saya dapat dari
menulis. Namun, saya hentikan saja soal ini sampai di ketiga hal tersebut. Saya
akan mencoba mengakhiri tulisan sederhana saya ini dengan menunjukkan adanya
kendala-kendala yang bersifat eksternal dan bagaimana saya mengatasinya.
Sebelum saya menguraikan soal ini, sebaiknya--apabila benar kita mau menjadi
seorang penulis yang andal--pecahkan lebih dahulu kendala-kendala yang bersifat
internal, baru kemudian melangkah ke pemecahan kendala yang bersifat eksternal.
Apabila saya ingin menulis untuk dapat dikonsumsi orang banyak, saya
biasanya lalu memikirkan kebutuhan orang banyak itu dan bukan kebutuhan saya.
Yang lebih parah lagi, saya biasanya lalu terjebak pada aturan-aturan menulis
yang disyaratkan oleh, misalnya, tulisan ilmiah atau tulisan untuk media massa.
Inilah salah satu kendala yang bersifat eksternal itu. Saya biasanya lalu sibuk
mempelajari aturan dan lupa bahwa saya sebenarnya harus menuliskan terlebih
dahulu apa yang hendak saya tulis. Biasanya, setelah itu, saya lalu kehilangan
kepercayaan diri dan akhirnya potensi menulis saya atau, bahkan, semangat
menggebu saya mendadak lenyap dan sulit saya munculkan lagi.
Kendala eksternal lain dalam menulis--yang biasanya sangat mengganggu
saya--adalah ketaktersediaan bahan untuk dituliskan. Misalnya, beberapa waktu
lalu sempat ramai tentang kurikulum baru yang bernama Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK). Saya tertarik dan ingin sekali menulis di salah satu koran
tentang soal ini. Sudah saya tulis dan sudah saya revisi berkali-kali tulisan
saya itu, namun kok ya rasa-rasanya tidak sempurna dan masih banyak kekurangan.
Akhirnya, betul, saya kirim ke sebuah koran, dan beberapa hari kemudian artikel
saya itu dikembalikan.
Saya lalu merenungkan soal ini dan apa sebenarnya yang terjadi. Ada
kemungkinan, artikel saya tak dimuat lantaran ada artikel yang lebih bagus.
Bisa jadi, artikel saya bagus, namun tidak tersedia ruang di koran itu untuk
dapat memuatnya. Atau, artikel saya memang tidak bagus alias masih belum layak
untuk dipublikasikan di media massa. Atau, ada faktor-faktor lain yang tidak
saya ketahui yang menyebabkan artikel saya tidak bisa dimuat di koran itu.
Saya biasanya menyimpan artikel saya yang gagal dimuat di media massa.
Kadang, saya membacanya lagi (karena saya senantiasa menyimpan apa pun tulisan
saya baik yang belum jadi maupun yang sudah jadi) dan menemukan bahwa artikel
saya masih belum utuh. Kalau saya menemukan artikel lain yang senada yang telah
dimuat di koran, saya kemudian membandingkannya. Saya terus belajar untuk
memperbaiki tulisan-tulisan saya yang akan "hidup" di masa datang.
Nah, dari pembelajaran itu, saya mendapatkan sesuatu yang berharga. Kadang
pada saat saya punya keinginan menulis, saya mungkin belum benar-benar mengecek
apakah bahan-bahan yang hendak saya tulis itu ada di dalam diri saya atau
tidak. Apabila bahan-bahan itu tanggung dan kurang lengkap, bisa jadi akan
menyebabkan tulisan yang sudah jadi itu tidak bertenaga alias biasa-biasa saja.
Atau, kalau bahan-bahan kurang lengkap, ada kemungkinan saya tak dapat
menyelesaikan tulisan itu atau, kadang, saya mengalami kemacetan di tengah
jalan.
Bagi yang suka mempelajari teknik menulis, ada satu teknik lagi untuk
memecahkan soal apakah kita punya bahan atau tidak. Teknik itu bernama
clustering atau mindmapping. Selain teknik freewriting atau fastwriting, teknik
yang saya sebut belakangan ini juga sering saya gunakan. Kadang-kadang efeknya
sungguh tidak saya duga. Saya betul-betul merasakan, ketika menggunakan teknik
ini, bahwa menulis yang dulu saya anggap sangat berat, ternyata dapat sangat
menyenangkan. Bahkan, kabar terakhir yang saya dengar, teknik clustering ini
juga dapat memicu seorang penyair untuk mengalirkan sekaligus menciptakan
sepenggal puisi yang menggigit.
Teknik clustering atau mindmapping ini didasarkan pada fakta bahwa otak
kita terdiri atas dua macam belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan.
Menurut para peneliti bekerjanya otak, masing-masing belahan itu bekerja dengan
cara yang sangat berbeda. Nah, menulis, menurut para pakar otak itu merupakan
kegiatan yang menggabungkan dua belahan otak kita. Apabila kita hanya
menjalankan satu belahan saja, maka yang terjadi adalah pelbagai kerepotan dan
frustrasi dalam menulis.
Di samping untuk mengecek apakah kita punya bahan atau tidak, teknik ini
juga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan membaca. Teknik
ini, hebatnya, juga mencoba memadukan aktivitas visual dan aktivitas tekstual
secara bersamaan. Intinya, apabila kita mau mengingat dan proses mengingat itu
diharapkan dapat bertahan cukup lama, maka gunakan teknik mindmapping (pemetaan
pikiran). Salah satu aktivitas membaca yang sangat penting adalah mengingat dan
mengait-ngaitkan. Nah, teknik ini, apabila dapat dilatih secara rutin dan
konsisten oleh seorang penulis, maka tidak hanya tes-bahan saja yang dapat
dilakukan, melainkan juga untuk mengefektifkan kegiatan membaca.
Pesan saya, cicillah bahan-bahan tulisan yang ada di dalam diri kita itu
secara rutin dan konsisten dengan mengeluarkannya perlahan-lahan. Dengan
menuliskan secara mencicil, kita sebenarnya sedang berupaya keras untuk
memecahkan kendala internal. Kalau kendala internal bisa kita pecahkan, saya
percaya sekali bahwa kendala eksternal akan lebih mudah kita atasi.
Demikianlah sedikit cerita saya tentang bagaimana membangkitkan motivasi
untuk mau menulis. Semoga bermanfaat. Bandung, 9 April 2003
Gimana Sih Cara Membuat Artikel Ilmiah
yang “Enak dan Perlu Dibaca "?
Oleh : Hernowo
Dalam segala
urusan hidup, sungguh sehat apabila sesekali kita menaruh tanda tanya besar
terhadap perkara-perkara yang sudah diterima sebagai kewajaran sampai tak
pernah dipertanyakan lagi. -Bertrand Russell
Dalam upaya memompa semangat saya menulis makalah ini, saya ingin menyandarkan
diri saya di "bahu" sang filosof Bertrand Russell. Saya memperoleh
kata-kata sakti Russell itu dari buku yang juga hebat karya Wandi S. Brata, Bo
Wero: Tips mBeling untuk Menyiasati Hidup (Gramedia, 2003). Kata-kata sakti
Russell itu kayaknya pas apabila saya gunakan untuk menyoroti syarat-syarat
penulisan karya ilmiah dan, setelah memahami syarat-syarat itu, apakah kita
lantas termotivasi dan dapat menulis sebuah karya tulis ilmiah?
Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin merumuskan lebih dahulu apa
yang saya maksud dengan tulisan yang--sebagaimana judul besar makalah saya
ini--"enak dan perlu dibaca". Setelah saya menunjukkan kepada para
pembaca mengenai maksud saya tersebut, saya baru akan menyajikan
pendapat-pendapat saya berkaitan dengan karya tulis ilmiah, terutama dalam
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Saya berharap materi yang saya
siapkan dan tulis ini dapat memberikan "mata baru" dalam memandang
karya tulis ilmiah dan dalam mencoba membuat sebuah karya tulis ilmiah dengan
cara-cara yang tidak sebagaimana lazimnya.
Nah, apa yang saya maksud dengan tulisan yang "enak dibaca"? Ini
sebenarnya merupakan slogan majalah Tempo, tetapi akan saya maknai sendiri.
Yang saya maksud dengan "tulisan yang enak dibaca" adalah tulisan
yang ditata sedemikian rupa oleh seorang penulis sehingga tulisan tersebut,
apabila dibaca seseorang, dapat menjelma bagaikan obrolan. Lho obrolan itu 'kan
tidak dapat dikategorikan sebagai komunikasi ilmiah? Dalam karyanya yang sangat
inspiratif, K.U.A.S.A.I Lebih Cepat: Buku Pintar Accelerated Learning (Kaifa,
2003), Colin Rose mengatakan, "Tulisan bagus biasanya bernada seperti
mengobrol. Tentu saja, untuk beberapa topik, gaya yang lebih formal pasti lebih
sesuai---tetapi jangan salah menganggap bahwa bersikap serius itu sama dengan
bersikap membosankan."
Lalu, apa yang saya maksud dengan tulisan yang "perlu dibaca"?
Ini juga merupakan slogan majalah Tempo. "Tulisan yang perlu dibaca"
adalah tulisan yang membuat siapa saja yang membaca tulisan itu lantas
terbangkitkan selera membacanya. Apabila selera membacanya terbangkitkan,
tentulah dia akan bergairah membaca dan akan membaca tulisan tersebut dengan
perasaan senang tiada tara. Dan, biasanya, ukuran "perlu" ini saya
sandarkan pada tiga hal: (1) memenuhi kaidah penalaran (reasoning), (2) penulis
melakukan pemilihan kata (diksi) yang baik dan akurat, serta (3) mengandung
koherensi dan komposisi yang baik dalam setiap kelompok gagasan yang
dirumuskan.
Apa Saja Syarat-syarat Penulisan Karya Ilmiah?
Dalam menuliskan bagian ini, saya menggunakan dua buku. Sebenarnya ada
banyak buku yang membicarakan bagaimana membuat karya tulis ilmiah. Namun, agar
kebingungan saya tidak terlalu bertumpuk-tumpuk dan tugas saya membaca dapat
sedikit dikurangi, maka saya memutuskan menggunakan dua buku saja. Tentu saja,
saya tidak langsung memutuskan hanya menggunakan dua buku yang telah saya
pilih. Saya memutuskan menggunakan dua buku yang saya pilih lantaran saya sudah
membaca juga yang lain dan saya merasakan bahwa dua buku yang saya pilih ini
dapat mewakili buku-buku lainnya.
Dua buku yang saya gunakan, pertama, adalah hasil suntingan Harun Joko
Prayitno, M. Thoyibi, dan Adyana Sunanda. Buku hasil suntingan ketiga orang
tersebut berjudul, Pembudayaan Penulisan Karya Ilmiah, terbitan Muhammadiyah
University Press. Saya menggunakan edisi cetakan ketiga, yang diterbitkan pada
Mei 2001. Melihat edisi cetakannya, buku ini cukup diminati konsumen. Terbukti,
setelah cetakan pertama pada Maret 2000, buku ini dicetak kedua kalinya pada
Oktober 2000. Dari pengantar edisi cetakan ketiga, dapat kita baca pula bahwa
buku ini mendapat respons yang bagus. Selain itu, di edisi cetakan ketiga ini
beberapa materi disempurnakan dan ditambah.
Buku ini disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil "Pelatihan Penulisan
artikel Ilmiah Perguruan Tinggi" yang diselenggarakan di Lembaga
Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terdiri atas enam bagian, buku
ini telah menunjukkan secara hampir lengkap tentang apa yang harus disiapkan
oleh seorang penulis apabila ingin menulis karya ilmiah. Bagian Pertama
membahas "kebijakan dan pengembangan jurnal ilmiah di perguruan
tinggi". Bagian Kedua membahas "anatomi karya ilmiah", yang di
dalamnya terdapat Bab "Pengertian dan Kriteria Karya Ilmiah", Bab
"Anatomi Artikel Ilmiah", Bab "Sistematika Artikel Ilmiah Hasil
Penelitian untuk Publikasi", dan Bab "Hak, Kewajiban, dan Tanggung
Jawab Penulis".
Bagian Ketiga membahas "pengorganisasian gagasan karya ilmiah";
bagian keempat membahas "bahasa dan teknik penulisan ilmiah" (di sini
dibahas masalah penggunaan bahasa, teknik pengutipan, dan penyuntingan); dan
Bagian Kelima membahas "resensi buku". Sementara itu, bagian
terakhir, Keenam, berisi lampiran-lampiran. Ada tiga macam lampiran, yaitu (1)
majalah berkala yang disempurnakan, (2) kode etik ilmuwan Indonesia, dan (3)
kriteria artikel ilmiah hasil penelitian. Saya tertarik untuk membaca lebih
dulu bab lampiran ini lantaran di dalamnya disebut-sebut tentang karya ilmiah
yang dapat digunakan untuk keperluan promosi staf di kalangan perguruan tinggi.
Di sini ditunjukkan secara gamblang tentang instrumen evaluasi sebuah karya
ilmiah yang dapat digolongkan sebagai "yang terakreditasi". Instrumen
evaluasi ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun
1995.
Buku kedua yang saya gunakan berjudul Menulis Karya Ilmiah: Artikel,
Skripsi, Tesis, dan Disertasi (PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) yang ditulis
oleh Etty Indriati, Ph.D. Apabila buku pertama ketebalannya mencapai hampir 300
halaman, buku kedua ini tipis, hanya 120 halaman. Saya memilih buku karya Dr.
Etty ini lantaran dia menulis berdasarkan pengalamannya saat menyusun disertasi
di University of Chicago. Lalu, yang membuat saya tertarik--selain ringkasnya
buku karyanya ini--Dr. Etty pernah ikut belajar di Sekolah "Ilmu Menulis
Karya Ilmiah" yang ada di Universitas Chicago yang bernama The Little Red
Schoolhouse of Chicago. Apakah sekolah yang disebutkan ini beneran atau tidak,
namun, sekali lagi, menarik perhatian saya.
Satu lagi yang menarik perhatian saya adalah apa yang ditulisnya di bagian
akhir pengantarnya. Dr. Etty menulis, "Scott Anderson di University of
Chicago sering menanyakan 'what do you mean?' pada waktu membaca tulisan
penulis, yang memaksa penulis mencermati kembali tulisan yang tidak jelas pemaparan
makna." Mengapa saya tertarik? Perhatikan pertanyaan dari Anderson,
"What do you mean?" Saya kira, Anderson benar bahwa inti menulis itu
sebenarnya adalah menunjukkan "makna". Atau, tulisan kita akan
menjadi sangat efektif apabila ada maknanya dan bisa dimaknai.
Oleh sebab itulah saya memahami sekali ketika Dr. Etty mengatakan pula
pentingnya berkomunikasi secara jelas dalam menulis karya ilmiah. "Menulis
karya ilmiah," tulis Dr. Etty, "pada dasarnya adalah cara ilmuwan
berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi yang baik bisa membuat yang diajak
berkomunikasi mengertai apa yang dimaksudkan oleh komunikator. Sama halnya
penulis yang baik harus bisa membuat pembaca mengerti apa yang dimaksudkan
penulis tanpa arti ganda. Dengan demikian, penulis harus lebih dahulu memahami
apa makna yang akan disampaikan kepada pembaca sebelum menuangkan gagasannya ke
atas kertas. Dengan kata lain, menulis adalah kegiatan berpikir selain
berkomunikasi."
Terdiri atas empat bab dan dua macam lampiran, buku ini sudah mampu memberikan
gambaran tentang apa sih tujuan seseorang menulis karya ilmiah dan bagaimana
meraih tujuan itu secara benar. Pada Bab Keempat, penulis dengan bagus
menambahkan satu bahasan materi yang penting, yaitu ihwal menyiapkan
presentasi. Ada dua macam presentasi yang dibahas penulis, yaitu prersentasi
lisan dan presentasi poster. Dan di bab lampiran, ditunjukkan macam-macam
tulisan ilmiah yang terdiri atas sebelas macam disertai penjelasannya. Lalu,
yang menarik, ada satu lampiran yang bisa difungsikan sebagai "check
list", yaitu "Daftar Pemeriksaan Bagian-bagian Tulisan". Dalam
menyiapkan sebuah tulisan, apalagi sebuah buku, daftar periksa itu sangat
penting agar seorang penulis dapat meneliti kembali apa-apa yang ditulisnya.
What Is To Be Done?
Ya, apa yang dapat dilakukan oleh seorang terpelajar setelah memahami
syarat-syarat penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana disebutkan dalam
buku-buku yang membahas soal itu? Apakah sang terpelajar itu lantas secara
cepat dapat terbangkitkan gairahnya untuk menulis karya ilmiah? Atau, sang
terpelajar itu seperti saya, yaitu tertunduk lesu dan merenungkan betapa banyak
syarat-syarat yang diperlukan agar sebuah tulisan dapat disebut sebagai tulisan
ilmiah? Apa yang sebaiknya saya lakukan setelah memahami syarat-syarat itu?
Setelah membaca buku-buku berkaitan dengan cara, syarat, dan kriteria
sebuah karya ilmiah, tiba-tiba di kepala saya banyak berjejalan pertanyaan yang
harus saya keluarkan. Mengapa sedikit sekali buku-buku ilmiah yang menarik
perhatian yang beredar di pasaran di Indonesia? Mengapa sebagian besar textbook
kita masih menggunakan buku-buku yang ditulis oleh para sarjana dari Barat?
Mengapa dosen-dosen kita tidak mencoba menyiapkan buku ajarnya sendiri yang
menarik dan dapat dikonsumsi oleh para muridnya dari tahun ke tahun? Apakah
menulis karya ilmiah itu sulit? Apakah menulis buku ilmiah itu tidak laku di
pasaran?
Apa sebenarnya yang terjadi dengan budaya menulis-ilmiah di kalangan para
terpelajar kita. Saya duga, setiap tahun ada ratusan skripsi, tesis, disertasi
yang dimunculkan oleh perguruan-perguruan tinggi kita. Saya kira juga, ada
banyak makalah, laporan ilmiah, artikel-artikel berbobot, yang terus mengalir
dari kaum terpelajar kita. Namun, mengapa gairah menerbitkan buku ilmiah yang
dapat dinikmati oleh masyarakat luas kayaknya tidak muncul? Apa yang
menyebabkan karya-karya ilmiah yang tersimpan di universitas kita lantas bisa
dicap tidak layak dibukukan? Apakah ini benar? Apakah keilmiahan bertentangan
dengan komersialitas? Apakah keilmiahan tidak sewajarnya disebarkan di tengah
masyarakat? Atau, saya salah mempertanyakan hal ini? Atau, ada hal-hal lain
yang lebih mendasar yang layak kita bahas lebih dahulu sebelum melontarkan
pertanyaan seperti ini?
Bagaimana mengubah keadaan yang melanda dunia kampus kita yang sepertinya
terasingkan dari kemeriahan penerbitan buku-buku orisinal dan yang memuat
hal-hal baru sebagaimana ditunjukkan secara sangat lantang oleh Amazon.com
ataupun oleh majalah mingguan Publishers Weekly? Mungkin puluhan, atau bahkan ratusan
buku, baik itu ilmiah maupun nonilmiah, terus memenuhi planet kita ini apabila,
secara rutin, kita mau berkunjung ke situs-situs penjual buku di Internet. Tak
hanya berhenti di situ. Planet kita juga dipenuhi oleh gagasan-gagasan baru
dalam menampilkan buku. Buku, pada saat ini, tidak hanya berisi teks melulu
(meskipun teks tetap penting), namun juga sudah dipermak sedemikian rupa
sehingga di dalamnya tersaji gagasan-gagasan hebat yang ditampilkan lewat
paduan bahasa kata dan bahasa rupa. Apakah hal-hal seperti ini juga menyentuh
dunia kampus kita?
Saya sebenarnya masih ingin bertanya. Namun, saya harus berhenti di sini.
Semoga tulisan saya ini bermanfaat dalam menyoroti karya tulis ilmiah dari
sudut pandang yang, semoga, berbeda. Bandung, 19 Maret 2003
Sekadar Catatan tentang Tulis Menulis
Oleh : Sindhunata
Oleh Penerbit Mizan, saya diminta untuk membagikan pengalaman di sekitar tulis menulis pada
rekan-rekan penulis. Seingat saya,
pengalaman menulis itu begitu luas dan panjang, banyak variasi dan
bidangnya. Karena itu, saya tidak tahu,
harus mulai darimana, atau harus mengutarakan pengalaman yang mana. Di bawah
ini saya justru ingin menyampaikan
terlebih beberapa pengalaman dan pernyataan para penulis dunia tentang
suka duka kepenulisan mereka. Pendapat
mereka ingin saya jadikan acuan bagi pengalaman saya sendiri. Semoga juga bagi
pengalaman Anda. Memang, acuan itu
sifatnya lebih reflektif, filosofis, bahkan teologis.
Kepenulisan
dan Keberadaan-Diri
Kepenulisan (Jerman: Schreiben) dan keberadaan-diri (Sein) adalah dua hal
yang tak terpisahkan. Bahkan untuk seorang penulis, kesatuan antara dua hal
itulah yang menentukan identitasnya (Undine Gruenter, lih. Die Zeit (2003)14,
hlm. 53). Dalam bidang penulisan sastra,
menulis sendiri adalah semacam rencana, dimana seorang pengarang ingin
membangun estetika hidupnya. Dengan
menulis, orang ingin menyatakan apa saja yang ia cita-citakan dan impikan dalam
hidupnya.
Kebenaran dari pernyataan ini dapat kita lihat dalam hidup para
penulis-penulis besar. Tampak, karya
tulis mereka adalah pergulatan hidup mereka sendiri. Nyaris tiada lagi perbedaan antara hidup
mereka dengan apa yang mereka tuliskan.
Mulai dari nilai, harapan, keputusasaan sampai cinta mereka. Menulis itu adalah identias bagi keberadaan
mereka, atau sebaliknya: keberadaan mereka ditentukan oleh kepenulisan mereka.
Jelas, menulis di sini lalu bukan sekadar pekerjaan sambilan, "upaya
untuk menambah dan mengejar (ngoyak) setoran", atau pencarian
keselebritasan yang dangkal. Menulis adalah
pergulatan hidup dalam intinya yang terdalam, semacam upaya untuk menemukan dan
menentukan identitas kita yang paling orisinal.
Jelas disini menulis bukan hanya pekerjaan yang menyenangkan, tapi
keperihan dan kepedihan untuk mencari diri kita yang hilang dan tenggelam dalam
pelbagai kedangkalan.
Wacana untuk menembus kegelapan
Kau yang turun dari surga
menentramkan segala sakit dan derita
siapa yang deritanya berlipatganda
akan diteduhkan berlipat ganda pula.
Ah, lelah aku sudah dengan pelbagai upaya
Apalagi artinya semua nikmat dan derita
Tentram dan lega, datanglah padaku
berisirahatlah di dadaku
(Goethe: Wanders Nachtlied).
Puisi itu adalah jeritan agar Tuhan menolong manusia, yang didera oleh
derita, dan diombang-ambingkan oleh nikmat dan derita. Ia ingin semuanya itu berhenti dan ia menjadi
tenang. Dalam keadaan demikian rasanya
kematian lebih menghiburkan daripada perjuangan.
Di manakah dia dapat menemukan ketentraman itu? Ya, dalam puisi itu sendiri. Bahan puisi yang ditulisnya adalah kententraman
itu sendiri. Dalam puisi itulah, orang
membuat suatu wacana tentang kegelapan hidup ini, dan mencoba untuk menemukan
alternatif rasional untuk memecahkannya.
Itulah kiranya yang harus kita alami ketika kita menulis. Kita didera oleh suatu persoalan, kita
menjadi lelah dan capai, kita ingin terbebas dari kelelahan dan kecapaian itu,
kita ingin menemukan kedamaian dan ketentraman.
Cara kita membebaskan diri dari persoalan, bukan dengan berpolitik, atau
berdemonstrasi, tapi dengan menulis.
Tulisan kita harus menjadi "obat", atau
"perhentian", yang dapat menyembuhkan sakit kita, mengheningkan dan
mengisitirahatkan kelelahan dan kegelisahan kita.
Tulisan yang terburu-buru dan asal-asalan kitanya tak bakal menjadi tempat
sandaran yang menentramkan. Kita puas
mungkin, tapi kepuasan itu hanya menyentuh nama
kita di luaran saja. Di dalam,
kita tetap merasa tidak puas, merasa belum menemukan jawab. Ironisnya, tulisan yang dalam justru menegur
kita, mengapa kamu hanya sedangkal itu saja.
Tulisan yang dalam makin menggelisahkan kita untuk terus mencari dan
mencari lagi. Tulisan itu mungkin
menentramkan pembaca, tapi tidak bagi kita.
Dalam arti ini menulis adalah pekerjaan yang menyakitkan seperti sebuah
pencarian diri yang tak pernah terpuaskan juga amat menyakitkan.
Nasib Tulisan di Tangan Pembaca
Tulisan itu menjadi berarti, ketika ia sudah memasyarakat. Artinya, pembacalah yang menentukan apakah
tulisan itu baik atau tidak (Martin Walser).
Ironisnya, ketika kita menulis, pembaca itu tidak terlalu kita
perhitungkan. KIta hanya berekspresi dan
berekspresi. Pembaca sendiri bisa mulai
menemukan arti dalam tulisan itu, jika ia sendiri mempunyai pengalaman, seperti
dituturkan dalam tulisan itu.
Dengan kata lain antara pembaca dan penulis harus ada sambungan pengalaman
yang sama. Dari sinilah sebuah tulisan
itu akan membentuk suatu kesadaran.
Hanya kesadaran itu tidak dapat kita rencanakan dari awal. Kesadaran itu muncul lewat pembaca dan dari
pembaca, setelah mereka membacanya. Ini
paradoks suatu penulisan: arti dari suatu tulisan itu kelihatannya lebih
merupakan produk dari pembaca daripada penulisan. Karena itu benarlah kata-kata: "Nasib
buku itu di tangan pembaca, sesuai dengan daya kemampuan dan tingkatan
mereka" (Manfred Fuhrmann).
Dilihat dari kacamata di atas, menulis itu adalah suatu petualangan. Kita boleh merasa tulisan kita baik, ternyata
tulisan itu tak berbunyi apa-apa bagi pembaca.
Dalam bahasa pemasaran buku: pasar pembaca itu sulit diterka. Melihat kenyataan itu, tak bisa kita mematok
dari awal, bahwa tulisan kita akan laku.
Kita memang harus memperhitungkan pembaca, tapi kita tidak boleh didikte
oleh pembaca. Biarlah pembaca
membacanya, sementara kita hanya menuliskannya.
Memang, jembatan antar kita dan pembaca akan terbangun, jika mempunyai
pengalaman yang diandaikan juga dialami pembaca. Maka menulis sesungguhnya bukan hanya
pekerjaan otak, tapi pekerjaan pengalaman: pengalaman mendesak kita untuk
merefleksikannya, dan kemudian menuliskannya.
Menulis Kkarena Dunia Tak Menyerupai Kita
Andaikan dunia sudah sama dengan kita atau keinginan kita, literatur itu
takkan pernah ada (Martin Walser). Tapi
dunia tak pernah sama dengan keinginan kita.
Mengapat dunia tak menyerupai kita?
Karena dari dirinya sendiri, dunia itu tak mempunyai makna. Sebagai manusia, kita tak dapat menanggung
sesuatu yang tanpa makna. Bahka
menyelidiki sesuatu yang tanpa makna pun sudah merupakan upaya untuk memberi
makna. Menulis tak lain tak bukan adalah
menanggapi dunia yang tanpa makna dan tak menyerupai kemauan kita itu menjadi
sesuatu yang menyerupai kita. Dengan
menulis kita memberi jawaban atas sesuatu yang kita anggap kurang, karena tidak
menyerupai kita.
Untuk menjalankan tugas kepenulisan itu, kita hanya punya satu alat, yakni
bahasa. Dengan bahasa, kita mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Sesuatu yang sudah kita rasa sama dan serupa
dengan keinginan kita, belum betul-betul terasa sebagai serupa, karena belum
terungkap dan diungkapkan. Baru dengan
bahasa, kita dapat membuatnya terasa, nyata dan terungkap. Kalimat, yang kita tuliskan, mengatakan pada
kita tentang sesuatu, yang tidak kita sadari, sebelum kita
mengkalimatkannya. Jadi bahasa adalah
semacam "alat produksi". Patut
diingat, kendati bahasa adalah alat kita, kita bukanlah “tuan†dari alat
tersebut. Karena itu, kita harus dengan
sabar menunggu, sampai bahasa itu menjadi peluang, yang memberi kita jalan
untuk mengerti dan membukakan banyak hal, yang sebelumnya tidak kita ketahui. Percaya pada kekuatan bahasa, kita akan diajak
untuk melihat banyak kemungkinan dalam hidup kita, untuk kita ungkapkan.
Banyak penulis lupa akan misteri dan kekuatan bahasa. Mereka lebih percaya pada pengetahuan dan
pengalamannya. Padahal semua itu tadi
masih mentah dan belum nyata, bila tidak dinyatakan dengan bahasa. Jangan mengira, menyatakan dengan bahasa itu
mudah. Sebelum menyatakan dengan bahasa,
kita harus menggulati pengetahuan kita dengan bahasa. Sering terjadi, dalam pergulatan itu kita
kalah. Kita merasa tahu dan mengerti,
merasa mengalami dan sadar, tapi semuanya itu tudak dapat kita kalimatkan,
artinya bahasa tak membantu kita untuk menyatakan semuanya itu tadi. Akhirnya, semuanya tinggal sebagai kegelapan
dan kebawahsadaran, padahal kita merasa tenang dan sadar tentangnya. Dalam hal ini bahasa adalah sarana pencerahan
bagi kegelapan kita.
Kendati tidak pernah bisa menjadi seratus persen tuan atas bahasa, bahasa
harus kita latih dan kuasai. Kalau
logika bahasa kita mampet, kalau gramatika kita kacau, kalau keindahan bahasa
tidak kita kuasai, dan perbendaharaan bahasa tidak kita punyai, dalam menulis
kita hanya akan menjumpai kekeringan belaka.
Sebaliknya, jika kita terlatih dan kaya akan bahasa, lorong-lorong
kepenulisan tiba-tiba membuka dengan sendirinya.
Menulis dan Kesepian
Berani menyendiri, berada dalam kesepian dan keterasingan adalah hal yang
harus terjadi dalam kepenulisan (Marguerite Duras). Kesepian itu bahkan harus dialami bukan hanya
secara rohani, tapi juga secara badani.
Namun kesepian ini bukan berarti isolasi. Kesepian itu lebih merupakan semacam
keberadaan diri yang sadar, yang justru terus bergulat untuk menemukan kontak
tapi juga menolak kontak.
Dalam kesepian itu orang bahkan menjadi liar. Menulis memang membuat orang menjadi
liar. Menulis membuat orang kembali
kepada kebuasan, yang ada sebelum
hidupnya. Seorang penulis tiba-tiba
mendapati dirinya liar seperti di hutan, dan selalu liar sepanjang hidupnya. Untuk menulis, orang harus menggigit bibir,
bergulat dengan keliarannya. Untuk itu
ia harus menjadi lebih kuat dari tubuhnya.
Ia juga harus lebih kuat daripada apa yang hendak ditulisnya. Kalau tidak, ia akan menyerah dan kalah. Maka menulis itu sebenarnya bukan hanya
menulis, tapi mengalahkan kelemahan dirinya, menundukkan apa yang dihadapinya. Penulis itu bagaikan binatang, yang berseru di
kala malam. Penulis itu tiba-tiba
merasakan hidup ini vulgar, dan ia tidak bisa menghaluskannya, sebelum ia ikut
dan terbenam dalam kevulgaran itu.
Jelas, orang yang tidak berani sepi, dia tak mungkin jadi penulis yang
baik. Tapi kesepian itu bukan romantisme
kesendirian. Kesepian itu adalah
suasana, yang menantang kita untuk berani bergulat dengan seluruh realitas,
yang ternyata tidak mudah kita taklukan.
Tak jarang orang menyerah dalam pergulatan itu, karena ia merasa tidak
kuat dan tidak mampu. Menulis akhirnya
adalah suatu askese, matiraga, suatu kebertapaan di tengah keramaian. Karang
Klethak, 29 Juni 2003
Mata Itu Begitu
Jernihnya
Oleh : Faidah Azuz
"Kalau aku
jadi raja, mereka tak hanya akan memperoleh pangan dan papan, tetapi juga
ajaran dari buku, karena perut yang kenyang itu tak bernilai jika pikiran
kelaparan". -The Prince and Pauper
Juli 2001, ketika saya mengunjungi stand Mizan di Pameran Buku Istora
Senayan Jakarta, saya dihadiahi beberapa sticker kecil berwarna merah dengan
tulisan seperti yang saya kutip di atas. Sticker itu saya bagikan ke beberapa
teman kerja di Makassar sebagai oleh-oleh, reaksi mereka berbeda-beda. Ada yang
langsung membacanya dan kemudian dengan antusias berkomentar tentang anak dan
buku.
Di pikiran mereka dirinya adalah raja yang berkewajiban mengenyangkan
anak-anak dengan ajaran dari buku. Tetapi ada juga yang tidak antusias, hanya
berkata pendek "iya..ya..betul juga... " lalu menghentikan
pembicaraan.
Di Pameran itu pula, saya berkenalan dengan Mas Hario yang diminta oleh
Mizan untuk mengawal stand divisi anak-anak. Mas Hario dengan cekatan dan
ekspresi penuh menjelaskan pada saya jenis bacaan dan kesesuaian tingkatan umur
anak-anak. Juga tentang tata warna dan bentuk gambar. Saya kagum bukan saja
pada keragaman bacaan anak-anak di Mizan, tetapi juga pada gaya Mas Hario
menerangkan. Belakangan saya tau bahwa Mas Hario berprofesi sebagai pendongeng,
maka tak pelak mulut saya membentuk huruf oooo yang panjang. Profesi ini belum
ada di Makassar, kota saya itu.
Tahun 2001 tepatnya tanggal 18 Nopember, Yayasan Katutui mengundang Mas
Hario ke Makassar untuk memberikan ceramah pada seminar "sayang anak lewat
cerita". Kami ingin membagi pengetahuan dengan para orang tua bahwa
kesibukan di tempat kerja tidak lantas membuat kita mereduksi waktu mendongeng
pada anak-anak. Mas Hario mengajarkan bagaimana mengolah cerita, bagaimana
menyelipkan pesan moral dalam bahasa anak-anak ketika mendongeng sebelum tidur.
Ketika Mas Hario memperagakan cara menuturkan cerita dengan mengambol
contoh kisah sahabat Nabi yang susah bersyahadat dan hendak dibakar saat
meninggal karena durhaka pada ibunya, sebagian peserta sekitar 200-an orang itu
ada yang merembeskan sapun tangan di sudut mata. Ada yang memejamkan mata, ada
yang menggit bibir kuat-kuat. Suasana menjadi hening. Duh... kami terharu dengan cara penuturan Mas
Hario.
Ini bukan kisah baru, hampir semua ibu-ibu yang hadir tau cerita
itu..tetapi cara penuturan yang optimal mampu menyentuh sudut hati peserta.
"Nah...bayangkan...jika...ibu-ibu saja sudah tersentuh hatinya, apalagi
anak-anak di rumah..pasti hati mereka yang bersih itu akan merekam pesan moral
baik-baik manakala disampaikan dengan cara yang menyentuh pula" Tutup Mas
Hario. "Ibu-ibu tidak bisa mengolah cerita dengan baik kalau tidak
memiliki sumber cerita...maka itu berarti...maaf ibu-ibu...apa boleh buat, saya
sarankan untuk rajin membaca, rajin ke toko buku memilih buku untuk
anak-anak..." begitu Mas Hario menyelesaikan sesinya. Kami menarik nafas
panjang, membenarkan!
***
Sekarang, sudah tahun 2003. Pengalaman dengan Mas Hario plus pesan dari
sticker Mizan melemparkan saya ke toko buku. Sudah dua jam saya berkeliling di
sini, mencari buku untuk kemenakan saya. Saya berkeringat di toko Gramedia
Jalan Dr. Ratulangi Makassar yang ber-AC. Bingung mencari buku yang cocok untuk
anak menjelang usia 2 tahun.
Betul-betul saya merasa tak berkutik mencari buku cerita untuk sang
kemenakan. Kebingungan ini semakin mengental ketika saya merasakan bahwa betapa
mudahnya mencari buku untuk diri sendiri, atau buku wajib untuk mahasiswa, atau
untuk perpustakaan tempat saya bekerja, atau bahkan untuk menghadiahi teman.
Kesukaan saya berinternet, berkomunikasi dengan beberapa penerbit atau penulis,
diskusi dengan pakar, atau aktifitas lain harus tersentak, betapa tidak
berdayanya ketika harus memilih buku untuk si kecil. Bingung dan penasaran semakin menjadi-jadi.
Dimana segala kemampuan---kata orang kemampuan intelektual---orang dewasa untuk
mencerna buku? Kebingungan tersebut sampai pada puncak keputusan. Pulang tanpa
membawa satu bukupun.
Tetapi rasa bingung telah berubah menjadi penasaran yang menggunung.
Besoknya saya menyediakan waktu khusus membawa sang kemenakan ke toko buku.
Saya menggiringnya ke bagian buku anak-anak. Membiarkan dia memilih, memilah,
dan membuka-buka beberapa halaman buku.
Pushhh.. betapa gampang si kecil memutuskan buku yang disukainya. Ternyata
si kecil hanya memilih satu majalah Bobo Yunior dan Buku cerita MIO-MIZAN tentang "ajakan berolah raga".
Matanya membesar dan tersenyum lucu ketika melihat ada gambar anak kecil
berjilbab. Dia memegang ujung jilbab kecilnya. Lalu dengan lidah cadelnya
mengatakan "Nuyu puna jibat," nurul juga punya jilbab, maksudnya.
Masya Allah, begitu mudah si kecil Nurul Salsabila memilih.
Bobo Yunior yang dipilihnyapun ada alasan. Si kecil menunjukkan gambar
jubah panjang Nirmala yang berwarna merah muda. Lalu berujar "ayun ade
yaya". Ternyata jubah panjang Nirmala dilihatnya sebagai bentuk kerucut
panjang mirip ayunan adiknya si Rara yang juga berwarna merah muda. Senyum saya
melebar.
Saya ingin bereksperimen, melihat reaksi si kecil terhadap buku-buku lain.
Saya memperlihatkan komik remaja. Dibukanya sebentar, lalu dikembalikan lagi.
Tidak berminat. Saya menunjukkan komik tentang sahabat Nabi terbitan
Rosda-Bandung. Si kecil langsung berteriak-teriak kegirangan, matanya berbinar
jernih, seperti menemukan sesuatu, "ini abi aut... ini abi aut... "
sambil menunjukkan gambar sorban. Mungkin teringat ketika dibacakan cerita Nabi
Daud menjelang tidurnya.
Saya kemudian menunjukkan buku yang berderet dibawah tulisan Politik. Si
kecil membukanya sebentar, membolak balik halaman tanpa curiga, kemudian
mengembalikan pada saya dan berujar dalam irama bertanya "ini ida
puna". (Ini punya Ida?). Mungkin
dipikiran sederhananya menemukan bahwa kalau buku yang banyak karakter teks
pasti milik orang dewasa seperti saya.
Masya Allah betapa sederhananya anak-anak memilah.
Sekarang, di Bulan Juni 2003, ketika semua bangsa hendak memperingati hari
anak sedunia, rasanya tidak perlu berangan-angan terlalu muluk untuk
menyelamatkan anak-anak yang berada jauh dari jangkauan kita. Di lingkungan
terkecil, di rumah, ternyata anak perlu diberdayakan. Berdaya secara intelektual,
juga kemampuan emosional, apalagi kemampuan spiritual. Meminjam istilah
sekarang, memberdayakan IQ, EQ, dan SQ.
Mungkin, jika negara ini telah mencapai tingkat kehidupan yang baik,
persoalan ekonomi bukan jadi masalah, anak bisa sekolah secara gratis yang
berarti IQ mereka bisa di perbaiki. Sekolah EQ dan SQ tidak bisa dibayar dengan
rupiah, tetapi teladan, kearifan, tebaran rasa ruhama (rasa sayang) itulah uang
sekolahnya. Untuk mengetahui apakah anak sudah terpuaskan IQ, SQ, dan SQ tidak
perlu mencari jauh-jauh, lihat saja matanya, bercermin disitu, kita segera
temukan jawabannya.
Saya kembali merenung kemudahan si kecil ketika memilih buku. Tidak semua
buku diakui sebagai miliknya. Masih mengingat buku untuk orang lain ketika
menemukan jubah Nirmala yang mirip ayunan. Agaknya kita orang dewasa perlu juga
belajar dari anak-anak terutama sifat jujur, sikap sportivitas, setia kawan,
tidak egois dan banyak lagi hal-hal natural dan normatif. Sampai disini
teringat kembali pada bukunya Kak Seto Mulyadi "anakku adalah
guruku". Saya mengangguk setuju.**
Menjadikan Teks sebagai Senjata
Oleh : Hernowo
Bahan-bahan yang saya gunakan untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada
anak-anak didik saya berasal dari apa saja yang saya baca. Saya mengajar sekali
seminggu pada hari Sabtu. Selama hampir seminggu--hampir setiap hari--saya
memilih dan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang saya baca dan dari
pelbagai ragam sumber informasi yang saya akses, seperti Internet, surat kabar,
majalah, televisi, dan lain-lain.
Saya ingin materi kebahasaan yang saya ajarkan senantiasa up to date.
Artinya, saya ingin menggunakan bahasa sebagai salah satu cara menjadikan
mereka tahu tentang apa saja yang sedang berkembang di sekitar mereka. Saya kok
merasa yakin bahwa dengan memosisikan bahasa seperti itu, akhirnya saya dapat
membuat mereka dapat merasakan manfaat belajar bahasa Indonesia.
Kadang, setelah saya selesai mengisahkan apa yang saya dapat, saya lalu
bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka dapat selama seminggu. Apakah
mereka memperoleh hal-hal baru dari apa yang mereka baca? Apakah ada sebuah
kabar atau berita yang mengesankan mereka yang mereka peroleh dari surat kabar,
misalnya? Apakah ada yang bermanfaat untuk mengembangkan diri mereka yang
berasal dari televisi, radio, ataupun Internet. Itulah, sekali lagi,
bahan-bahan yang saya gunakan untuk mengajarkan bahasa Indonesia.
Apakah dengan begitu saya lantas tidak mengikuti kurikulum pengajaran
bahasa Indonesia yang disediakan oleh pemerintah? Saya jelas masih berpedoman
dan mempelajari kurikulum itu. Namun, saya menggunakannya secara fleksibel,
tidak kaku. Misalnya, saya sadar bahwa saya harus mengajarkan bahasa Indonesia
dalam konteks dapat mencakup empat keterampilan berbahasa: berbicara, menyimak,
membaca, dan menulis. Saya, memang, senantiasa berusaha mencoba mendasarkan
proses belajar-mengajar saya untuk keperluan peningkatan empat keterampilan
berbahasa tersebut.
Benar, saya memang hanya menekankan pada salah satu aspek keterampilan
berbahasa saja, yaitu menulis. Mengapa? Hal ini ada kemungkinan, pertama,
lantaran keterbatasan saya. Saya merasa tidak layak untuk mengklaim bahwa saya
mampu mengajarkan (apalagi melatih) mereka, anak didik saya, dalam keempat
keterampilan berbahasa atau berkomunikasi tersebut. Saya lalu mengambil saja
yang merupakan salah satu aspek yang, menurut saya, memang saya kuasai.
Kedua, saya kok merasa yakin bahwa dengan mengajarkan keterampilan menulis
kepada mereka, saya sekaligus dapat menunjukkan bahwa apabila mereka mau dan
akhirnya mampu menguasai keterampilan menulis, bisa jadi ketiga aspek
keterampilan berbahasa--berbicara, menyimak, dan membaca--dapat mereka
tingkatkan juga. Ini memang masih berupa hipotesis saya. Masih perlu diuji
keandalannya. Apabila ditanyakan kepada saya apa landasannya, ya saya akan
bercerita tentang pengalaman diri saya.
Selama ini saya memang mencoba benar-benar menggunakan kegiatan menulis
untuk mengatasi permasalahan saya dalam berkomunikasi. Sebelum saya berlatih
habis-habisan menulis, saya termasuk orang yang gagap berbicara secara lisan,
apalagi kalau diminta berbicara di depan orang banyak. Saya kadang gugup dan
gembrobyos (keringat terus mengalir dari tubuh saya). Yang lebih parah adalah
saya kadang tidak dapat mengendalikan pembicaraan begitu waktu mulai bergerak.
Kadang saya terjebak untuk bicara ke mana-mana, ngalor-ngidul, tak keruan
ujung-pangkalnya. Ujung-ujungnya, saya bingung sendiri dan tak paham dengan
hal-hal yang saya bicarakan.
Nah, lewat menuangkan lebih dahulu secara tertulis apa pun yang ingin saya
omongkan, saya merasa lebih enak dan percaya diri. Saya menuangkan bukan dalam
bentuk outline atau poin per poin. Saya menuangkan secara bebas dan total dalam
bentuk esai yang kadang berlembar-lembar panjangnya. Yang penting saya sudah
mengeluarkan semua hal yang memang ingin saya omongkan atau keluarkan. Apabila
saya berhasil melakukannya, saya akan lebih mudah dan lancar dalam menyampaikan
apa yang perlu saya sampaikan.
Yang mengherankan saya, apa pun yang saya tulis kemudian melekat-kuat di
benak saya. Saya seperti diberi kekuatan untuk dapat mengendalikan omongan
saya. Saya merasa, menulis dapat membantu saya untuk menyaring dan menguasai
materi yang ingin saya omongkan. Dan kalau sudah begini menulis saya rasakan
dapat mempiawaikan cara berkomunikasi lisan saya. Saya lalu dapat berbicara
secara benar, tertata, dan fokus. Sekali lagi, kemampuan menulis dapat
digunakan seseorang untuk memperbaiki komunikasi lisannya.
Menulis juga dapat "memaksa" saya untuk mau membaca atau mencari
tambahan informasi. Lantas, setelah itu, apa saja yang saya baca dapat saya
manfaatkan untuk mengembangkan diri saya apabila saya dapat menyerap
"gizi" yang saya baca. Caranya? Ya dengan "mengikat" atau
menuliskan hal-hal menarik dan mengesankan saya yang saya peroleh dari kegiatan
membaca. Ada kemungkinan, tanpa didampingi kegiatan mencatat, proses pembacaan
saya tidak begitu efektif. Informasi yang saya serap hanya menumpuk di kepala
saya dan hilang satu per satu akibat tindihan informasi baru.
Nah, terakhir, untuk dapat mencatat secara baik, saya harus mendengarkan
dengan baik pula apa saja yang saya baca. Kadang tuntutan untuk dapat
menuliskan sesuatu secara bernas dan tuntas juga "memaksa" saya untuk
menyimak dengan penuh perhatian terhadap sumber informasi yang saya serap.
Apabila saya menyerap informasi dari sebuah buku, maka saya harus
"mendengarkan secara aktif" (active listening) setiap gagasan yang
ingin disampaikan oleh seorang pengarang.
Hanya dengan menyimak secara penuh perhatianlah seseorang itu dapat
"membaca" apa saja yang ingin diserapnya. Juga apabila kita ingin
dapat menampung segala curahan hati (curhat) seseorang, kita perlu benar-benar
merekam seluruh gerak-gerik fisik, kata-kata yang keluar, dan juga emosi yang
bergejolak yang disampaikan oleh seseorang tersebut. Active listening tak
mungkin terbentuk apabila tidak disertai kesungguhan membaca, merekam (bisa
dengan mencatat), dan memberikan respons secara lisan (berkomunikasi secara
empatik).
**
Demikianlah, kurang lebih, materi yang saya berikan kepada seorang
mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Bahasa dan Sastra saat
mewawancarai saya pada Jumat, 13 Juni 2003. Sang mahasiswi itu tertarik untuk
mengetahui cara saya mengajarkan bahasa Indonesia di sebuah SMU. Dia ingin tahu
metode yang saya gunakan dalam mengajar dan bagaimana saya menyusun kurikulum
serta apa yang ingin saya raih. Yang menarik--di antara beberapa pertanyaan
yang dilontarkan kepada saya--dia juga bertanya soal sebab-sebab pengajaran
bahasa Indonesia yang--dirasakannya dan juga saya rasakan--kadang membosankan.
Kenapa ya?
Apakah pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah memang terasa
membosankan? Saya kira bagi yang menyenangi mata pelajaran bahasa Indonesia,
tentulah mata pelajaran itu menyenangkan. Bagi yang tak menyenangi mata
pelajaran tersebut--apalagi bagi yang memiliki minat tinggi dalam mempelajari
mata pelajaran lain selain bahasa Indonesia--tentulah, bisa jadi, kelas yang
mengajarkan materi pelajaran bahasa Indonesia akan terasa membosankan.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya membuat kegiatan belajar-mengajar
bahasa Indonesia menjadi tidak membosankan? Atau, apakah membosankan dan tidak
membosankan dalam kaitan pembelajaran bahasa Indonesia ini harus didudukkan
lebih dahulu ketimbang memasalahkan dan kemudian mencari solusinya? Apakah
pelajaran bahasa Indonesia di sekolah selama ini memang membosankan? Saya tidak
tahu. Saya hanya menunjukkan kepada mahasiswi yang mewawancarai saya tentang
pengalaman saya mengajarkan bahasa Indonesia selama hampir lima tahun di SMU.
Saya tunjukkan kepadanya--termasuk saya bertanya juga kepada mahasiswi
tersebut--bahwa apabila seseorang ingin melanjutkan studinya ke perguruan
tinggi, tentulah salah satu (atau mungkin lebih) dari empat cara berbahasa
(yang telah disebutkan sebelum ini) sangat penting untuk dikuasai. Misalnya
kemampuan menulis. Kemampuan menulis, setidaknya, perlu dikuasai oleh seseorang
yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Apakah ada yang tidak
setuju berkaitan dengan hal ini? Mungkin ada ya yang tidak setuju.
Lalu, saya dan mahasiswi itu terlibat diskusi tentang dunia
tulis-menulis--di antaranya adalah bagaimana cara memotivasi seseorang untuk
mau membiasakan diri menulis. Terutama, setelah mahsiswi itu tahu bahwa saya
hanya mengajarkan bidang keterampilan menulis di SMU tempat saya mengajarkan
bahasa Indonesia. Mengapa hanya menulis, kan belajar bahasa itu tidak hanya
berkaitan dengan menulis? Kan masih ada keterampilan lain berbahasa yang perlu
dipelajari? Saya kemudian menjelaskan kepadanya sebagaimana tulisan yang saya
ciptakan di awal tulisan ini.
Apabila kegiatan belajar-mengajar bahasa Indonesia di sekolah kita anggap,
memang, cenderung membosankan (tidak merangsang anak didik untuk menguasai
keterampilan berbahasa), lantas apa yang dapat kita lakukan untuk mengubah
keadaan yang, mungkin, membosankan itu?
**
Saya katakan kepada mahasiswi yang mewawancarai saya bahwa tujuan saya
mengajarkan bahasa Indonesia adalah untuk memperkaya pemikiran anak didik saya.
Saya senantiasa mengawali pengajaran saya dengan menceritakan apa saja yang
saya dapat berkaitan dengan teks. Kadang saya membawa buku dan menunjukkan
manfaat yang saya serap dari teks yang saya baca. Kadang saya membuat
transparansi yang bahannya saya peroleh dari Internet, surat kabar, atau media
lain.
Saya merasa tidaklah mungkin pembelajaran di kelas yang hanya memakan waktu
efektif selama satu setengah jam dapat digunakan untuk menyampaikan seluruh
materi pelajaran yang ingin diajarkan. Saya kadang menyiasatinya dengan
memberikan gambaran besar dan apa manfaat mata pelajaran yang ingin dipelajari
mereka saat itu. Saya juga berusaha untuk merangsang mereka agar tidak hanya
berhenti belajar di kelas. Saya mendorong mereka untuk belajar di dunia yang
lebih luas.
Saya ingin anak didik saya belajar bahasa Indonesia sesuai dengan
perkembangan yang terjadi di luar. Saya, terutama, ingin menunjukkan kepada
mereka bahwa teks dapat dijadikan "senjata" untuk, salah satunya,
memperkaya pikiran mereka. Apabila pikiran mereka dapat diperkaya dengan
teks-teks yang membuat cakrawala mereka semakin lebar, tentulah mereka akan
dapat merangsang diri mereka sendiri untuk terus mencari pengetahuan yang
bermanfaat, salah satunya, lewat teks, dengan, misalnya menyelenggarakan
kegiatan membaca buku, berselancar di Internet, atau berdiskusi.
Saya juga katakan kepada mahasiswi itu bahwa saya tidak hanya memberikan
pengetahuan kepada mereka berkaitan dengan bahasa Indonesia. Saya kadang
mengajak mereka untuk menggunakan bahasa untuk memecahkan problem-problem
mereka. Saya ingin mereka berlatih menggunakan bahasa Indonesia demi keuntungan
diri mereka. Saya, misalnya, memberikan tugas kepada mereka untuk membuat surat
lamaran kerja. Saya kadang meminta mereka untuk menulis surat kepada orangtua
atau sahabat mereka. Saya juga meminta mereka untuk mengekspresikan diri mereka
secara tertulis dan bebas.
Saya menganjurkan mereka untuk menyediakan buku harian. Saya katakan kepada
mereka bahwa buku harian dapat membuat mereka hidup dalam dunia yang ingin mereka
ciptakan sendiri. "Menuliskan rasa marah, harapan, ketakutan, kecemburuan
bisa mencegah Anda dari menguburkan emosi Anda dalam-dalam, yang menyebabkan
emosi itu sulit diraih kembali. Penggunaan huruf besar, tanda seru, atau kata
sifat saat menulis buku harian merupakan cara Anda berteriak tanpa harus
membangunkan tetangga," tulis Laurel Schmidt.
Tugas-tugas yang saya berikan saya pola sedemikian rupa sehingga tugas itu
betul-betul berkaitan dengan diri mereka dan mereka, nantinya, dapat merasakan
manfaatnya. Saya ingin tugas-tugas bahasa Indonesia yang saya berikan kepada
mereka dapat membuat diri mereka menguasai keterampilan berbahasa--setidaknya
keterampilan menulis--secara benar-benar mengasyikkan mereka. Bagaimana membuat
anak didik saya menyenangi sebuah tugas? Bukankah tugas-tugas mereka di sekolah
sudah terlalu banyak untuk dikerjakan di rumah?
Saya senantiasa memberikan tugas dengan lebih dahulu membebaskan diri
mereka. Misalnya, saya meminta mereka untuk mengirimkan tugas mereka dalam
bentuk e-mail. Di samping mudah, cepat, dan murah meriah, e-mail dapat
membebaskan mereka lantaran sifatnya yang sangat personal. Saya juga meminta
mereka untuk mencatat perkembangan diri mereka lewat buku harian. Merujuk ke
kata-kata Schmidt, saya kira buku harian juga dapat membebaskan diri mereka.
Kadang cara saya mencek apakah mereka menulis atau tidak di buku harian mereka
adalah saat mereka menjalani ulangan-ulangan harian yang kadang saya lalukan
secara mendadak tetapi membuat mereka tidak merasa tertekan.
Nah, salah satu kegiatan menyenangkan yang terakhir saya berikan kepada
mereka adalah tugas memilih lagu yang mereka sukai. Saya meminta mereka memilih
satu lagu yang benar-benar bermakna bagi mereka. Saya meminta mereka--selain
mendengarkan dengan saksama dan menikmati iramanya--agar menuliskan lirik dan
kemudian mengapresiasi sesuai apa yang mereka pahami.
Tentu, untuk membuat mereka lebih senang, saya senantiasa memberikan hadiah
berupa buku-buku yang cocok dengan karakter mereka, terutama bagi yang berprestasi.
Reward semacam ini, saya kira akan membuat harga diri dan kepercayaan diri
mereka membubung tinggi. Insya Allah.[]
Buku 'Curhat' Hillary Clinton
Oleh : Rostita
Semua orang bisa menulis. Menulis tema apa saja---termasuk curhat---dan itu
dilakukan mantan first lady Amerika Serikat, Hillary Clinton. Tgl. 2 Juni 2003,
buku tulisan senator New York itu diluncurkan. Judulnya Living History, berisi
pengalamannya sebagai ibu negara selama 8 tahun di Gedung Putih mendampingi
suaminya Bill Clinton yang menjabat presiden Amerika Serikat selama dua
periode. Tapi yang jadi topik utama buku terbitan Simon&Schuster itu adalah
'curhat' Hillary Clinton seputar affair suaminya dengan Monica Lewinski.
"Sesak rasanya dada ini. Saya menangis dan saya membentak Bill. "Apa
sih maksudnya? Ngomong apa kamu? Kenapa kamu begitu?' Saya sangat kesal. Bill
berdiri di depan saya, sambil terus berkata, "Maafkan saya ya. Maafkan
saya. Saya hanya ingin melindungimu dan Chelsea.'"
Perempuan lain mungkin enggan menuliskan hal yang paling rahasia seperti
itu. Tapi Hillary memilih menuliskannya.
Hillary bukan hanya ingin memaparkan fakta, dan rasanya, ia juga tidak
mencari sensasi, karena sebagai senator, ibu satu anak itu sanggup menyedot
kucuran dana sampai 3 juta dollar AS untuk Partai Demokrat yang
diwakilinya.
Entahlah mengapa Hillary menuliskan pengalaman pahitnya. Tapi, Profesor di
Fakultas Kedokteran Harvard, Alice Domar (penulis buku Self-nurture: Learning
to Care for Yourself as Effectively as You Care for Everyone Else, (Wanita
Belajarlah Mencintai Dirimu: Menyayangi dan Memerhatikan Keluarga Tanpa
Mengabaikan Sendiri, Qanita, 2002), mengatakan "menuliskan segala sesuatu
dapat mengatasi kenangan dan perasaan pahit, sehingga seseorang meneruskan
kembali hidup dengan penuh percaya diri.
Entahlah, apakah Hillary ingin berbagi. Tapi, ada satu kutipan menarik dari
The Associated Press yang mempublikasikan Living History.
"Menurut Hillary, pencalonan dirinya untuk duduk di kursi senat
mewakili New York menjadi jembatan penyembuh hubungannya dengan Bill Clinton.
'Bill dan saya jadi lebih banyak berdiskusi tentang kursi senat, dan kami tidak
menggugat masa depan hubungan kami. Lama-lama kami jadi lebih santai.'"
Ini mengingatkan saya akan sebuah pendapat yang mengatakan, jika kita sedang
menghadapi satu masalah, alihkan konsentrasi ke hal lain, maka masalah itu akan
terasa lebih ringan.
Hillary hanya menulis. Menulis saja. Menulis isi hatinya, perasaannya,
pemikirannya, pengalamannya dan lain-lain. Dan kita---pembacanya (mungkin kita
akan membaca bukunya karena menurut www.yahoo.com, hak terbitnya sudah dijual
kepada 16 negara, mungkin, termasuk Indonesia)---menemukan banyak hal dari
tulisannya. Dari publikasi The Associated Press saja, setidaknya ada dua hal,
menulis untuk menyembuhkan hati, dan menulis untuk berbagi, memotivasi. Tapi,
yang sangat jelas, buku Hillary Clinton ini juga membuktikan hasil riset
James W. Pennebaker (penulis
"Ketika Diam Bukan Emas", Kaifa 2002) bahwa mencurahkan isi hati
(self-disclosure) dapat berpengaruh positif bagi perasaan, pikiran, dan
kesehatan tubuh---yang caranya sangat mudah dilakukan: membuka-diri
kepada orang yang dipercaya, atau yang lebih baik lagi: menuliskan
semuanya secara bebas di catatan pribadi.
Ngomong-ngomong, Simon&Schuster sangat yakin, Living History setebal
562 halaman bakal laris. Edisi
pertamanya yang dicetak 1 juta eksemplar memang laris di pasaran. Hillary
Clinton sendiri dibayar 2,85 juta dollar AS. **
Wow, Aku Bisa Menulis!"
Oleh : Hernowo
Suatu ketika, setelah mencetak prestasi besar dalam sejarah kehidupannya
sebagai atlet bola basket, Michael Jordan ditanya oleh seorang wartawan
televisi terkenal. "Apa yang membuat Anda mampu melesakkan bola hingga
mendekati angka 50 poin?" Jordan menjawab sembari mata-tajamnya menatap
mata sang wartawan, "Keinginan. Saya memang mempunyai keinginan untuk
mencetak angka yang banyak dalam setiap pertandingan."
Keinginan? Sekali lagi, apakah hanya keinginan yang mampu memotivasi Jordan
untuk berprestasi dalam setiap pertandingan bola basketnya? Mari, pertanyaan
ini tidak usah kita jawab lebih dahulu. Saya akan mengajak Anda untuk berpindah
dari Jordan ke Covey. Dalam buku berpengaruhnya, The 7 Habits, Stephen R. Covey
bercerita. Covey bercerita tentang apa sih yang dimaksudkan dengan
"habit" atau kebiasaan itu. Katanya, kebiasaan merupakan titik
pertemuan antara pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan keinginan
(desire).
Lalu di dalam bukunya itu, Covey membuat gambar untuk lebih menjelaskan apa
yang dimaksud dengan titik pertemuan. Gambar itu terdiri atas tiga lingkaran,
yang di dalam setiap lingkaran tertulis kata pengetahuan, keterampilan, dan
keinginan. Ketiga lingkaran itu lalu dipertemukan dan di tengah-tengah
pertemuan ketiga lingkaran itu diberi arsir (raster) dan terciptalah apa yang
didefinisikan dengan kebiasaan. Apa sebenarnya yang diinginkan Covey dengan
menciptakan ketiga hal itu?
"Pengetahuan adalah paradigma teoretis, 'apa yang harus dilakukan' dan
'mengapa', "tulis Covey. "Keterampilan adalah 'bagaimana melakukannya'.
Dan keinginan adalah motivasi, 'keinginan untuk melakukan'. Agar sesuatu bisa
menjadi kebiasaan dalam hidup kita, kita harus mempunyai ketiga komponen
tersebut." Mari, kita berhenti sejkenak di sini dan merenungkan secara
intens apa yang kita peroleh dari semua ini? Dari ucapan Jordan sekaligus
kata-kata Covey?
Michael Jordan, salah satu atlet terbaik yang pernah dilahirkan oleh NBA,
adalah olahragawan bola basket yang dikenal memiliki keterampilan sangat tinggi
dalam bermain basket. Bahkan Jordan sempat disemati oleh sebuah istilah yang,
bisa jadi, hanya dimiliki oleh pesawat terbang: Air Jordan! Dan dalam sebuah
film, Space Jam, Jordan sempat dilukiskan sebagai pebasket yang tidak punya
lawan-tanding di bumi ini sehingga harus dicarikan lawan-tanding dari planet
lain.
Saya kira pengetahuan Jordan tentang olahraga basket juga tak kalah hebat
dari keterampilannya memainkan bola basket itu sendiri. Bahkan, sebuah buku
yang ditulis oleh seorang penceramah motivasi dan inspirasi terkemuka di Amerika,
Pat Williams--How To Be Like Michael Jordan (Kaifa, 2002)--menunjukkan bahwa
pengetahuan kebolabasketan Jordan telah membuatnya menciptakan aturan-aturan
kehidupan yang membuat dirinya meraih prestasi tinggi baik di lapangan basket
maupun di kehidupan yang lebih luas. Jordan adalah teladan kedisiplinan, tak
kenal menyerah, dan pekerja keras dalam meraih sebuah hasil.
Bagaimana dengan keinginan (desire) Jordan dalam meraih prestasi tinggi
ketika bermain bola basket? Inilah, menurut saya, salah satu aspek penting yang
dimiliki Jordan. Jarang ada seorang atlet berprestasi atau tokoh-tokoh hebat
yang mengeluarkan pernyataan seperti Jordan. Sebagaimana saya tulis di awal
bahwa yang mendorongnya meraih prestasi tinggi adalah keinginan. Bisa jadi,
Jordan punya pengetahuan dan keterampilan tinggi dalam bermain bola basket.
Namun, apa jadinya apabila Jordan tak punya keinginan untuk meraih prestasi
tinggi?
Tentu saja, ada kemungkinan, Jordan tak bisa seperti Jordan saat ini
apabila tidak memiliki keinginan. Keinginan--meskipun sulit diprediksi
bagaimana kita dapat merasakan memilikinya dan caranya supaya kita punya
keinginan--merupakan unsur pembeda yang sangat penting antara apakah orang
"hebat" yang satu dan orang hebat yang lain dapat meraih sukses.
Meskipun ada dua orang yang sama hebatnya berkaitan dengan pengetahuan dan
keterampilan yang dimiliki, kedua orang ini secara sangat jelas dapat memiliki
nasib berbeda apabila diukur dari sisi keinginan.
Lalu apa kaitan keinginan dengan kegiatan menulis?
Pembaca yang budiman, pada akhir Mei 2003 lalu, saya, selaku koordinator
Mizan Writing Society (Masyarakat tulis Mizan [MTM]), mencoba melakukan aksi di
Pesta Buku Jakarta. Aksi yang saya lakukan adalah membuka Klinik Baca-Tulis.
Sifat aksi ini dapat dikatakan sebagai semacam "pelayanan" kepada
masyarakat. Bisa jadi, klinik itu juga merupakan peniruan persis dari aksi
Posyandu atau Poliklinik yang menggarap kesehatan masyarakat.
Benar bahwa Klinik Baca-Tulis yang diselenggarakan oleh MTM--bekerja sama
dengan Penerbit Mizan di Pesta Buku Jakarta--tersebut memang mencontoh
praktik-praktik poliklinik atau posyandu yang telah tersebar luas di tengah
masyarakat. Klinik yang didirikan MTM dimaksudkan untuk membantu masyarakat
luas dalam memecahkan problem-problem membaca dan menulis yang, mungkin,
melilit mereka.
Memang, saya sebagai "dokter" di klinik tersebut tidak
sebagaimana dokter beneran yang memberikan obat. Saya hanya mengajak para
pengunjung yang datang ke klinik saya untuk mengobrol--tepatnya, membagikan
pengalaman membaca dan menulis. Pada saat menyusun skenario bagaimana nantinya
klinik ini berjalan, saya mengusulkan agar setiap pengunjung dapat menuliskan
lebih dahulu apa saja yang mau diobrolkan. Saya beranggapan bahwa dengan
menuliskan lebih dahulu apa yang mau diobrolkan tentulah akan memudahkan saya,
terutama, untuk mempersiapkan obrolan-bandingan.
Juga, saya menganggap bahwa apabila seseorang dapat menuangkan secara
tertulis persoalan yang menggayuti benak dan hatinya--terutama berkaitan dengan
kegiatan membaca dan menulis--maka orang yang menuliskan persoalannya tersebut
akan lebih mudah mengomunikasikan dan menikmati perbincangan yang terjadi. Saya
juga merancang agar mekanisme klinik berjalan secara sangat personal. Artinya
saya, sebagai "dokter", memang melakukan obrolan secara "face to
face" dan pribadi.
Dengan mengobrol secara pribadi, biasanya orang lebih dapat terbuka dan
total dalam mengeluarkan persoalannya. Apalagi persoalan yang ingin diungkapkan
ini sebenarnya persoalan yang biasa dan, bisa jadi, melanda semua orang namun
sangat urgen. Dan, meniru terapi berbicara dan menulis yang dilakukan oleh
psikolog James W. Pennebaker, saya juga ingin menjadikan keterbukaan atau
kesediaan mengalirkan secara bebas apa yang dipikirkan seseorang itu dapat membantunya
dalam mengatasi tekanan.
Namun, apa yang terjadi dengan klinik perdana yang saya rintis ini?
Skenario itu ternyata berantakan. Tiba-tiba saja ada banyak sekali orang yang
datang dan mengerubung saya. Saya kemudian dibanjiri oleh banyak sekali pertanyaan
yang bermacam-macam. Ada pertanyaan yang bisa saya tangkap secara jelas, dan
juga, kadang, ada yang tidak dapat saya cerna. Akhirnya, saya pun harus
melayani para pengunjung secara massal. Dan pengunjung tak berhenti bertanya.
Saya pun harus terus berbicara, berbicara, dan berbicara.
**
Salah satu hal yang saya catat dan menarik untuk saya bagikan kepada para
pembaca adalah antusiasme pengunjung. Rata-rata para pengunjung klinik saya itu
memiliki "keinginan-kuat" untuk dapat membaca buku secara baik,
rutin, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Selain itu, mereka juga ingin dapat
menuliskan seluruh pengalaman menariknya sehingga dapat dibagikan dan kemudian
dibaca oleh orang lain. Saya kira--mengikuti Jordan dan juga teori Covey
tentang kebiasaan--apa yang saya jumpai itu merupakan fenomena menarik. Saya
katakan menarik lantaran sudah kerap terdengar di lingkungan kita bahwa budaya
membaca--apalagi budaya menulis--masyarakat Indonesia itu rendah.
Meskipun data yang saya kumpulkan tidak sahih atau kurang memenuhi syarat
untuk dijadikan referensi, namun saya merasakan sendiri betapa antusiasmenya
para pengunjung yang datang ke klinik saya. Saya kemudian menebak-nebak sendiri
kenapa mereka mengikuti klinik saya secara antusias. Atau, dalam bahasa lain,
saya kok sangat yakin bahwa para pengunjung klinik saya itu sudah menyimpan
"keinginan" yang sangat besar untuk dapat membaca dan menulis buku.
Hanya kapan "keinginan" itu dapat diledakkan oleh mereka, mereka
tidaklah mengetahuinya.
Ada dua hal yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, kalau itu
benar--yaitu, dugaan saya bahwa mereka memang punya "keinginan"--maka
saya kira apa yang disimpan oleh para pengunjung klinik saya itu dapat mengubah
keadaan mereka. Sebab, mengikuti Jordan, keinginan mampu memotivasi seseorang
untuk meraih sebuah prestasi. Dan apabila saja keinginan membaca dan menulis
buku secara baik yang dimiliki para pengunjung klinik saya itu benar-benar
mendorong mereka untuk melakukan kebiasaan membaca dan menulis secara sedikit
demi sedikit, setiap hari, tentulah mereka akan menguasai keterampilan dan
memiliki pengetahuan membaca dan menulis.
Kedua, kalau itu salah--yaitu mereka sebenarnya memang tidak punya
keinginan sebelumnya--maka dengan merangsang mereka dalam bentuk pembukaan
klinik sebagaimana yang saya rancang itu, sebenarnya tak sedikit orang yang
kemudian berhasil memunculkan keinginan untuk bisa memiliki pengetahuan dan
menguasai keterampilan membaca dan menulis. Saya percaya bahwa keinginan dapat
diciptakan. Apabila seseorang berhasil merumuskan manfaat tentang apa saja yang
ingin dilakukannya, tentulah orang itu dapat memunculkan keinginannya secara
hebat.
Terlepas dari semua apa yang saya uraikan, Klinik Baca-Tulis milik MTM ini
nantinya memang ingin, pertama-tama, menampung keluhan dan semacamnya berkaitan
dengan buku, membaca, dan menulis. Kami menyadari betapa tidak mudahnya
seseorang yang ingin bertanya soal buku yang baik dan menarik, dan juga soal
kegiatan membaca dan menulis yang menyenangkan, menemukan orang yang tepat untuk
melayani keinginan bertanya itu. Nah, Klinik Baca-Tulis MTM didirikan untuk
membuka peluang kepada masyarakat yang ingin mengalirkan keluhan atau apa pun
yang, mungkin, telah disimpannya lama sekali. Klinik Baca-Tulis akan bersedia
berubah wujud menjadi "keranjang sampah" atau wadah apa pun yang
bermanfaat bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kemampaun membaca dan
menulisnya.
Kedua, Klinik Baca-Tulis ingin membuat dan melontarkan isu ke tengah
masyarakat tentang pentingnya membaca dan menulis buku. Sudah disadari sejak
lama bahwa membaca dan menulis buku merupakan salah satu kegiatan yang dapat
membawa sekelompok masyarakat membangun peradaban yang tinggi. Sayangnya, di
Indonesia, kesadaran itu memang ada, hanya praktik atau aksi dalam
menerjemahkan kesadaran tersebut dalam program-program yang nyata belumlah
banyak. Beberapa komunitas yang peduli buku memang sudah mulai bermunculan.
Namun, dukungan dari pelbagai pihak yang ingin diraih oleh komunitas-komunitas
itu masih belum kelihatan secara sangat nyata. Dengan menciptakan isu, kami
berharap dukungan perlahan-lahan bisa mulai mengkristal.
Ketiga, Klinik Baca-Tulis MTM melakukan pendekatan dalam memecahkan problem
membaca dan menulis dengan cara yang diharapkan berbeda. Atau, kalau toh tidak
bisa berbeda secara signifikan dengan pendekatan yang selama ini ada, maka
diharapkan klinik ini dapat ikut memperkaya bagaimana merangsang tumbuhnya
potensi membaca dan menulis di tengah masyarakat luas. Klinik ini mencoba
memangkas kendala-kendala yang mengerangkeng seseorang untuk memunculkan
potensi membaca dan menulis. Pendekatan yang digunakan dapat disebut sebagai
"pendekatan unleashing" yang membuat seseorang secara sangat bebas
memunculkan apa yang dipendamnya sekian lama.
Lewat pendekatan-pendekatan yang berbeda itulah diharapkan, suatu saat
kelak, tentulah dengan usaha yang cukup dan kepemilikan "keinginan yang
sangat kuat", setiap orang dapat berteriak sangat keras dan merasa dirinya
menemukan sesuatu--"Wow, aku ternyata bisa menulis!"[]
Menulis Untuk Mentransformasi Diri
Oleh : Hernowo
Pada 12, 17, dan 20 April, Mas Hernowo berkeliling menjajakan (buku)
"Pizza"-nya. Pada 12 dan 20 April dalam acara "Book
Signing" di Toko Buku Gramedia Matraman, Jakarta, dan Gramedia, Jalan
Sudirman, Jogja. Pada 17 April dalam acara bedah buku "Pizza" di IAIN
Sunan Gunung Djati, Bandung. Dalam ketiga acara tersebut, Mas Hernowo
menyiapkan sebuah tulisan yang tersaji berikut ini. Selamat menikmati.
Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza merupakan contoh konkret bagaimana saya
menerapkan teori "mengikat makna". Saya "mengikat"
(mencatat) apa saja yang berkesan dan menarik bagi diri saya lewat tulisan.
Saya "mengikat" apa pun yang masuk ke dalam diri saya dan yang
berasal dari mana pun.
Ada kalanya makna itu tak langsung muncul pada saat saya mencatat apa saja
yang ingin saya catat. Kadang makna itu baru muncul setelah waktu berjalan
beberapa saat. Atau, kadang makna itu tiba-tiba muncul setelah saya
mengaitkannya dengan sesuatu, setelah saya berproses, mengalir biasa seperti
orang lain mengalir. Yang pasti, makna itu muncul secara sangat kuat, setelah
saya menuliskan sesuatu.
Oh ya, pada saat awal saya mencatat, media yang saya gunakan kadang tidak
berbentuk kertas. Ponsel atau layar komputer juga sangat kerap saya gunakan.
Nah, apa-apa yang saya "ikat" itulah yang ingin saya sebut sebagai
catatan harian saya sebagaimana saya mengklaim buku Andaikan adalah
wujud-konkret catatan harian saya.
Untuk apa saya menulis buku? Dalam sanubari saya terdalam, sudah lama
sekali tersimpan sebuah obsesi. Saya ingin menunjukkan manfaat praktis dan
manfaat sangat luar biasa dari aktivitas membaca dan menulis. Bahkan kalau
seseorang dapat memadukan dua aktivitas tersebut secara rutin dan konsisten,
misalnya setiap hari, saya berani memberikan garansi bahwa orang tersebut akan
memperoleh "kekayaan" yang tiada tara pada suatu saat kelak.
Obsesi saya ini sebenarnya begitu jelas terlihat di buku Andaikan dan belum
begitu jelas terlihat di buku Mengikat Makna, meskipun di MM soal obsesi saya
ini sudah saya singgung selintasan. Nah, kini, saya sudah merasakannya. Dan apa
yang sudah saya lakukan dan rasakan bisa juga dialami oleh siapa saja. Ya,
siapa saja, saya tegaskan.
Catatlah apa saja yang memang menurut Anda layak dicatat. Kumpulkan catatan
Anda itu secara teratur. Biarkan catatan itu tumbuh dan mengikuti mengalirnya
waktu. Kalau perlu, sekali-sekali, rawatlah. Sayangilah. Beri pupuklah. Dan,
ingat, seperti tetanaman atau hewan, kadang catatan itu ada yang mati dan ada
juga yang "bersinar" sangat menyilaukan.
Saya mengaitkan seluruh materi yang ada di buku Andaikan dengan "word
smart". Memang, saya terpengaruh oleh pandangan Howard Gardner dan pemikir
seperti Buzan, Pennebaker, Krashen, Armstrong, dan yang lain soal
kecerdasan-berbahasa ini. Saya kemudian merumuskan sendiri apa sih guna bahasa?
Kenapa kita harus mempelajari bahasa?
Kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia di sebuah SMU. Saya lalu
merumuskan bagi saya sendiri sebuah tujuan baru mengapa saya mengajar bahasa
Indonesia dan apa selayaknya yang perlu kita pelajari berkaitan dengan bahasa.
Ketemulah rumusan berikut bahwa bahasa itu dapat digunakan sebagai salah satu
senjata untuk memecahkan masalah-masalah kita. Misalnya untuk merencanakan masa
depan atau untuk merumuskan siapa diri kita.
Konsep "word smart" itu kemudian saya kembangkan sebagaimana yang
tampak pada bagan AMBaK Melejitkan "Word Smart" di buku Andaikan.
Bagan itu tak ada di konsep pemikiran Gardner, Buzan ataupun yang lain. Ada
kemungkinan apa yang dibayangkan oleh para penemu konsep "kecerdasan"
itu seperti apa yang saya gambarkan. Namun, saya kira, pikiran saya dan pikiran
mereka tidak persis sama. Kan saya punya karakter sendiri. Saya hidup dengan
nasi dan kangkung, sementara Gardner dan Buzan tidak sebagaimana saya hidup.
Sungguh setelah dapat melahirkan buku kedua, saya ingin menegaskan di sini
bahwa membaca dan menulis buku bagi saya itu "meringankan" sekaligus
menyenangkan. Mengapa begitu? Pertama, ini lantaran dua macam kegiatan itu
dapat saya lakukan secara mencicil. Kedua, membaca dan menulis itu sangat
membantu saya dalam mengenali diri saya. Ketiga, bukan hanya menulis (ini
konsep Pennebaker) ternyata membaca juga menyembuhkan. Saya merasakan semua
ini.
Dan, tentu saja, ternyata apa yang saya tulis ini cukup memberikan imbalan
yang lain, yaitu dapat "menghidupi" saya. Atau kalau saya boleh
meminjam kata-kata Kiyosaki, dalam menjalankan aktivitas membaca dan menulis,
saya tidak lantas mampu membuat buku demi uang. Saya membuat buku lantaran saya
ingin agar "uang" bekerja untuk saya. Saya kira sungguh menyenangkan
ya menjadi orang yang biasa lalu bisa "bermakna" bagi orang lain?
Benar, melakukan hal-hal biasa yang akhirnya bisa menjelma menjadi hal-hal
yang luar biasa, eh, "berharga", sangat mempengaruhi saya belakangan
ini. Ada kemungkinan saya mengetahui hal ini sudah cukup lama saat saya membaca
buku Don Gabor, Big Things Happen. Itu terjadi pada tahun 1999 ketika saya
ingin memberikan pengantar untuk buku yang diproses oleh rekan-rekan saya di
Mizan berkaitan dengan "gaya selingkung" Penerbit Mizan.
Gabor mengilhami saya dengan kata-kata saktinya. Dia menulis, "Kalau
saja Anda rajin melakukan hal-hal kecil dengan benar, (insya Allah) pada suatu
ketika nanti Anda akan dapat menciptakan hal-hal besar." Saya kok waktu
itu, dalam hati, meyakini soal ini. Lalu ya mengalirlah saya dengan membaca apa
saja dan menulis apa saja.
Saya mengerjakan buku ini hampir mencakup seluruh aspeknya. Saya bisa
melakukan itu karena saya bekerja pada penerbit yang menerbitkan buku saya.
Saya mengerjakan hampir apa saja, dari mulai yang kecil-kecil hingga yang
besar-besar. Saya menganggap buku saya adalah apa yang merupakan bagian dari
darah dan daging saya. Ya seperti anak-anak sayalah. Ini lantaran saya memang
terlibat sekali dalam melahirkan gagasan-gagasan saya hingga menjadi bentuk
yang terstruktur dan dapat dibukukan.
Saya harus merawatnya (lihat tulisan asli saya di buku Andaikan, halaman
116, yang merupakan catatan harian saya yang usianya sudah 15 tahun kalau
diukur pada tahun sekarang). Saya harus menyimpan dan menyusuinya hingga
catatan-catatan saya itu tumbuh sehat, cerdas, dan bergizi.
Kini saya punya banyak sahabat, baik sahabat lewat SMS atau Internet
ataupun surat tercetak. Ya, tak sedikit orang yang merasa terinspirasi oleh
buku saya. Alhamdulillah. Saya jadi bersemangat sekali untuk membantu siapa
saja agar bangkit dan mampu "menyulap" hal-hal biasa yang ada di
dalam dirinya menjadi hal-hal berharga---paling tidak untuk diri
sendirinya---lewat menulis.
Untuk mengakhiri catatan saya ini, izinkan saya mengutip pendapat Fatima
Mernissi tentang menulis. Tulisan Mernissi ini saya cuplik dari artikelnya
berjudul "Menulis Lebih Baik ketimbang Operasi Pengencangan Kulit
Wajah" yang dimuat di karyanya, Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual
Kaum Wanita dalam Sejarah Islam (Mizan, 1999, h. 34-35):
"Menulis adalah menangkap kesempatan yang amat-sangat-sangat kecil
untuk mengungkapkan perasaan Anda. Itu berarti mengambil risiko untuk
berkomunikasi dengan seseorang yang tidak peduli sama sekali dengan hal yang
Anda pikirkan dan katakan. Menulis surat saja, misalnya, merupakan suatu
kesempatan yang luar biasa bagi seseorang yang terisolasi.
"Pada saat Anda menulis surat, Anda mula-mula berdialog dengan diri
Anda sendiri. Kemudian, ada kemungkinan surat itu Anda kirimkan kepada orang
yang terdekat dengan diri Anda. Bahkan, bisa jadi, surat itu Anda kirimkan ke
orang-orang yang sedang berkuasa.
"Meskipun saya tidak bisa menjamin surat Anda bisa dibaca oleh orang
yang berkuasa, yang jelas apabila Anda berusaha mengungkapkan diri Anda setiap
hari maka Anda memang tidak dapat mengubah langsung dunia, namun Anda
sebenarnya dapat mengubah diri Anda sendiri. Dan saya yakin bahwa dengan
mengubah diri sendiri, sesungguhnya Anda tengah mengubah dunia."
Saya kira, saya sudah membuktikan apa yang dikatakan dan diyakini oleh
Fatima Mernissi. Saya dapat menunjukkan apa yang dikatakan Mernisi lewat dua
karya saya, Mengikat Makna dan Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza. Semoga
bermanfaat.[]
Menulis Itu Melatih Saya untuk Jujur
Oleh : Hernowo
Pada Jumat, 16 Mei 2003, pukul 13.00 WIB hingga selesai, akan diadakan
sebuah diskusi buku karya Hernowo, Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza: Rangsangan
Baru untuk Melejitkan "Word Smart" (Kaifa, 2003, cetakan kedua).
Acara ini akan diselenggarakan di Masjid Agung At-Tin, tepatnya di Ruang
Serbaguna, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Penulis buku Andaikan akan
hadir sebagai pembicara pertama, dan sebagai pembahas akan dihadirkan seorang
penulis dan pemerhati sastra, Joni Ariadinata. Sementara itu, acara ini akan
dibuka sekaligus dimoderatori oleh penulis fiksi yang baru-baru ini mendapat
penghargaan dari Penerbit Mizan, Asma Nadia. Berikut adalah tulisan Hernowo
untuk acara tersebut. Selamat menikmati.
Mahkota seniman adalah keindahan yang akan menghayati hasratnya dan
menimbulkan cinta. Dalam menyampaikan tugasnya, seorang seniman harus jujur.
Karyanya merupakan ekspresi perasaannya sendiri dan bukan hanya sekadar
mewakili yang di luar dirinya.
Ali Audah
Ya, menuliskan apa saja ke selembar kertas berarti saya sebenarnya sedang
berusaha keras untuk jujur kepada diri saya sendiri. Menulis adalah sebuah
aktivitas yang sangat personal. Yang terlibat hanyalah diri sang penulis,
meskipun dia menuliskan tentang persoalan-persoalan besar yang melingkupi
dirinya.
Memang betul bahwa pada saat saya menulis, saya dibantu oleh banyak hal.
Pertama, mungkin, adalah pengalaman saya berinteraksi dengan orang lain. Ini
jelas sesuatu yang membuat saya punya bahan untuk dituliskan. Saya tidak
dapat--atau akan mengalami kesulitan--menulis apabila bahan-bahan yang ingin
saya tuliskan tidak atau belum menjadi bagian dari pengalaman saya.
Kedua, mungkin, saya dibantu atau, bahkan, didorong oleh gagasan-hebat
milik orang lain sehingga saya harus menuliskan sesuatu. Gagasan-hebat ini bisa
saja saya temukan di buku-buku yang saya baca, atau saya peroleh dari menonton
film, sinetron, atau saya gaet dari irama musik yang saya dengarkan.
Kadang-kadang gagasan yang mampu mendorong saya menulis datang bagaikan kilat.
Dan ini, kadang, tidak bisa saya duga sebelumnya.
Ketiga, mungkin saja, saya dibantu oleh ketidakstabilan emosi saya akibat
gangguan orang lain. Misalnya saja saya dibuat kesal oleh seseorang atau saya
dipuji habis-habisan oleh seseorang sehingga diri saya limbung. EQ atau
kecerdasan emosi biasanya sangat sering saya gunakan pada saat-saat awal mau
menulis.
Tentu, tidak hanya tiga hal itu yang membantu saya sehingga saya dapat
menuliskan sesuatu. Saya kira saya masih bisa menyebutkan banyak hal. Dan saya
kira, orang lain bisa menyebut lagi lebih banyak hal ketika dia dapat
menuliskan sesuatu. Saya cukupkan tiga hal itu sekadar menunjukkan bahwa,
meskipun menulis itu merupakan kegiatan yang sangat personal, tetap saja banyak
faktor di luar sang diri personal yang membantunya dapat menulis.
Namun--lagi-lagi saya harus cepat-cepat menambahkan sesuatu di sini--semua
itu tetap harus dikembalikan kepada diri sendiri pada saat kita mau menuliskan
sesuatu. Apa pun faktor di luar diri Anda yang dapat mempengaruhi atau
menggerakkan Anda untuk bisa menulis, faktor-faktor dari luar itu tetap tidak
ada gunanya apabila tidak Anda pertemukan dengan totalitas diri Anda. Apabila
kita tidak dapat berkompromi dengan, atau tidak mau memahami, atau tidak jujur
kepada diri kita sendiri, ada kemungkinan kita tidak dapat menulis secara
lancar, mengalir, dan menyenangkan.
**
Apa yang saya maksud dengan "jujur kepada diri sendiri"? Tidak
mudah, memang, membicarakan soal jujur ini. Bagaimana kita mengukur sebuah kejujuran?
Apabila kejujuran dikaitkan dengan kegiatan menulis, ada kemungkinan kita dapat
mengukur soal jujur ini dari seberapa jauh seorang penulis tidak menjiplak atau
menelan mentah-mentah gagasan-orisinal orang lain.
Apakah di dunia ini ada gagasan-orisinal milik seorang penulis, misalnya?
Bukankah setiap penulis itu tentu, ujung-ujungnya, hanya merakit
gagasan-gagasan banyak orang dan kemudian sedikit diimbuhi dengan gagasannya
sendiri? Bagaimana menentukan bahwa sebuah gagasan adalah milik atau merupakan
temuan orisinal seorang penulis ?
Bagaimana pula dengan sosok seorang Chairil Anwar yang, pada awal mencipta
sajak, menurut beberapa pengamat, beliau belajar banyak dari sajak-sajak orang
lain? Bagaimana pula dengan Buya Hamka yang pernah diisukan menciptakan sebuah
novel yang juga, menurut beberapa pengamat, mirip dengan novel yang diciptakan
oleh penulis asing? Bagaimana kita mendudukkan soal-soal seperti ini?
Saya tidak ingin membawa persoalan "jujur kepada diri sendiri"
itu melebar-lebar. Saya akan mencoba menunjukkan saja kepada para pembaca
tulisan saya tentang pendapat saya. Bisa jadi, pendapat saya ini masih belum
sempurna atau banyak memiliki kekurangan. Namun, yang ingin saya harapkan
adalah semoga saya dapat membantu Anda untuk memecahkan sendiri
persoalan-persoalan berkaitan dengan kejujuran dalam menulis.
Pertama, saya kok sangat yakin bahwa setiap manusia--termasuk di sini para
penulis--punya ciri khasnya sendiri-sendiri yang tidak mungkin sama persis
dengan orang lain. Saya kira, pada suatu saat kelak, entah kapan, setiap
manusia bisa menemukan sendiri ciri khas tersebut. Apalagi seorang penulis.
Seorang penulis diberi kemampuan lebih oleh Sang Penciptanya untuk lebih cepat,
lebih kukuh, dan lebih percaya diri dalam menemukan ciri-ciri khas yang
dimilikinya.
Jadi, bagi saya, pada tahap sangat awal, seorang penulis layak meniru gaya
penulis lain. Bahkan di sini, saya ingin mengatakan, secara tegas dan lantang:
harus! Harus meniru lebih dahulu. Dahulu, waktu masih kanak-kanak, kita meniru
cara bicara orangtua kita. Juga, kita meniru cara berjalan orang-orang di
sekeliling kita. Sekarang, sesudah dewasa, kita punya ciri khas sendiri dalam
berbicara. Juga, mungkin, dalam berjalan. Jadi, tidak apa, pada saat awal,
meniru bukan?
Bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam bentuk plagiat? Jujurlah kepada
diri Anda sendiri. Saya kira tidak usah orang lain yang memutuskan bahwa kita
ini seorang plagiat dengan deretan bukti yang ditunjukkan oleh orang lain.
Sebelum kita mau menerbitkan karya tulis kita, sebenarnya kita dapat bertanya
kepada diri sendiri tentang apakah karya tulis kita merupakan plagiat atau
tidak.
Bagaimana kalau suara hati kita mengatakan itu tidak merupakan karya
plagiat, namun di dalamnya ada beberapa tulisan yang meniru gagasan orang lain?
Asal kita dapat mempertanggungjawabkan, kenapa kita harus takut? Sekali lagi,
meniru tidaklah merupakan suatu cela pada saat kita memang mau belajar menulis.
Meniru, ada kemungkinan, bisa membantu kita untuk menemukan karakter kita.
Kedua, saya kok juga yakin bahwa setiap orang dapat menuliskan sesuatu.
Setiap orang tentu mempunyai pengalaman, seberapa pun sederhananya pengalaman
yang dimilikinya. Pengalaman inilah yang dapat dijadikan bahan untuk
dituliskan. Apa gunanya pengalaman dituliskan? Ya untuk diseleksi, lewat
kegiatan menulis, apakah pengalaman itu berharga untuk diri sendirinya atau
tidak? Kalau tidak atau kurang berharga? Ya dicoba dihargainya sendiri atau
dicari jalan keluarnya agar pengalaman berikutnya dapat mengesankannya atau
membuat dirinya berharga. Dan ini bisa dilakukan siapa saja lewat menulis.
Kadang-kadang, memang, ada orang yang sudah kebelet atau kepingin menulis
tetapi macet atau kehabisan kata-kata. Saya ingin menunjukkan kepada orang ini
bahwa sebenarnya bukan soal dia tidak bisa atau tidak mampu menulis. Tetapi
yang membuat dirinya macet menulis adalah ketidaktersediaan bahan yang ada pada
dirinya. Atau dalam kata lain, orang ini sebenarnya tidak punya banyak
pengalaman mengenai apa yang ingin ditulisnya.
Nah, untuk memudahkan agar kita dapat menuliskan sesuatu berdasarkan
pengalaman yang kita miliki, kita harus bersikap jujur kepada diri kita
sendiri. Kalau kita menipu diri kita--dengan mengatakan bahwa di dalam diri
tersimpan banyak pengalaman berharga yang layak dibagikan kepada orang lain,
padahal sebenarnya tidak ada--ya, tentu, kita akan kesulitan dalam menuangkan
pengalaman kita dalam bentuk tertulis. (Meskipun, ya meskipun, kita sudah
dibantu oleh seorang penulis andal lain dalam menuliskan pengalaman kita itu.)
Agar kita dapat jujur dengan diri kita sendiri saat menuliskan pengalaman
kita, saya sarankan menulislah lebih dulu untuk ditujukan kepada diri sendiri.
Buatlah catatan harian yang diisi setiap hari secara kontinu dan konsisten.
Buku catatan harian dapat menjadi alat bantu yang luar biasa--dan saya sudah
membuktikan keampuhannya--dalam melakukan tes apakah kita punya pengalaman
berharga atau tidak untuk kita bagikan kepada orang lain. Saya kira, buku
catatan harian juga bisa lebih berperan dari sekadar alat bantu seperti itu.
Buku catatan harian juga dapat menunjukkan siapa diri kita, apa ciri khas kita,
dan apa sebenarnya keunikan yang kita miliki.
**
Sampailah kita pada batas akhir. Apakah kejujuran ini bisa menjadi
kriteria-baru untuk sebuah tulisan yang baik? Apa sebenarnya tulisan yang baik
itu? Menurut saya, tulisan yang baik adalah tulisan yang bermanfaat bagi
perkembangan diri orang lain. Apabila tulisan itu dibaca orang lain dan orang
lain yang membacanya dapat memperbaiki dirinya akibat membaca tulisan itu, maka
inilah yang saya maksud dengan tulisan yang baik.
Tulisan dalam bentuk fiksi ataupun nonfiksi dapat bertindak sebagaimana
yang saya sebutkan sebelum ini. Tulisan dapat mempengaruhi orang lain. Tulisan
berbeda dengan penggambaran secara visual. Sebuah tulisan dapat mengajak
seseorang untuk merenungkan diri sendirinya. Tulisan dapat berubah seperti
cermin yang dapat digunakan untuk berkaca--baik itu menyangkut keadaan fisik
maupun nonfisik orang yang membaca sebuah tulisan.
Nah, supaya setiap tulisan yang dilahirkan oleh seorang penulis dapat
menjadi tulisan yang baik dan dapat mempengaruhi pembacanya menjadi lebih baik,
saya ingin mensyaratkan bahwa tulisan tersebut harus ditulis secara jujur oleh
penulisnya. Semoga apa yang saya gagas ini dapat dipahami. Dan saya ingin
mengakhiri tulisan saya ini dengan kata-kata berikut ini:
"Saya hanya bisa mengeluarkan kata-kata dan merangkai kata-kata itu
menjadi sesuatu yang berharga (atau kadang kata-kata itu "bertenaga")
untuk diri saya--dan semoga juga berharga untuk pembaca tulisan saya--apabila
saya menulis apa adanya tentang diri saya. Ini berarti saya harus jujur kepada
diri saya sendiri.".**
Buku, Ingatan, Kenangan
Oleh : Anwar Holid
Barangkali buku memang menolong kita untuk mengingat kembali banyak hal,
merunutkan segala yang berserakan di kepala dan hasrat. Menyimpan kenangan,
mencatat sejarah dan kejadian, memberi banyak pengetahuan & harapan. Sejauh
mungkin menyingkirkan ingatan kita pada kematian dan putus asa. Dengan segala
cara buku memerangi sebisa mungkin musuh besar manusia yang disebut Milan
Kundera: lupa. Jawaban membenarkan itu; bahwa semakin banyak orang membaca,
semakin banyak mengisi akal dengan pengetahuan, jiwa diaktifkan, hidup
seseorang akan semakin waras. Uzur dan pikun menjauh. Sebab begitu manusia
pikun atau alpa, kehidupannya akan menyedihkan, menjadi kekanak-kanakan, dan
emosinya tak stabil.
Minggu, 22 September 2002. Kami pindah ke sebuah rumah kecil, di kawasan
Panorama, Geger Kalong Girang, Bandung. Saking kecilnya, tukang angkut yang
membantu kami itu mengeluh, "Apa masih muat tempatnya?" saat kami
bolak-balik keempat kalinya dari rumah lama membawa berbagai barang: buku,
perabot, baju, kaset, CD, kertas, dokumen, dan lain-lainnya. Saya dan istri
tertawa. Memang, rumah ini terlalu kecil untuk langsung diisi oleh barang
sebanyak itu.
"Mas, bukunya banyak-banyak amat sih!" tukang angkut itu masih
berkomentar saat harus bolak-balik membawa berkardus-kardus berisi buku yang
kami miliki. Sebagian besar adalah buku yang saya miliki saat masih lajang dan
akhirnya menjadi bagian dari mahar. Sebagian lagi milik istri saya. Lainnya
jelas-jelas merupakan harta gono-gini, karena kami memilikinya saat sudah
menjadi suami-istri. Sisanya berasal dari "warisan" banyak orang:
paman istri saya mewariskan beberapa buku mewah tentang kapal, buku foto
Indonesia masa revolusi, sejarah bergambar bangsa Yahudi, dan tumbuh-tumbuhan.
Ada hadiah dari mantan atasan usai berhasil menulis di media massa. Ada
kumpulan puisi sebagai hadiah perkawinan kami, dari pasangan penyair Benny R.
Budiman dan Nenden Elis.
Betulkah buku milik kami sangat banyak? Meskipun kenyataannya memang
menyita hampir seluruh rak lemari di rumah, saya tetap tak berani bilang bahwa
itu banyak. Ketika saya beres-beres rumah hampir seminggu lamanya, ternyata
buku menyita waktu paling lama untuk dirapikan dibandingkan baju, foto, dan
perabot lain. Pantas saja tukang angkut itu keberatan mengangkat-angkat
kardus-kardus, seakan tak akan habis.
Meskipun mungkin tak sampai ribuan judul--kami belum bikin katalog--buku
menjadi hiasan dominan di rumah kecil itu. Saat malam-malam menjelang tidur,
saya terhenyak, bagaimana jadinya kalau orang yang koleksinya lebih banyak dari
kami pindah dan membawa serta buku mereka? Saya kenal beberapa orang yang koleksi
bukunya ribuan. Artinya, milik kami itu tak ada apa-apanya. Tapi, memang sih,
katakanlah di lingkungan RT, buku kami termasuk sangat banyak. Adakah sesuatu
yang berharga dari deretan buku yang mengisi rak-rak almari itu?
Sambil membereskan buku, dalam hati saya mendesah, "Ya Tuhan, semoga
saya mendapatkan setetes ilmu dari ratusan buku yang berjejer di sini."
Saya terharu. Baru menyadari betapa banyak artinya buku-buku itu bagi kehidupan
saya, istri, dan anak. Saya berharap minimal mendapatkan sesuatu dari buku yang
bertumpuk-tumpuk memenuhi ruang dalam rumah dan hati ini. Apa pun. Barangkali
sejumput hikmah, khazanah, pengetahuan, kenangan, puisi, kisah, keindahan,
bahkan yang fisikal, termasuk sejumlah uang.
Ketika tiba-tiba memegang sebuah judul, saya teringat kala pertama kali
mengerjakan order terjemahan dari penerbit yang saya sanjung. Atau teringat
uang hasil terjemahan Fihi ma Fihi karya Rumi itu habis semuanya untuk
keperluan salin istri dan belanja kebutuhan anak pertama kami. Ada yang
merupakan hadiah dari kawan dekat, dibeli karena ingin mendekati seorang gadis,
atau sebagai hadiah kepada istri dan anak. Begitu kembali melihat Merahnya
Merah saya langsung takjub bahwa saya telah membacanya di usia yang sangat
dini, kelas 5 SD. Bahkan saya sendiri ragu bisa memahaminya hingga kini,
meskipun selalu tergetar oleh petualangan dan kisah tokohnya.
Saya tersenyum lebar memperhatikan print-out Saman, yang saya lakukan di
sela-sela hiruk-pikuk demo menjatuhkan rezim Soeharto, krisis kertas, ekonomi,
dan Piala Dunia 1998. Dulu, naskah itu baru menghebohkan sastra Indonesia,
belum lagi diterbitkan, dan saya bersyukur sekali mendapatkan copy file-nya
dari seorang teman, Aendra H. Medita, wartawan D&R. Sekarang, print-out itu
saya sandingkan dengan Larung, yang ditandatangani Ayu Utami di
ak.'sa.ra--sebagai bentuk takzim saya kepada para penulis--saat didiskusikan
dan "dibandingkan" dengan The God of Small Thing. Bagi saya penulis
itu mirip Tuhan, sebab mereka melakukan yang juga dikerjakan Tuhan: mencipta.
Sebuah buku Inggris bergambar ternyata kini menjadi kawan akrab anak kami,
menjadi media latih bicara dan belajar mengenal banyak nama, peristiwa, angka,
dan warna. Buku itu sering dia bawa ke mana pun dia pergi. Padahal anak lain
biasanya membawa mobil-mobilan atau pesawat mainan. Sekarang dia mulai akrab
dengan buku lain: kisah nabi, binatang, Harry Potter, Winnie The Pooh dan
kawan-kawannya, dongeng rakyat, juga Harun dan Lautan Dongeng karya Salman
Rushdie itu. Ibunya yang rajin mendongengkan menjelang tidur--dan itu rupanya
menenangkan dia.
Ternyata, buku-buku itu memberi banyak sekali pada saya. Mereka memberi
energi, semangat, inspirasi, gagasan, perubahan, membentuk sikap, wawasan,
pengetahuan, ilmu. Benar-benar tak disangka, betapa dalam kehidupan ini saya
setiap saat berhubungan dengan buku, sastra, penerbitan, dan tulis-menulis.
Bahkan nyaris tenggelam di dalamnya. Saya melihat dan memahami banyak hal dari
buku-buku. Mencoba memahami banyak hal: sastra, seni rupa, kebudayaan,
filsafat, kritik sosial, filsafat, agama, tasawuf, tokoh-tokoh kehidupan.
Tapi, terus-terang, saya suka kecut jangan-jangan buku sebanyak itu tak
sebegitu bergunanya bagi kehidupan seseorang. Kawan saya pernah bilang,
"Kamu tak akan pernah bisa jadi sufi sekalipun sudah baca buku tasawuf
se-Bandung ini. Ada banyak hal yang tidak bisa didapat dari sekadar membaca;
melainkan kamu harus mempraktikkannya, melatihnya, melakukannya. Bukan sekadar
memahami dan mengetahui."
Dia benar. Kita kadang-kadang masih bisa memahami sesuatu, tetapi tidak
selamanya setuju atau mau melakukan yang dimengerti itu. Saya masih ingat
pernah dicemooh karena sering mengutip bacaan atau buku sebagai cermin
kehidupan. Katanya, "Tahu nggak, buku itu fiksi, karangan, nggak nyata.
Kenyataan jauh lebih rumit dari semua yang ditulis itu." Tapi, kata saya,
justru kehidupan yang paling dramatis, yang menyentuh, ada di tulisan, di
catatan harian, di buku-buku. Saya teringat Sampar, Lapar, kehidupan Yusuf Ali,
bahkan pemahaman Frithjof Schuon tentang Islam. Sangat mencengangkan, luar
biasa, mendebarkan.
Barangkali buku memang menolong kita untuk mengingat kembali banyak hal,
merunutkan segala yang berserakan di kepala dan hasrat. Menyimpan kenangan,
mencatat sejarah dan kejadian, memberi banyak pengetahuan & harapan. Sejauh
mungkin menyingkirkan ingatan kita pada kematian dan putus asa. Dengan segala
cara buku memerangi sebisa mungkin musuh besar manusia yang disebut Milan
Kundera: lupa. Jawaban membenarkan itu; bahwa semakin banyak orang membaca,
semakin banyak mengisi akal dengan pengetahuan, jiwa diaktifkan, hidup
seseorang akan semakin waras. Uzur dan pikun menjauh. Sebab begitu manusia
pikun atau alpa, kehidupannya akan menyedihkan, menjadi kekanak-kanakan, dan
emosinya tak stabil.
Selesai menjejerkan buku-buku di rak itu, saya terdiam. Betapa saya
beruntung dan berusaha bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk mengintip,
merasakan, menjelajahi dunia antah-berantah dari rumah sekecil ini. Saya diberi
jendela pengetahuan. Diberi kunci ilmu. Diberi mata-hati. Semuanya saya lakukan
dari sebuah buku. []
Minggu, 22 September 2002. Kami pindah ke sebuah rumah kecil, di kawasan
Panorama, Geger Kalong Girang, Bandung. Saking kecilnya, tukang angkut yang
membantu kami itu mengeluh, "Apa masih muat tempatnya?" saat kami bolak-balik
keempat kalinya dari rumah lama membawa berbagai barang: buku, perabot, baju,
kaset, CD, kertas, dokumen, dan lain-lainnya. Saya dan istri tertawa. Memang,
rumah ini terlalu kecil untuk langsung diisi oleh barang sebanyak itu.
"Mas, bukunya banyak-banyak amat sih!" tukang angkut itu masih
berkomentar saat harus bolak-balik membawa berkardus-kardus berisi buku yang
kami miliki. Sebagian besar adalah buku yang saya miliki saat masih lajang dan
akhirnya menjadi bagian dari mahar. Sebagian lagi milik istri saya. Lainnya
jelas-jelas merupakan harta gono-gini, karena kami memilikinya saat sudah
menjadi suami-istri. Sisanya berasal dari "warisan" banyak orang:
paman istri saya mewariskan beberapa buku mewah tentang kapal, buku foto
Indonesia masa revolusi, sejarah bergambar bangsa Yahudi, dan tumbuh-tumbuhan.
Ada hadiah dari mantan atasan usai berhasil menulis di media massa. Ada
kumpulan puisi sebagai hadiah perkawinan kami, dari pasangan penyair Benny R.
Budiman dan Nenden Elis.
Betulkah buku milik kami sangat banyak? Meskipun kenyataannya memang
menyita hampir seluruh rak lemari di rumah, saya tetap tak berani bilang bahwa
itu banyak. Ketika saya beres-beres rumah hampir seminggu lamanya, ternyata
buku menyita waktu paling lama untuk dirapikan dibandingkan baju, foto, dan
perabot lain. Pantas saja tukang angkut itu keberatan mengangkat-angkat
kardus-kardus, seakan tak akan habis.
Meskipun mungkin tak sampai ribuan judul--kami belum bikin katalog--buku
menjadi hiasan dominan di rumah kecil itu. Saat malam-malam menjelang tidur,
saya terhenyak, bagaimana jadinya kalau orang yang koleksinya lebih banyak dari
kami pindah dan membawa serta buku mereka? Saya kenal beberapa orang yang
koleksi bukunya ribuan. Artinya, milik kami itu tak ada apa-apanya. Tapi, memang
sih, katakanlah di lingkungan RT, buku kami termasuk sangat banyak. Adakah
sesuatu yang berharga dari deretan buku yang mengisi rak-rak almari itu?
Sambil membereskan buku, dalam hati saya mendesah, "Ya Tuhan, semoga
saya mendapatkan setetes ilmu dari ratusan buku yang berjejer di sini."
Saya terharu. Baru menyadari betapa banyak artinya buku-buku itu bagi kehidupan
saya, istri, dan anak. Saya berharap minimal mendapatkan sesuatu dari buku yang
bertumpuk-tumpuk memenuhi ruang dalam rumah dan hati ini. Apa pun. Barangkali
sejumput hikmah, khazanah, pengetahuan, kenangan, puisi, kisah, keindahan,
bahkan yang fisikal, termasuk sejumlah uang.
Ketika tiba-tiba memegang sebuah judul, saya teringat kala pertama kali
mengerjakan order terjemahan dari penerbit yang saya sanjung. Atau teringat
uang hasil terjemahan Fihi ma Fihi karya Rumi itu habis semuanya untuk
keperluan salin istri dan belanja kebutuhan anak pertama kami. Ada yang
merupakan hadiah dari kawan dekat, dibeli karena ingin mendekati seorang gadis,
atau sebagai hadiah kepada istri dan anak. Begitu kembali melihat Merahnya
Merah saya langsung takjub bahwa saya telah membacanya di usia yang sangat
dini, kelas 5 SD. Bahkan saya sendiri ragu bisa memahaminya hingga kini,
meskipun selalu tergetar oleh petualangan dan kisah tokohnya.
Saya tersenyum lebar memperhatikan print-out Saman, yang saya lakukan di
sela-sela hiruk-pikuk demo menjatuhkan rezim Soeharto, krisis kertas, ekonomi,
dan Piala Dunia 1998. Dulu, naskah itu baru menghebohkan sastra Indonesia, belum
lagi diterbitkan, dan saya bersyukur sekali mendapatkan copy file-nya dari
seorang teman, Aendra H. Medita, wartawan D&R. Sekarang, print-out itu saya
sandingkan dengan Larung, yang ditandatangani Ayu Utami di ak.'sa.ra--sebagai
bentuk takzim saya kepada para penulis--saat didiskusikan dan
"dibandingkan" dengan The God of Small Thing. Bagi saya penulis itu
mirip Tuhan, sebab mereka melakukan yang juga dikerjakan Tuhan: mencipta.
Sebuah buku Inggris bergambar ternyata kini menjadi kawan akrab anak kami, menjadi
media latih bicara dan belajar mengenal banyak nama, peristiwa, angka, dan
warna. Buku itu sering dia bawa ke mana pun dia pergi. Padahal anak lain
biasanya membawa mobil-mobilan atau pesawat mainan. Sekarang dia mulai akrab
dengan buku lain: kisah nabi, binatang, Harry Potter, Winnie The Pooh dan
kawan-kawannya, dongeng rakyat, juga Harun dan Lautan Dongeng karya Salman
Rushdie itu. Ibunya yang rajin mendongengkan menjelang tidur--dan itu rupanya
menenangkan dia.
Ternyata, buku-buku itu memberi banyak sekali pada saya. Mereka memberi
energi, semangat, inspirasi, gagasan, perubahan, membentuk sikap, wawasan,
pengetahuan, ilmu. Benar-benar tak disangka, betapa dalam kehidupan ini saya
setiap saat berhubungan dengan buku, sastra, penerbitan, dan tulis-menulis.
Bahkan nyaris tenggelam di dalamnya. Saya melihat dan memahami banyak hal dari
buku-buku. Mencoba memahami banyak hal: sastra, seni rupa, kebudayaan,
filsafat, kritik sosial, filsafat, agama, tasawuf, tokoh-tokoh kehidupan.
Tapi, terus-terang, saya suka kecut jangan-jangan buku sebanyak itu tak
sebegitu bergunanya bagi kehidupan seseorang. Kawan saya pernah bilang,
"Kamu tak akan pernah bisa jadi sufi sekalipun sudah baca buku tasawuf
se-Bandung ini. Ada banyak hal yang tidak bisa didapat dari sekadar membaca;
melainkan kamu harus mempraktikkannya, melatihnya, melakukannya. Bukan sekadar
memahami dan mengetahui."
Dia benar. Kita kadang-kadang masih bisa memahami sesuatu, tetapi tidak
selamanya setuju atau mau melakukan yang dimengerti itu. Saya masih ingat
pernah dicemooh karena sering mengutip bacaan atau buku sebagai cermin
kehidupan. Katanya, "Tahu nggak, buku itu fiksi, karangan, nggak nyata.
Kenyataan jauh lebih rumit dari semua yang ditulis itu." Tapi, kata saya,
justru kehidupan yang paling dramatis, yang menyentuh, ada di tulisan, di
catatan harian, di buku-buku. Saya teringat Sampar, Lapar, kehidupan Yusuf Ali,
bahkan pemahaman Frithjof Schuon tentang Islam. Sangat mencengangkan, luar
biasa, mendebarkan.
Barangkali buku memang menolong kita untuk mengingat kembali banyak hal,
merunutkan segala yang berserakan di kepala dan hasrat. Menyimpan kenangan,
mencatat sejarah dan kejadian, memberi banyak pengetahuan & harapan. Sejauh
mungkin menyingkirkan ingatan kita pada kematian dan putus asa. Dengan segala
cara buku memerangi sebisa mungkin musuh besar manusia yang disebut Milan
Kundera: lupa. Jawaban membenarkan itu; bahwa semakin banyak orang membaca,
semakin banyak mengisi akal dengan pengetahuan, jiwa diaktifkan, hidup
seseorang akan semakin waras. Uzur dan pikun menjauh. Sebab begitu manusia
pikun atau alpa, kehidupannya akan menyedihkan, menjadi kekanak-kanakan, dan
emosinya tak stabil.
Selesai menjejerkan buku-buku di rak itu, saya terdiam. Betapa saya
beruntung dan berusaha bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk mengintip,
merasakan, menjelajahi dunia antah-berantah dari rumah sekecil ini. Saya diberi
jendela pengetahuan. Diberi kunci ilmu. Diberi mata-hati. Semuanya saya lakukan
dari sebuah buku. []
Minggu, 22 September 2002. Kami pindah ke sebuah rumah kecil, di kawasan
Panorama, Geger Kalong Girang, Bandung. Saking kecilnya, tukang angkut yang
membantu kami itu mengeluh, "Apa masih muat tempatnya?" saat kami
bolak-balik keempat kalinya dari rumah lama membawa berbagai barang: buku, perabot,
baju, kaset, CD, kertas, dokumen, dan lain-lainnya. Saya dan istri tertawa.
Memang, rumah ini terlalu kecil untuk langsung diisi oleh barang sebanyak itu.
"Mas, bukunya banyak-banyak amat sih!" tukang angkut itu masih
berkomentar saat harus bolak-balik membawa berkardus-kardus berisi buku yang
kami miliki. Sebagian besar adalah buku yang saya miliki saat masih lajang dan
akhirnya menjadi bagian dari mahar. Sebagian lagi milik istri saya. Lainnya
jelas-jelas merupakan harta gono-gini, karena kami memilikinya saat sudah
menjadi suami-istri. Sisanya berasal dari "warisan" banyak orang:
paman istri saya mewariskan beberapa buku mewah tentang kapal, buku foto
Indonesia masa revolusi, sejarah bergambar bangsa Yahudi, dan tumbuh-tumbuhan.
Ada hadiah dari mantan atasan usai berhasil menulis di media massa. Ada
kumpulan puisi sebagai hadiah perkawinan kami, dari pasangan penyair Benny R.
Budiman dan Nenden Elis.
Betulkah buku milik kami sangat banyak? Meskipun kenyataannya memang
menyita hampir seluruh rak lemari di rumah, saya tetap tak berani bilang bahwa
itu banyak. Ketika saya beres-beres rumah hampir seminggu lamanya, ternyata
buku menyita waktu paling lama untuk dirapikan dibandingkan baju, foto, dan
perabot lain. Pantas saja tukang angkut itu keberatan mengangkat-angkat
kardus-kardus, seakan tak akan habis.
Meskipun mungkin tak sampai ribuan judul--kami belum bikin katalog--buku
menjadi hiasan dominan di rumah kecil itu. Saat malam-malam menjelang tidur,
saya terhenyak, bagaimana jadinya kalau orang yang koleksinya lebih banyak dari
kami pindah dan membawa serta buku mereka? Saya kenal beberapa orang yang
koleksi bukunya ribuan. Artinya, milik kami itu tak ada apa-apanya. Tapi,
memang sih, katakanlah di lingkungan RT, buku kami termasuk sangat banyak. Adakah
sesuatu yang berharga dari deretan buku yang mengisi rak-rak almari itu?
Sambil membereskan buku, dalam hati saya mendesah, "Ya Tuhan, semoga
saya mendapatkan setetes ilmu dari ratusan buku yang berjejer di sini."
Saya terharu. Baru menyadari betapa banyak artinya buku-buku itu bagi kehidupan
saya, istri, dan anak. Saya berharap minimal mendapatkan sesuatu dari buku yang
bertumpuk-tumpuk memenuhi ruang dalam rumah dan hati ini. Apa pun. Barangkali
sejumput hikmah, khazanah, pengetahuan, kenangan, puisi, kisah, keindahan,
bahkan yang fisikal, termasuk sejumlah uang.
Ketika tiba-tiba memegang sebuah judul, saya teringat kala pertama kali
mengerjakan order terjemahan dari penerbit yang saya sanjung. Atau teringat
uang hasil terjemahan Fihi ma Fihi karya Rumi itu habis semuanya untuk
keperluan salin istri dan belanja kebutuhan anak pertama kami. Ada yang
merupakan hadiah dari kawan dekat, dibeli karena ingin mendekati seorang gadis,
atau sebagai hadiah kepada istri dan anak. Begitu kembali melihat Merahnya Merah
saya langsung takjub bahwa saya telah membacanya di usia yang sangat dini,
kelas 5 SD. Bahkan saya sendiri ragu bisa memahaminya hingga kini, meskipun
selalu tergetar oleh petualangan dan kisah tokohnya.
Saya tersenyum lebar memperhatikan print-out Saman, yang saya lakukan di
sela-sela hiruk-pikuk demo menjatuhkan rezim Soeharto, krisis kertas, ekonomi,
dan Piala Dunia 1998. Dulu, naskah itu baru menghebohkan sastra Indonesia,
belum lagi diterbitkan, dan saya bersyukur sekali mendapatkan copy file-nya dari
seorang teman, Aendra H. Medita, wartawan D&R. Sekarang, print-out itu saya
sandingkan dengan Larung, yang ditandatangani Ayu Utami di ak.'sa.ra--sebagai
bentuk takzim saya kepada para penulis--saat didiskusikan dan
"dibandingkan" dengan The God of Small Thing. Bagi saya penulis itu
mirip Tuhan, sebab mereka melakukan yang juga dikerjakan Tuhan: mencipta.
Sebuah buku Inggris bergambar ternyata kini menjadi kawan akrab anak kami,
menjadi media latih bicara dan belajar mengenal banyak nama, peristiwa, angka,
dan warna. Buku itu sering dia bawa ke mana pun dia pergi. Padahal anak lain
biasanya membawa mobil-mobilan atau pesawat mainan. Sekarang dia mulai akrab
dengan buku lain: kisah nabi, binatang, Harry Potter, Winnie The Pooh dan
kawan-kawannya, dongeng rakyat, juga Harun dan Lautan Dongeng karya Salman
Rushdie itu. Ibunya yang rajin mendongengkan menjelang tidur--dan itu rupanya
menenangkan dia.
Ternyata, buku-buku itu memberi banyak sekali pada saya. Mereka memberi
energi, semangat, inspirasi, gagasan, perubahan, membentuk sikap, wawasan,
pengetahuan, ilmu. Benar-benar tak disangka, betapa dalam kehidupan ini saya
setiap saat berhubungan dengan buku, sastra, penerbitan, dan tulis-menulis.
Bahkan nyaris tenggelam di dalamnya. Saya melihat dan memahami banyak hal dari
buku-buku. Mencoba memahami banyak hal: sastra, seni rupa, kebudayaan,
filsafat, kritik sosial, filsafat, agama, tasawuf, tokoh-tokoh kehidupan.
Tapi, terus-terang, saya suka kecut jangan-jangan buku sebanyak itu tak
sebegitu bergunanya bagi kehidupan seseorang. Kawan saya pernah bilang,
"Kamu tak akan pernah bisa jadi sufi sekalipun sudah baca buku tasawuf
se-Bandung ini. Ada banyak hal yang tidak bisa didapat dari sekadar membaca;
melainkan kamu harus mempraktikkannya, melatihnya, melakukannya. Bukan sekadar
memahami dan mengetahui."
Dia benar. Kita kadang-kadang masih bisa memahami sesuatu, tetapi tidak
selamanya setuju atau mau melakukan yang dimengerti itu. Saya masih ingat
pernah dicemooh karena sering mengutip bacaan atau buku sebagai cermin
kehidupan. Katanya, "Tahu nggak, buku itu fiksi, karangan, nggak nyata.
Kenyataan jauh lebih rumit dari semua yang ditulis itu." Tapi, kata saya,
justru kehidupan yang paling dramatis, yang menyentuh, ada di tulisan, di
catatan harian, di buku-buku. Saya teringat Sampar, Lapar, kehidupan Yusuf Ali,
bahkan pemahaman Frithjof Schuon tentang Islam. Sangat mencengangkan, luar
biasa, mendebarkan.
Barangkali buku memang menolong kita untuk mengingat kembali banyak hal,
merunutkan segala yang berserakan di kepala dan hasrat. Menyimpan kenangan,
mencatat sejarah dan kejadian, memberi banyak pengetahuan & harapan. Sejauh
mungkin menyingkirkan ingatan kita pada kematian dan putus asa. Dengan segala
cara buku memerangi sebisa mungkin musuh besar manusia yang disebut Milan
Kundera: lupa. Jawaban membenarkan itu; bahwa semakin banyak orang membaca,
semakin banyak mengisi akal dengan pengetahuan, jiwa diaktifkan, hidup
seseorang akan semakin waras. Uzur dan pikun menjauh. Sebab begitu manusia
pikun atau alpa, kehidupannya akan menyedihkan, menjadi kekanak-kanakan, dan
emosinya tak stabil.
Selesai menjejerkan buku-buku di rak itu, saya terdiam. Betapa saya
beruntung dan berusaha bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk mengintip,
merasakan, menjelajahi dunia antah-berantah dari rumah sekecil ini. Saya diberi
jendela pengetahuan. Diberi kunci ilmu. Diberi mata-hati. Semuanya saya lakukan
dari sebuah buku. []
Annemarie Schimmel
Ia Datang Bagai Mutiara Peradaban
Oleh : Yuliani Liputo
Erfurt adalah sebuah kota kecil di bagian Jerman. Di kota inilah dibesarkan
seorang gadis dengan minat yang dianggap aneh di masa ketika negerinya sedang
tercabik-cabik oleh Perang Dunia II. Ketika nasionalisme dan fanatisme politik
tengah memenuhi udara Jerman, Annemarie Schimmel justru tenggelam dalam pesona
bahasa Arab dan sejarah kebudayaan Islam.
Schimmel masih berusia lima belas
tahun ketika pertama kali terpikat pada puisi-puisi berbahasa Arab. Melalui
guru bahasa Arabnya dia diperkenalkan pada sejarah kebudayaan Islam. Jalan
telah dipilihkan baginya. Sepanjang hidupnya setelah itu dia konsisten menekuni
bidang kajian Islam dan membuahkan karya-karya penting antara lain Gabriel's
Wing: A Study into the Religious Ideas of Sir Muhammad Iqbal; Mystical
Dimentions of Islam; And Muhammad is His Messenger; A Two-Colored Brocade: The
Imagery of Persian Poetry; Calligraphy and Islamic Culture, serta puluhan
makalah dan terjemahan dalam bahasa Turki, Jerman, dan Inggris.
Dua tokoh Islam yang menjadi pusat perhatian Schimmel adalah Mawlana
Jalaluddin Rumi dan Muhammad Iqbal. Perkenalan pertamanya dengan Rumi adalah
lewat Diwan-i Shams-i Tabriz terjemahan R.A. Nicholson yang disalinnya dengan
tangan. Dia berhasil membuat terjemahannya sendiri yang pertama atas
puisi-puisi Rumi dan Hallaj pada Desember 1940.
Rumi menjadi begitu hidup di tangan Schimmel, seperti yang dipaparkan pada
buku Akulah Angin, Engkaulah Api: Hidup dan Karya Jalaluddin Rumi (Mizan,
1993). Minat puitisnya disertai dengan bakat pemahaman spiritual yang tajam
menghasilkan ulasan-ulasan yang kembali menghadirkan Rumi kepada khalayak
pembaca secara lebih nyata dibanding para penulis lain.
Ketika menjadi profesor Sejarah Agama di Universitas Ankara, Turki,
Schimmel sering mengadakan kunjungan ke Konya, tempat dimakamkannya sang
Mawlana. Pada acara peringatan hari lahir Rumi, 17 Desember 1954, dia diberi
kehormatan untuk menyampaikan kuliah pembuka. Kegiatan itu baru mulai
diselenggarakan kembali setelah lama dilarang oleh pemerintahan Turki.
Di sanalah untuk pertama kalinya Schimmel mendapat kesempatan menyaksikan
tarian darwisy. Pengalaman ini membuat Rumi semakin hidup dalam diri Schimmel,
menjadi sumber inspirasi dan penenang hatinya hingga saat ini.
Kekagumannya pada penyair Indo-Muslim Muhammad Iqbal tumbuh bersamaan, namun
baru mendapat perhatian ketika dia mulai sering diundang ke Pakistan sejak
1958. Iqbal bagi Schimmel adalah personifikasi gabungan semangat Rumi dan
Goethe, seorang pembaru yang aktif dalam politik dan sekaligus sangat mistikal.
Schimmel tergerak untuk menerjemahkan salah satu karya Iqbal, Javidnama, ke
dalam bahasa Turki. Terjemahan inilah yang membuatnya dekat dengan Pakistan.
Di Pakistan dia menemukan bukan hanya kenangan dan gema karya-karya Iqbal,
tetapi juga keindahan ekspresi puitis bahasa Urdu. Negeri Iqbal ini seakan
menjadi tanah air kedua bagi Schimmel. Dia dekat dengan Bhutto dan Jenderal Zia
ul-Haq, sering muncul di acara-acara TV Pakistan, dan akhirnya diangkat menjadi
warga kehormatan Pakistan dengan memperoleh penghargaan Hilal-i Pakistan
melalui sebuah upacara yang juga dihadiri oleh Aga Khan. Sejak 1982, namanya
bahkan diabadikan di salah satu jalan yang indah di Kota Lahore.
Ketika memilih untuk belajar sejarah kebudayaan Islam di Universitas
Berlin, Schimmel barangkali tak pernah membayangkan, suatu hari akan menjadi
Presiden Asosiasi Sejarah Agama Internasional (1980), atau diundang untuk
memberikan kuliah Gifford di Edinburgh, atau menjadi profesor universitas
bergengsi di Amerika, Harvard University.
Tapi dunia akademis seakan telah diniscayakan baginya. Setelah berhasil
memperoleh gelar Ph.D. di bidang studi-studi Islam pada November 1941 (ketika
masih berusia 21 tahun). Schimmel diangkat menjadi profesor untuk bidang yang
sama di Universitas Marburg atas rekomendasi seorang sejarawan agama Jerman
yang dikaguminya, Friedrich Heiler. Setelah itu berturut-turut dia mengajar di
Universitas Ankara, Turki, Universitas Bonn, dan terakhir di Harvard University
sebagai profesor kultur Indo-Muslim sejak 1970.
Setumpuk gelar dan kehormatan pun diraihnya dari berbagai universitas di
Eropa dan Timur Tengah, demikian pula penghargaan dan medali sebagai pengakuan
dunia atas sumbangsih pentingnya terhadap bidang kajian sejarah agama,
literatur dan mistisisme. Pada lima tahun silam, Schimmel menerima "Peace
Price 1995" dari German Book Trade.
Schimmel senang menggambarkan perjalanan hidupnya sebagai lingkaran proses
belajar yang terus membesar. Belajar baginya adalah proses mengubah pengetahuan
dan pengalaman menjadi kebijakan dan cinta, untuk menjadi dewasa. Seperti kisah
dari Timur, kerikil bisa berubah menjadi batu ruby jika ia dengan sabar menahan
sinar matahari. Menumpahkan darahnya sendiri dalam sebuah pengorbanan
tertinggi. Schimmel adalah mutiara yang membawakan pemahaman yang lebih baik
tentang Islam kepada Barat.
Beberapa karya Schimmel yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
antara lain: Dan Muhammad adalah Utusan Allah: Penghormatan terhadap Nabi Saw.
dalam Islam (1991), Akulah Angin Engkaulah Api: Hidup dan Karya Jalaluddin Rumi
(1993), Rahasia Wajah Suci Ilahi: Memahami Islam secara Fenomenologi (1996),
dan Jiwaku adalah Wanita: Aspek Feminin dalamSpiritualitas Islam (1998).[]
Sebuah Jembatan Yang Terbangun Dari Kata-Kata
Warisan Annemarie Schimmel
Oleh : Pangestuningsih
Musim semi 1996. Perempuan berperawakan mungil itu menjadi satu-satunya
pusat perhatian dalam pertemuan yang dihadiri para penulis, penerbit, dan
pejabat tinggi Jerman, termasuk Presiden Roman Herzog. Perempuan itu, Annemarie
Schimmel, berbicara tentang kata. "Kata yang baik laksana pohon yang
baik...", demikian dia mengutip Al Quran. "Kata diyakini sebagai
suatu kekuatan kreatif oleh sebagian besar agama di dunia; katalah yang
mengantarkan wahyu; kata diamanahkan kepada umat manusia sebagai titipan yang
harus dijaga, jangan sampai ada yang teraniaya, terfitnah, atau terbunuh oleh
kata-kata."
"Kata memiliki kekuatan yang tak dapat kita ukur. Dan pada kekuatan
kata inilah terletak tanggung jawab para penyair, lebih-lebih lagi para
penerjemah, karena satu kesalahan samar saja dapat memicu kesalahpahaman yang
berbahaya."
Nyata benar pesan yang disampaikan Schimmel saat menerima penghargaan
tahunan Peace Prize dari German Books Trade itu bukan sekadar sambutan
seremonial. Persis setelah namanya diumumkan sebagai pemenang Peace Price
setahun sebelumnya, sekitar dua ratus intelektual Jerman dan Eropa memprotes
penganugerahan tersebut. Lewat kata-kata, mereka menuding Schimmel mendukung
apa yang mereka namakan sebagai "fundamentalisme Islam"--sebuah
kampanye yang disebut Schimmel telah "menghancurkan apa yang saya bangun
hampir seumur hidup saya, melukai hati dan pikiran saya...." Kendati
demikian Schimmel tetap berbesar hati bahkan memanjatkan doa, "Semoga
mereka yang menyerang saya bahkan tanpa mengenal saya secara pribadi atau
membaca karya-karya saya, tidak akan mengalami luka seperti yang saya rasakan.
Ketulusan Schimmel itu tentu tak lepas dari masa panjang kehidupan yang
dilaluinya dengan merawat dan mencintai "kata-kata yang baik". Wanita
kelahiran Erfurt, Jerman, ini belum lama beranjak dari usia 10 tahun ketika dia
terpikat pada puisi-puisi berbahasa Arab. Lewat jalan kata-kata pula dia
mengenal sejarah dan kebudayaan Islam, menekuni kajian Islam dan menghasilkan
karya-karya monumental seperti Gabriel's Wing: A Study into the Religious Ideas
of Sir Muhammad Iqbal; Mystical Dimensions of Islam; And Muhammad is His
Messenger; A Two Colored Brocade: The Imagery of Persian Poetry; Calligraphy
and Islamic Culture.
Demikian besar keyakinan Schimmel pada kata-kata, seyakin dia pada moto
penyair Jerman Friedrich Ruckert, bahwa "Puisi semata mampu menuntun
manusia menuju rekonsiliasi dunia." Puisi, menurut Ruckert, adalah
"lidah utama umat manusia"; puisi menghubungkan manusia karena ia
menjadi bagian dari setiap peradaban di dunia.
Schimmel menggambarkan kekuatan kata dalam membangun hubungan antarmanusia
ini dengan menyitir sebuah cerita dalam tulisan Mawlana Jalaluddin Rumi. Dalam
prosa berbahasa Persia itu, Rumi--sufi dan penyair abad 13 yang mendapat
perhatian besar Schimmel selain penyair Pakistan Muhammad Iqbal--mengisahkan
seorang anak laki-laki yang sering mengeluh pada ibunya tentang sosok hitam
yang menakutkannya. Akhirnya sang ibu menasehati agar anaknya menyapa saja
sosok hitam tersebut, karena sifat sosok itu bisa diketahui dari jawabannya
terhadap sapaan kita. Sebab kata-kata, sebagaimana sering dinyatakan para
penyair Persia, menyingkapkan sifat pembicaranya layaknya bebauan--persis
dengan kenyataan bahwa kita tak mungkin tertipu oleh kue yang bertabur bawang
putih, bukannya almond, kendati penampilannya sungguh mengundang selera.
Pesona kata jua yang telah membawa Annemarie Schimmel melanglang berbagai
kawasan masyarakat Muslim; masyarakat yang disebutnya lebih terpesona pada kata
dan bahasa, berbeda dengan rekannya di Barat yang lebih terpikat pada musik. Di
usianya yang masih belia ketika itu, sebagai profesor Sejarah Agama di
Universitas Ankara, Schimmel seolah mengenali kembali sudut-sudut Istanbul masa
lalu melalui baris-baris tentang kota indah itu, yang didendangkan para penyair
Turki selama hampir lima abad. Schimmel pun mampu mencintai budaya Pakistan
melalui syair-syair yang dinyanyikan di seluruh provinsi di negara itu.
Schimmel juga sempat mencatat pengalaman seorang mahasiswanya, satu di antara
warga Amerika yang disandera di Teheran saat terjadi Revolusi Iran. Sang
mahasiswa menyadari perubahan sikap penyanderanya, ketika dia melafalkan sebuah
syair Persia. Kata-kata dalam syair itu telah menjadi sebuah jembatan,
menghapuskan perbedaan ideologis yang demikian dalam. Persis seperti yang
dikatakan Herder, "Dari puisi kita mendapatkan pemahaman tentang sebuah
zaman atau suatu bangsa secara mendalam, lebih ketimbang yang kita dapatkan
dari sejarah politik dan militer."
Sang pembangun jembatan itu kini telah tiada. Annemarie Schimmel, meninggal
dunia 28 Januari 2003 di Bonn, Jerman, pada usia 80 tahun. Hanya semangat dan
kecintaannya terhadap "kata-kata yang baik" yang dapat kita
lestarikan, sebenarnyalah kita perlukan, di era kini ketika kata-kata lebih
sering memisahkan ketimbang menyatukan; lebih sering memutuskan ketimbang
menghubungkan. Betapa terasa kini semangat dan kecintaan Schimmel itu demikian
berharga. Dan betapa mengharukan karenanya, kerendahan hati pencinta kata itu,
yang tercermin dalam puisinya:
sang pencinta,
menenun satin dan brokat
dari air mata, O Kawan, agar dapat menghamparkannya
suatu hari, di bawah telapak kakimu...
dan aku menenun
sutera kata-kata yang selalu baru
hanya untuk menyembunyikanmu.[]
Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza
Oleh : Hernowo
Ya, andaikan buku-buku yang ada di rak-rak perpustakaan adalah
"makanan" kesukaan kita. Apa jadinya ya? Tentu kita akan lahap
membacanya. Inilah "kunci" untuk membuka gembok yang menyebabkan kita
enggan membaca buku.
"Kunci" ini, oleh Stephen Covey (penulis The 7 Habits of Highly
Effective People), disebut paradigma. Apaan tuh paradigma? Paradigma adalah
kacamata. Paradigma adalah cara kita memandang sesuatu.
Bayangkan Anda memiliki kacamata minus 2. Lima tahun kemudian, Anda harus
mengganti kacamata Anda dengan kacamata minus 3. Namun, Anda bersikukuh tak mau
mengganti kacamata minus 2 Anda. Apa yang terjadi? Anda merasa pusing apabila
melihat sesuatu. Inilah akibat yang timbul dikarenakan Anda mempertahankan
paradigma kacamata minus 2 Anda.
Apa ya paradigma Anda berkaitan dengan membaca buku? Mungkin ini:
"Wah, boring deh membaca buku yang tebal-tebal itu." Atau ini:
"Setiap kali membaca buku ilmiah, saya tentu ngantuk." "Saya
pilih nonton sinetron aja deh ketimbang baca buku. Baca buku bikin kepala cepat
botak!"
Itulah paradigma---atau kacamata yang Anda gunakan---dalam membaca buku.
Memang, tidak semua orang memandang aktivitas membaca buku ilmiah seperti itu.
Nah, tulisan ini akan mencoba membantu siapa saja yang merasa masih kesulitan
untuk memasuki dunia buku.
Menganggap Buku sebagai "Makanan"
Pertama-tama, untuk memasuki dunia buku, kita perlu mengubah paradigma
(atau kacamata) dalam memandang buku. Buku sama saja dengan makanan, yaitu
makanan untuk ruhani kita. Bayangkanlah apabila jasmani kita tidak diberi nasi,
telur, daging ayam, dan makanan bergizi tinggi lainnya. Apa yang akan terjadi?
Tubuh kita akan loyo dan sakit-sakitan.
Demikian jugalah yang terjadi dengan ruhani kita. Buku adalah salah satu
jenis "makanan ruhani" kita yang sangat bergizi. Mendengarkan
pengajian dan ceramah adalah juga sebentuk "makanan ruhani". Namun,
buku kadang memiliki gizi lebih dibandingkan dengan ceramah.
Lewat paradigma-baru membaca buku---dengan menganggap buku sebagai
makanan---kita dapat memperlakukan buku laiknya makanan kesukaan kita. Pertama,
agar membaca buku tidak lantas membuat kita ngantuk, maka pilihlah buku-buku
yang memang kita sukai, sebagaimana Anda memilih makanan yang Anda gemari.
Kedua, cicipilah "kelezatan" sebuah buku sebelum membaca semua
halaman. Anda dapat mengenali lebih dulu siapa pengarang buku tersebut. Atau
Anda bisa bertanya kepada seseorang yang menganjurkan Anda untuk membaca sebuah
buku (misalnya guru, orangtua, atau sahabat Anda). Mintalah kepada mereka untuk
menunjukkan lebih dulu hal-hal menarik yang ada di buku itu.
Ketiga, bacalah buku secara ngemil (sedikit demi sedikit, laiknya Anda
memakan kacang goreng). Apabila Anda bertemu dengan buku ilmiah setebal 300
halaman, ingatlah bahwa tidak semua halaman buku itu harus dibaca. Cari saja
halaman-halaman yang menarik dan bermanfaat. Anda dapat ngemil membaca di pagi
hari sebanyak 5 halaman. Nanti, di sore hari, tambah 10 halaman.
Manfaat Membaca Buku
Mengapa gizi sebuah buku melebihi ceramah atau hal-hal lain yang Anda
peroleh dari telinga (mendengar) dan mata (melihat) Anda? Sebab, hanya lewat
membaca bukulah kita mampu menumbuhkan saraf-saraf di kepala kita. Aktivitas
membaca buku menggabungkan banyak aktivitas penting lain.
Pertama, Anda perlu memusatkan perhatian agar sebuah teks yang Anda baca
dapat memberikan manfaat kepada Anda. Kedua, apabila Anda menemukan hal-hal
menarik dari sebuah buku, Anda dapat memberikan tanda (seperti menstabilo atau
memberikan catatan di pinggir-pinggir marjin buku).
Ketiga, sebuah kalimat yang menarik akan membuat saraf-saraf di otak Anda
bekerja secara efektif. Tiba-tiba saraf-saraf itu berhubungan dan membuat Anda
dapat menemukan sesuatu yang baru.
Dan, ini yang ajaib, membaca buku akan membuat Anda tetap berpikir! Seorang
peneliti dari Henry Ford Health System, bernama Dr. C. Edward Coffey,
membuktikan bahwa hanya dengan membaca buku seseorang akan terhindar dari
penyakit demensia.
Demensia adalah nama penyakit yang merusak jaringan otak. Apabila seseorang
terserang demensia, dapat dipastikan bahwa dia akan mengalami kepikunan atau
(dalam bahasa remaja disebut) "tulalit".
Menurut penelitian Coffey, pendidikan (salah satu pendidikan termudah
adalah membaca buku) dapat menciptakan semacam lapisan penyangga yang
melindungi dan mengganti-rugi perubahan otak. Hal itu dibuktikan dengan
meneliti struktur otak 320 orang berusia 66 tahun hingga 90 tahun yang tak
terkena demensia.
Membaca dengan Gaya SAVI
Apabila Anda sudah mengubah paradigma membaca buku Anda---bahwa membaca
buku seperti memakan pizza---dan sudah memahami manfaat membaca buku, cobalah
mulai membaca buku-buku ilmiah saat ini juga. Untuk mempermudah Anda dalam
membaca buku, di bawah ini saya sajikan tip-tip Dave Meier yang saya cuplik
dari buku-menariknya, The Accelerated Learning Handbook.
Meier menamai tip-tipnya ini "metode belajar gaya SAVI". SAVI
adalah singkatan dari Somatis (bersifat raga/tubuh), Auditori (bunyi), Visual
(gambar), dan Intelektual (merenungkan). Nah, silakan menggunakan Gaya SAVI
dalam membaca sebuah buku, sebagaimana petunjuk berikut.
Pertama, membaca secara Somatis. Ini berarti, pada saat Anda membaca,
cobalah Anda tidak hanya duduk. Berdiri atau berjalan-jalanlah saat membaca
buku. Gerakkan tubuh Anda saat membaca. Misalnya, setelah membaca 5 atau 7
halaman, berhentilah sejenak. Gerakkan tangan, kaki, dan kepala Anda. Setelah
itu, baca kembali buku Anda.
Kedua, membaca secara Auditori. Cobalah sesekali membaca dengan menyuarakan
apa yang Anda baca itu (dijaharkan). Lebih-lebih lagi apabila Anda menjumpai
kalimat-kalimat yang sulit dicerna. Insya Allah, telinga Anda akan membantu
mencernanya.
Ketiga, membaca secara Visual. Ini berkaitan dengan kemampuan dahsyat Anda
yang bernama imajinasi atau kekuatan membayangkan. Cobalah bayangkan saat Anda
membaca sebuah konsep atau gagasan. Kalau perlu gambarlah! Ini, insya Allah,
juga akan mempercepat pemahaman Anda.
Keempat, membaca secara Intelektual. Ini juga berkaitan dengan kemampuan
luar biasa Anda. Anda perlu jeda atau berhenti sejenak setelah membaca. Dan
renungkanlah manfaat yang Anda peroleh dari pembacaan Anda. Akan lebih bagus
apabila---saat Anda merenung itu---Anda juga mencatat hal-hal penting yang Anda
peroleh dari halaman-halaman sebuah buku. Insya Allah, Anda akan dimudahkan
dalam menuangkan atau menceritakan kembali apa-apa yang Anda baca. Selamat
membaca buku!***
Catatan: Tulisan ini pernah dimuat di majalah Sabili No.
26, Th. IX, edisi 27 Juni 2002/16 Rabiul Akhir 1423.
Yuk Menulis, Yuk!
Oleh : Herry Mohammad
DARI judulnya, MENGIKAT MAKNA, buku ini pastilah lain dari yang lain. Sudah
banyak buku-buku tentang teknik menulis yang lahir dari para pengarang ternama
di bumi pertiwi ini. Rata-rata bersemangat ketika memberikan kiat-kiatnya, baik
judul maupun isinya. Mengarang Itu Gampang (Arswendo Atmowiloto); Yuk, Menulis
Cerpen, Yuk (M. Diponegoro), Menggebrak Dunia Mengarang (Eka Budianta), adalah
beberapa contoh saja.
Bila buku-buku yang sudah ada di pasaran lebih banyak memberikan kiat-kiat
dalam menulis (cerpen, kolom, maupun buku), Mengikat Makna ini punya nilai plus
tersendiri. Setidak ada tiga nilai plus dari buku yang satu ini.
Pertama, buku ini punya daya dorong pada pembacanya agar bisa membaca
dengan memahami teks dan konteksnya. Jadi, tidak asal membaca saja. Tapi, lewat
kiat-kiatnya, penulis memberikan sentuhan: bagaimana bisa memahami buku yang
dibaca secara baik.
Kedua, pemahaman bacaan yang baik, lalu diresapkan, dan, seoptimal mungkin
bisa memberikan gizi pada kualitas intelektual sang pembaca. Dengan gizi yang
baik, sebuah buku akan bisa mengubah pola pikir dan pola tindak dari si
pembaca.
Ketiga, buku ini mencoba memprovokasi pembacanya. Para pembaca tidak hanya
didorong untuk bisa memahami dan mengubah pola pikir dan pola tindaknya, tapi
juga memprovokasinya untuk menulis buku.
Tiga hal tersebut sangat kentara dalam buku yang ditulis dengan cara yang
provokatif, penuh enerji, dan bergizi ini.
**
DALAM suatu kesempatan berdiskusi dengan para da'i --juru dakwah-- se Jawa
Timur, Oktober 1991, ada keluhan: ''Wah, menulis itu sulit, mas!''. Diskusi di
Masjid Al-Falah, Surabaya itu memang bertema ''Teknik Membuat Laporan'' yang
tentunya berkaitan dengan tulis-menulis.
''Lho, bukankah kalian ini pandai dan fasih berpidato?''
''Iya, namanya juga da'i. Tapi, ngomong dan nulis itu kan lain!'' jawab
sekitar 30-an da'i muda yang, menurut pengurus lembaga induknya, adalah
putra-putra terbaik dalam berdakwah di garis depan.
Para da'i sungguh fasih berdakwah, karena itu memang pekerjaannya. Tapi,
ketika diminta menuliskan laporan bulanannya --yang berupa aktivitas, problema,
dan penyelesaiannya-- tiba-tiba mereka jadi ''gagap''.
Tentu ada yang salah. Benar. Rupanya, mereka tak terbiasa menuangkan
ide-idenya dalam bentuk kata-kata, menyusun kalimat, dan menjadi satu gugusan
alinea. Padahal, para da'i itu adalah kelompok elit di lingkungannya.
Dia mendapatkan bahan-bahan ceramah, khotbah, dan pidatonya, dari
bahan-bahan bacaan, baik yang berupa buku, hadits, Al-Quran, Koran, maupun
fenomena alam dan sosial yang ada.
Kalau itu soalnya, sebenarnya mereka sudah punya modal. Tapi, modal saja
tidak cukup. Ia mesti punya keberanian untuk memulai. Kalau mau berdagang, ya
jangan takut kalau nantinya gagal dan merugi. Begitu pula dalam hal menulis.
Modal sudah ada, tinggal menuangkannya.
Dan menulis, ibarat belajar naik sepeda. Tak ada orang yang tiba-tiba saja
bisa mengendarai sepeda dengan mahir. Awalnya juga sempoyongan, menabrak pohon,
tembok, bahkan orang yang sedang berjalan. Lutut terluka. Belum sembuh, sudah
menabrak lagi. Luka lagi. Belum lagi kalau menabrak orang, dapat bonus:
bentakan, cacian, dan mungkin tempelengan alias bogem mentah!
Tradisi atau etos menulis itulah yang mesti ditumbuhkembangkan. Tapi, etos
itu baru bisa muncul ketika seseorang sudah faham benar dengan apa saja yang
pernah ia baca. Ingat, lho, dalam komunitas prismatik --masyarakat transisi
dalam terminologi ahli politik asal Amerika, Fred W. Rigg-- tak jarang orang
menenteng buku hanya supaya dipandang sebagai orang terpelajar.
Padahal, fungsi buku, adalah bagaimana ia mampu mempengaruhi orang-orang
yang membacanya. Kalau orang hanya sekedar membaca tapi tidak mengubah apa-apa
terhadap dirinya, ya, sama juga bohong. Artinya, orang tersebut tak faham
dengan apa yang dia baca. Membaca mesti bisa mempengaruhi dan atau mengubah
pola pikir dan pola tindak seseorang. Bila ia sudah menjadi pemabaca yang
''berhasil'', maka ia bisa maju selangkah lagi: berpotensi menjadi seorang
penulis.
Nah, dalam menulis itu tak ada teorinya. Yang ada adalah teknik. Ditambah
pengalaman dan kemauan yang terus menerus.
**
SEKARANG mari kita melihat nilai plus dalam menulis dibanding dengan budaya
oral dalam bentuk ceramah, khotbah, atau pidato.
Bila Anda berpidato --juga ceramah dan khotbah-- di depan podium, bisa jadi
ditonton dan didengar oleh puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang.
Tingkat efektivitas untuk mengubah pola pikir dan pola laku seseorang tidaklah
besar.
Orasi yang menggebu-nggebu misalnya, mungkin bisa ''membakar'', dalam
suasana yang penuh emosional, pada saat yang bersamaan. Tapi, ketika pulang ke
rumah masing, kembali dengan kesibukan masing-masing, dan segera akan
terlupakan. Tunggu orasi berikutnya, dan segera terlupakan kembali. Pesan lewat
oral nafasnya tidak panjang, sebatas jarak podium ke rumah.
Mau bukti? Lihatlah majelis-majelis taklim yang menyebar ke seantero
geografis dan masyarakat Indonesia itu. Majelis taklim, yang berupa pesan-pesan
moral tersebut, mestinya bisa mengubah pola pikira dan pola tindak jamaahnya.
Tapi apa yang Anda saksikan? Sifat-sifat yang berkaitan dengan nilai-nilai
luhur agama seakan tak membekas. Mengapa? Karena jamaah hanya ''menonton'' dan
''mendengar'' saja. Tak lebih dari itu. Yang lebih menyedihkan, begitu para
da'i, muballigh, atau orator tersebut meninggal, pesan-pesannya segera menghilang
dari peredaran. Inilah akibat tragis dari ilmu yang tidak didokumentasikan
dalam bentuk tulisan.
Berbeda dengan budaya tulis. Bila Anda menulis buku misalnya, maka karya
tersebut akan dibaca oleh puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan umat manusia.
Bisa jadi dibaca oleh generasi ke generasi.
Lihatlah karya-karya Al-Ghazali (1058-1111 M). Karya legendarisnya, ''Ihya
Ulumuddin'' dan ''Bidayatul Hidayah'', sampai sekarang dicari dan dibaca orang.
Karya-karya lainnya, yang jumlahnya mencapai 200-an, juga masih diterbitkan
oleh berbagai penerbit. Padahal, karya-karya tersebut ditulis pada abad 12.
Tengok pula pada pemikiran politik Islam klasik. Di pesantren-pesantren,
nama Al-Mawardi (974-1058 M) sangat terkenal. Ini karena buah pikirannya
tentang Administrasi Negara tertuang dalam buku ''Al-Ahkam al-Sulthaniyah''.
Dalam buku ini pula ia mengemukakan pikiran-pikirannya tentang idealnya seorang
kepala negara. Buku-buku tentang politik Islam yang ditulis orang di era
milenium ini, tak pernah bisa melupakan jasa Al-Mawardi.
**
SEKARANG, mari kita mulai melangkah, membiasakan menulis. Banyak cara untuk
memulainya.
Pertama, dengan memanfaatkan catatan harian. Apa saja kejadian, baik yang
dialami, dilihat, maupun di dengar, ditulis dalam catatan buku harian. Catatan
itu bisa pendek, bisa juga panjang. Bisa pula berupa renungan.
Catatan-catatan tersebut, suatu hari akan bermanfaat. Lihat misalnya
wartawan kawakan Rosihan Anwar. Dengan catatan-catatannya, ia bisa mengulas
masa lalu, kini, dan esok, dengan amat memukau. Ini terlihat dalam
tulisan-tulisannya yang menyebar di berbagai surat kabar dan majalah. Buku
catatan harian Kartini, Ahmad Wahib, dan Sio Hok Gie, adalah sekedar contoh.
Kedua, dalam bentuk surat-surat. Dengan surat, seseorang bisa menulis dengan
leluasa, bergaya bebas, dan bisa berimprovisasi. Surat menyurat ini,
sebagaimana buku catatan harian, bisa menjadi saksi sejarah. Lihatlah
''Surat-surat dari Endeh'', antara Soekarno dengan A. Hassan. Juga
''Surat-surat Kartini'', surat-surat Nurcholis Madjid dengan M. Roem, dan
sebagainya. Bahkan, surat-surat yang ditujukan dari berbagai kalangan
masyarakat yang ditujukan kepada Soeharto pun, pasca kelengserannya, sudah
dibukukan.
Lalu, untuk konsumsi majalah atau koran, berbagai tulisan bisa disesuaikan
dengan misi lembaga yang dituju. Tapi yang jelas, ada standarnya: berbagai
tulisan itu hendaknya merujuk dengan perkembangan berita yang ada. Juga halaman
yang tersedia. Kejelian membaca peluang, dari berbagai disiplin ilmu, pastilah
bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin guna menembus sekat-sekat yang ada di
majalah atau koran. Nah, selamat mencoba !** Bandung, Selasa, 28 Agustus 2001
Bila Sebuah Buku Demikian Bermutu….
Oleh : Anwar Holid
Tidak hanya lagu, buku pun kadang-kadang dirilis ulang. Tentu para penerbit
tidak sekadar ingin bernostalgia atau merindukan kembali masa lalu. Sebab ada
sesuatu yang berbeda ketika sebuah buku atau lagu diterbitkan ulang. Yang
berbeda itu adalah ruh atau nuansanya. Ruh ketika sesuatu yang lama dimunculkan
kembali ialah semacam pertaruhan apakah dia masih memiliki daya hidup atau
tidak.
Kita ingin merasakan yang berbeda apabila mendapati hal lama yang pernah
demikian mengisi ingatan kembali menyeruak mengisi kekinian. Kita berharap
mendapatkan energi baru, penyegaran kembali, dan nuansa baru yang dahulu
mungkin luput dari perhatian kita. Perhatikanlah misalnya lagu-lagu yang
dirilis ulang itu. Selain menawarkan kenangan, kondisi, dan semangatnya memang
berbeda. Sering itu dilakukan setelah mempertimbangan banyak hal.
Pertama yang mencolok tentu saja pembawanya (dalam hal ini: penerbit).
Harus diakui, yang membawakan kembali lagu lama biasanya mereka yang sangat
menyukai lagu itu. Jarang penyanyi asli
membawakan kembali lagu itu, meskipun bukannya tidak pernah terjadi. Artinya,
dia membawakan kembali sesuatu yang demikian berharga, hingga perlu dipelihara
nilainya, dan dipertahankan keindahannya. Semacam penghormatan kepada orang
yang menciptakannya. Dalam hal penerbitan, sama halnya. Kerap sebuah buku
diterbitkan ulang oleh penerbit lain (biasanya lebih muda), karena mereka
demikian terinspirasi oleh buku tersebut.
Kedua, penerbitan kembali buku lawas biasanya dipicu oleh kondisi tertentu
bahwa buku tersebut relevan dengan keadaan kini, atau mampu menerangkan
beberapa persoalan yang dianggap mencuat—buku tersebut memenuhi standar
keingintahuan saat itu. Ini menyangkut pertimbangan seberapa penting nilai buku
tersebut (di kalangan umum) apabila diterbitkan, akan memenuhi kebutuhan apa
saja buku tersebut, dan sebagainya.
Ketiga, ialah seberapa besar pasar masa kini akan mampu menyerap buku-buku
lawas yang dahulu pernah diterbitkan itu? Tentu saja pertimbangan ekonomi
sangat penting dalam menerbitkan kembali sebuah buku, baik yang ketika pertama
kali diterbitkan langsung menjadi besrt seller atau yang gagal di pasar. Untuk
kasus kedua itu, biasanya penerbit biasanya membuat semacam perbaikan (revisi),
apakah melalui penyuntingan kembali naskah dan isinya, memberikan kata
pengantar dari narasumber yang layak (prominent) atau sekadar melalui
penampilannya (minimal perubahan sampul).
Pertimbangan Lain
Bila sistem percetakan penerbit sudah bagus, mereka juga tidak segan-segan
untuk menerapkan sistem print-on-demand di bagian penjualan atau produksinya,
yakni kemampuan menyediakan buku-buku sesuai permintaan konsumen (pasar). Di
Indonesia, teknologi ini tergolong sangat langka, bahkan mungkin belum mampu
dilakukan, sebab masih banyak buku-buku lawas yang belum habis diserap pasar,
dan masih berusaha ditawarkan dengan berbagai cara, termasuk dengan rabat
setengah harga produksinya! Menurut prakiraan, sistem print-on-demand
memungkinkan penerbit masih mampu mendapatkan untung meskipun buku tersebut
hanya dipesan satu buah saja oleh pembeli.
Buku-buku yang kerap dilupakan orang kadang-kadang juga mendapat perhatian
dari penerbit, hingga kemudian mereka memutuskan menerbitkannya kembali. Seri
Penguin Classics atau Bantam Classics adalah contoh buku-buku lama yang diterbitkan karena judul itu sudah sukar
ditemukan di pasar. Di Indonesia, penerbitan kembali buku Islam dan Keturunan
Arab atau Partai Politik di Pentas Nasional oleh Mizan bisa dianggap sebagai
respons positif atas buku klasik yang mulai sukar didapat di pasar—sebab
penerbit pertamanya tidak menerbitkan kembali buku itu.
Meskipun pengorbanan harus diberikan dan risiko harus ditempuh oleh
penerbit yang mau memunculkan kembali buku lama, kita tentu harus berterima
kasih untuk beberapa hal. Pertama ialah penerbitan itu akan mengekalkan ingatan
kita bahwa buku-buku itu telah membantu dengan cara yang sangat bermakna
tentang cara memahami peradaban dan kebudayaan manusia.
Kedua, sumberdaya buku (naskah) itu kadang-kadang sangat sukar ditemukan.
Anda tentu akan sangat bisa merasakan betapa bahagianya seandainya seluruh
manuskrip buku Pramudya Ananta Toer, Gadis Pantai, yang lenyap oleh
keberingasan rezim Orde Baru, bisa diterbitkan ulang—tidak hanya sebagiannya.
Dalam keadaan yang sangat terdesak, kita selalu baru akan bisa merasakan
betapa berartinya sesuatu yang lenyap di dalam diri dan ingatan kita. Sering
sebuah buku baru bisa diterbitkan kembali setelah naskah aslinya ditemukan di
tumpukan buku-buku bekas yang nyaris hancur. Atau atas pertolongan pembaca yang
dengan apik merawat buku tersebut. Bila itu yang terjadi, kita tidak saja
berutang pada penulis, penerbit, atau penemu naskah itu. Kita agaknya harus
pula berterima kasih kepada Alam yang menjaga manuskrip itu tetap utuh dan
diselami makna-maknanya. Mungkin untuk mengabadikan nilai luhur itu pula,
sebuah penerbit, Hikmah, berani kembali menerbitkan naskah-naskah lama seperti
Surat-surat Al-Ghazali karya Abdul Qayyum.
Jadi sidang pembaca, buku lama belum tentu kehilangan nilainya. Sebab
seperti kata pepatah: tidak ada buku lama, yang ada adalah buku yang belum kita
baca.[]
Label:
OPINI







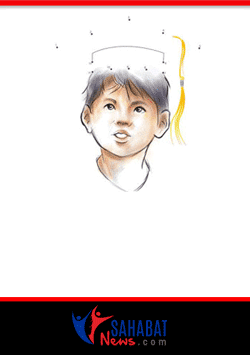
.jpg)








